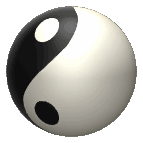PRINSIP-PRINSIP ILMU TASAWUF (MYSTICISM TEORITIS)
PRINSIP-PRINSIP ILMU TASAWUF (MYSTICISM TEORITIS)‘Irfân (mistisisme) secara etimologis berarti sejenis pengetahuan (makrifat), konsepsi (tashawwur), dan pengetahuan yang dalam (bashîrah). Sementara itu, secara terminologis, ‘irfân dapat dikatakan sebagai sejenis pengetahuan langsung yang berada di luar indera dan akal. Tidak mudah mencapai pengetahuan itu, kecuali bagi orang yang secara amaliah bersungguh-sungguh menghilangkan berbagai rintangan dan tabir-tabir hati melalui sejenis perjalanan spiritual (sulûk) atau tarikan Ilahi (jadzb). Dengan cara itu, seorang arif dapat mencapai batin, kegaiban, dan kesatuan sejati yang tersembunyi di balik hal-hal yang tampak dan kemajemukan (katsrah). Dalam sulûk ini terdapat perjalanan ruh yang mendatangkan kesempurnaan jiwa serta diperoleh pengenalan diri dan pencerahan batin.
Untuk menjelaskan makna ‘irfân secara lebih dalam dan penjelasan berbagai dimensi dan aspeknya, kita harus membagi bangunan ‘irfân ini ke dalam beberapa bagian. Bagian-bagian itu sebagai berikut:
1. ‘Irfân bisa berarti idrâk (persepsi), yakni makrifat langsung tanpa melalui perantaraan dari akar ilmu hudhûrî (ilmu pemberian Ilahi) dan yang dimasuki seorang arif ketika berhadapan langsung dengan jiwa hakiki dan ilmu kesatuan (wahdah). Demikian pula batin atau kegaiban alam.
2. ‘Irfân bisa berarti sejenis pandangan (nazhrah) atau penglihatan (ru’yah). Berdasarkan hal ini, ‘irfân membahas bentuk kajian yang diformulasi dan batiniah yang didasarkan pada penakwilan terhadap nash-nash agama atau pengaruh-pengaruh etika di dalam tema al-qirâ’ah al-‘irfâniyyah (kajian mistisisme). Ketika itu, ‘irfân dapat digunakan dalam berbagai kajian lain, seperti kajian-kajian filsafat, fiqih, dan kalam.
3. ‘Irfân bisa berarti uslûb (metode). Dalam hal ini, ‘irfân terbatas dalam lingkup alamiah, yang berarti sejenis sulûk dan jalan kehidupan yang membawa satu individu cenderung untuk keluar dari kemapanan secara ilmiah, amaliah, dan etis. Tindakan itu berbeda dengan kebiasaan sehari-hari, keinginan hawa nafsu, dan kecenderungan diri karena keinginan untuk sampai pada hakikat kegaiban yang tersembunyi di balik tabir-tabir lahiriah.
4. ‘Irfân bisa berarti kumpulan berbagai ajaran yang termuat di dalam buku-buku dan ucapan-ucapan khusus para arif (dalam dimensi teoretis dan praktisnya), karena tujuannya adalah menjelaskan jalan sulûk.
5. ‘Irfân bisa berarti institusi sejarah. Eksistensi dan manifestasi eksternal dan sosial kelompok ini dalam Islam direpresentasikan dalam kelompok sufi yang memiliki banyak hubungan dan interaksi dengan kelompok-kelompok sosial dan keagamaan yang lain.
Dari aspek sejarah, istilah ‘irfân sudah dikenal sejak permulaan dalam kata yang lain, seperti ahli makrifat dan ahli tasawuf yang berporos pada makna ketiga (yang telah disebutkan di atas). Setelah itu, kata tersebut mengambil makna kedua, keempat, dan kelima, lalu kembali pada makna pertama. Adapun yang dijadikan sandaran buku kami ini adalah dimensi teoretis dari makna keempat, yakni ‘irfân dalam arti kumpulan berbagai ajaran. Kajiannya telah dilakukan berdasarkan asumsi bahwa hal itu merupakan warisan ruhaniah dari kebudayaan Islam dengan nama khusus yaitu ‘irfân nazharî (mistisisme teoretis) menurut berbagai pandangan dan didasarkan pada seni prosa dan puisi dalam cakupan istilah-istilah seni atau kata-kata dan makna-makna simbolik.[1]
Prinsip-prinsip Kolektif Metode Mistisisme
Setelah mendalami mistisisme dan berbagai dimensinya, untuk memahami makrifat atau cabangnya dalam bentuk mistis harus didasarkan pada beberapa pilar berikut.
1. Keyakinan terhadap adanya tingkatan-tingkatan alam eksistensi. Para peneliti mistisisme mengatakan bahwa mereka telah melewati aspek-aspek lahiriah, penglihatan biasa terhadap alam ini, dan masuk ke dalam aspek-aspek batiniah.
2. Keyakinan terhadap adanya tingkatan-tingkatan persepsi dan pemahaman seseorang, padahal tidak mungkin menganggap pengetahuan inderawi lahiriah, bahkan pengetahuan rasional, sebagai pengetahuan mistisisme. Tetapi pengetahuan itu termasuk sejumlah pengetahuan superfisial (disebabkan ketidakmampuan akal untuk mengetahui berbagai hakikat tertinggi dari alam ini). Jalan satu-satunya untuk mencapai hakikat-hakikat teologis dari alam ini adalah ilmu hudhûrî dan syuhûdî, dan yang terdiri dari berbagai tingkatan dan fase.
3. Keyakinan terhadap adanya tingkatan-tingkatan manusia, karena biasanya seorang arif mempercayai adanya persamaan antara manusia dan alam ini, dan kaitan pengetahuan manusia dengan alam sebagai perantaraan di antara kedua unsur tersebut. Berdasarkan hal ini, seseorang juga dapat memiliki tingkatan-tingkatan yang terdapat di alam ini, dimana ia dapat naik dan berkembang melalui perjalanannya di jalan mistis, di samping mencapai pengetahuan-pengetahuan mistis berkenaan dengan keutamaan dan tingkatan karakter mistis (maqâmât).
4. Tingkatan-tingkatan, keadaan-keadaan, dan pengetahuan-pengetahuan itu seluruhnya faktual, dimana tindakan-tindakan mulia dari semua kelompok mistis dianggap sebagai penegasan dan perincian tentang hakikat alam, bukan semata-mata simbol-simbol intelektual atau hal-hal yang bersifat imajinatif, di samping adanya prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas pada kelompok-kelompok mistis (baik yang bersifat keagamaan maupun yang tidak bersifat keagamaan). Namun, ada prinsip lain yang dapat ditemukan dalam mistisisme agama, misalnya:
5. Kesakralan dan kesucian pemikiran. Sebab, tingkatan-tingkatan dan keadaan-keadaan mistis berarti hubungannya dengan Allah Swt. (karena hal itu dianggap sebagai sesuatu yang berkaitan dengan makrifat, cinta [mahabbah], takut [khauf], dan harapan [rajâ’]). Bisa juga ditambahkan dua prinsip ke dalam prinsip-prinsip tersebut dalam mistisisme Islam. Kedua prinsip itu adalah:
6. Penyandaran pada ilmu tentang nama-nama sebagai landasan. Setelah ini, akan kami kemukakan permulaan dan perkembangan mistisisme Islam yang didasarkan pada nama-nama Ilahi, baik yang berkaitan dengan ontologi (‘ilm al-wujûd) atau epistemologi (‘ilm al-ma‘rifah) maupun yang berkaitan dengan aspek praktis (dalam hal khusus pada aspek peniruan akhlak Allah Swt.).
7. Penyandaran pada tingkatan-tingkatan Al-Quran. Sebab, dapat dikatakan bahwa mistisisme Islam merepresentasikan makna-makna batiniah ayat-ayat Al-Quran dan tingkatan-tingkatan internalnya. Untuk mengetahui makna-makna batiniah itu diharuskan menempuh tingkatan-tingkatan eksistensi dan manusia yang analog dengan batiniah Al-Quran.
Tidak diragukan, bahwa kesamaan tingkatan-tingkatan kitab tadwînî (Al-Quran) dengan kitab takwînî (alam eksistensi), dan juga dengan kitab anfusî (eksistensi) manusia merupakan bagian dari kesitimewaan-keistimewaan mistisisme Islam.
Jalan menuju mistisisme Islam yang di dalamnya terkandung perjalanan menempuh tingkatan-tingkatan tersebut dan kesampaian ke tingkatan-tingkatan (maqâmât) dan setasiun-setasiun (manâzil) mistis yang tinggi dinamakan wilâyah yang—melalui kendaraan mahabbah dan ‘isyq atau riyâdhah dan penguasan nafsu—di dalamnya terkandung perjalanan-perjalanan seorang arif (wali) dalam nama-nama Ilahi dan kefanaannya di dalam nama-nama Allah terindah (al-asmâ’ al-husnâ). Selanjutnya, adalah hubungan dan keabadiannya dalam hakikat-hakikat nama-nama tersebut.
Mistisisme Teoretis dan Praktis
Istilah mistisisme teoretis (‘irfân nazharî) digunakan untuk menyebut sekumpulan pemikiran mistis yang objek-objeknya berporos di seputar Esensi (Dzât) Al-Haqq Swt. dan semua manifestasinya—yakni nama-nama, sifat-sifat dan aktivitas-aktivitas-Nya. Dengan kata lain, Dzât sebagai salah satu determinasi (ta‘yyun).
Sementara itu, Al-Qaishari mendefisikan mistisisme (‘irfân)—teoretis dan praktis—dengan menganggapnya sebagai ilmu yang mengandung suatu objek, masalah, dan faedah, dengan definisi berikut:
“Pengetahuan tentang Allah Swt. berkenaan dengan nama-nama, sifat-sifat, aktivitas-aktivitas, dan manifestasi-manifestasi-Nya, keadaan-keadaan mabda’ (tempat bermula) dan ma‘âd (tempat kembali), hakikat-hakikat alam semesta dan metode kembalinya ke satu hakikat yakni Esensi Ketunggalan (Dzât Ahadiyyah), serta mengetahui sulûk dan mujâhadah untuk membebaskan diri dari belenggu parsial dan hubungannya dengan tempat bermulanya serta memiliki sifat kemutlakan dan keuniversalan.”[2]
Berdasarkan asas ini, kita dapat mendeskripsikan masalah-masalah mistisisme sebagai berikut.
1. Sifat keberadaan kemajemukan (katsrah) (hubungan alam semesta ini dengan Al-Haqq dan perjalanan turunnya).
2. Penjelasan manifestasi nama-nama dan sifat-sifat.
3. Penjelasan metode kembalinya kemajemukan (katsrah) ke kesatuan (wahdah) (perjalanan naik alam semesta).
4. Metode kembali (sulûk), dimana yang terakhir ini berkaitan dengan mistisisme praktis (‘irfân amalî).
Atas dasar hal ini, “masalah-masalah” tersebut berarti manifestasi-manifestasi dan hukum-hukum khusus bagi Al-Haqq Swt. dan juga nama-nama, sifat-sifat, dan aktivitas-aktivitas-Nya. Dengan kata lain, yang terpenting dari dua masalah yang dikemukakan dalam mistisisme adalah:
1. Apakah tauhid itu? (Kajian-kajian tentang kesatuan eksistensi dan turunan-turunannya).
2. Siapakah yang diesakan itu? (Meliputi kajian-kajian tentang manusia paripurna atau insan kamil dan hal-hal yang berkaitan dengannya).
Bagian pertama mencakup dua kajian; (1) penegasan keesaan (wahdah) dan (2) penjelasan tentang kemajemukan (katsrah). Tujuannya adalah mengetahui Al-Haqq dan menyandarkan metodenya pada penyingkapan-batin oleh para arif (urafa), teks-teks wahyu Ilahi, dan hadis-hadis dari orang-orang maksum, di samping dalil-dalil akal untuk membuktikan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh melalui pengetahuan yang muncul dalam hati (wijdâniyyah) dan penyingkapan-batin (kasyfiyyah). Kemudian, penjelasan tentang pandangan mistis yang komprehensif dan jawaban terhadap hal-hal yang meragukan yang berkaitan dengannya.
Objek-objek mistisisme teoretis atau pandangan mistis yang komprehensif dan masalah-malahnya bisa meliputi lima bagian pokok, yaitu sebagai berikut.
1. teori pengetahuan mistis (kajian-kajian pendahuluan).
2. ilmu tentang eksistensi mistis.
3. ilmu tentang pengetahuan mistis tentang Allah.
4. ilmu tentang pengetahuan mistis tentang alam.
5. ilmu tentang pengetahuan mistis tentang manusia.
Adapun mistisisme praktis adalah perjalanan melewati fase-fase kesempurnaan manusia yang sesuai dengan metode khusus dengan harapan untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah Swt. dan mencapai makrifat Ilahi, lalu tingkatan kewalian (wilâyah) tertinggi (tingkatan haqq al-yaqîn dan kesatuan dari kesatuan [jam‘ al-jam‘]).
Mistisisme Islam pada dua abad permulaan kemunculan Islam terbatas pada mistisisme teoretis dan jalan-jalan kehidupan mistis (dan hal itu melalui dua cara, yaitu kezuhudan dan cinta [hubb] atau ‘isyq). Kemudian—setelah menggabungkan antara tindakan-tindakan mulia para arif dalam makrifat dalam lingkup sekumpulan pemikiran mereka yang tertulis dan buku-buku mereka—dapat tersebar.
Pada saat urafa pengamal (‘amaliyyûn)—jika boleh dikatakan begitu—hanya memiliki hati yang bersih dan niat yang tulus dalam amal-amal mereka yang memulai dua unsur asasi ini merupakan modal satu-satunya bagi mereka selama mereka menempuh fase-fase spiritual. Sebab, bangunan mistisisme teoretis berkenaan dengan pengajaran dan pembelajaran, berdiri di atas sejumlah ilmu; mulanya adalah logika (manthiq), filsafat, dan teologi (kalâm), dan selanjutnya adalah keakraban dengan ucapan-ucapan para arif, penyingkapan-batin mereka, dan tindakan mulia mereka. Berdasarkan hal ini, mistisisme teoretis menyerupai filsafat pertama, walaupun ada perbedaan esensial di antara keduanya. Betapa indah apa yang dikatakan oleh Muthahhari dalam masalah ini:
“’Irfân dengan sifatnya ini menyerupai filsafat Ilahi, karena melakukan penafsiran dan penjelasan tentang eksistensi (wujûd). Namun, sementara argumentasi filsafat didasarkan pada prinsip-prinsip akal semata, maka argumentasi ‘irfân didasarkan pada prinsip-prinsip penyingkapan-batin (kasyf)—seperti yang dikatakan—dan setelah itu dijelaskan dengan bahasa akal; sementara argumentasi akal dalam filsafat adalah dalam bentuk objek-objek yang ditulis dengan suatu bahasa dan dikaji dengan bahasa yang sama, maka argumentasi ‘irfân adalah dalam bentuk objek-objek yang diterjemahkan dari bahasa lain, dalam arti seorang arif—setidaknya, menurut pengakuannya—menjelaskan apa yang disaksikan dengan hati dan kesempurnaan eksistensinya dengan bahasa akal.”[3]
Adapun mengenai perbedaan antara mistisisme teoretis dan ilmu-ilmu humaniora yang lain dapat dikemukakan sebagai berikut.
“Menurut temanya, yaitu membahas tentang falsafah hakikat eksistensi: tema teologi (kalâm) adakah prinsip-prinsip akidah, sedangkan temak ‘irfân adalah Esensi Al-Haqq di smaping salah satu determinasi (ta‘ayyun).
Menurut metodenya, yaitu mengikuti metode filsafat akal, metode teologi adalah metode akal (‘aqlî) dan syariat (naqlî), dan kadang-kadang juga didasarkan pada metode lain, sedangkan metode ‘irfân adalah metode akal dan penyingkapan-batin, dan kadang-kadang didasarkan pada dalil syariat (naqlî).
Menurut tujuannya, tujuan filsafat adalah mengetahui hukum-hukum eksistensi, turunan-turunannya, dan macam-macamnya; tujuan teologi adalah penegasan prinsip-prinsip akidah; sedangkan tujuan ‘irfân adalah mengenal nama-nama dan sifat-sifat Al-Haqq, serta aspek-aspek batin dan gaib dari alam ini.
Dalam menegaskan pandangan Mulla ‘Abdurrazzaq Al-Lahiji[4], Haji Mulla Hadi Al-Sabziwari membagi para pencari pengetahuan hakikat segala sesuatu pada empat kelompok, sebagai berikut.
Kelompok pertama, mereka dalah kaum teolog (mutakallim), dan pada umumnya bekerja dengan menyelaraskan pandangan-pandangan mereka dengan lahiriah syariat.
Kelompok kedua, mereka adalah kaum sufi, dan mereka tidak menyelesaraskan pandangan-pandangan mereka dengan syariat, tetapi mereka membatasi diri pada kesungguhan melawan nafsu dan menyucikan batin.
Kelompok ketiga, mereka adalah kaum peripatetik (masysyâ’ûn) yang kegiatan mereka terbatas pada pemikiran, penjelasan dan dalil akal semata.
Kelompok keempat, kaum illuminis (isyrâqiyyûn) yang menggabungkan kedua metode ini.[5]
Al-Sabziwari memandang bahwa kelompok terakhir adalah yang diliputi pertolongan Al-Haqq, yang mendorongnya untuk mengklasifikasikan Mulla Shadra, penulis buku Al-Hikmah Al-Muta‘âliyyah, dan metodenya ke dalam kaum illuminis.[6]
Adapun hal yang berkaitan dengan sebab dan motif yang mendorong penulisan mistisisme teoretis (‘irfân nazharî) pada abad ke-3 H dan sesudahnya, dan yang semangatnya sampai pada abad ke-7 di tangan Muhyiyuddin bin ‘Arabi, maka dapat kami tunjukkan melalui beberapa butir berikut.
1. Motif pengetahuan (makrifat), dimana seseorang merasakan kebutuhan untuk menyelaraskan antara berbagai dimensi eksistensi dan persepsinya—yakni hati, akal, dan pengalaman—yang mendorongnya untuk menulis tafsir yang komprehensif-rasional dan sedapat mungkin mengharmoniskan pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh melalui cita-rasa ruhaniah (ma‘ârif dzauqiyyah) dan hakikat-hakikat yang diperoleh melalui penyaksian-batin (haqâ’iq syuhûdiyyah)-nya.
2. Menghindarkan kontradiksi. Seperti kita ketahui, perbedaan dalam pengungkapan oleh para arif, dan yang kadang-kadang menyebabkan pertentangan secara lahiriah, disebabkan oleh perbedaan tingkatan (manzilah), pengalaman spiritual, dan kapasitas eksistensial mereka. Inilah di antaranya yang memberikan kesan mereka di mata orang lain bahwa mereka saling bertentangan di antara mereka sendiri dan bahwa ucapan mereka tidak berdasar.
3. Tuduhan terhadap pemikiran. Beberapa hal, baik ungkapan maupun ucapan ekstatik (syathahât), disebabkan oleh kekurangan dalam pengalaman atau dalam menerjemahkan ilmu hudhûrî ke dalam ilmu hushûlî secara keliru, dan yang menyebabkan pertentangan dengan lahiriah syariat. Keadaan-keadaan itu disebabkan oleh pemahaman yang buruk terhadap hal-hal yang disyariatkan.
4. Kekhawatiran akan kehilangan makna. Sebab, keasingan dalam pengalaman mistis, dan selanjutnya adalah kesulitan dalam mengambil pemahaman-pemahaman yang sesuai dengan pengetahuan yang muncul dalam hati (wijdâniyyah), dan akhirnya adalah ketidakmampuan kata-kata dan ungkapan untuk menjelaskan hakikat-hakikat yang diperoleh melalui penyaksian (haqâ’iq syuhûdiyyah), semua itu menyebabkan keraguan akan kehilangan makna dari pengetahuan yang diperoleh dari penyaksian-batin dan kekhawatiran akan kebutuhan pengetahuan yang diperoleh oleh para arif pada makna yang dimaksud. Perlu ditunjukkan bahwa sebagian besar keraguan ini muncul dari sebagian filosof dan mutakallim atau ahli hadis.
Dalam menjelaskan alasan keperluan pada ilmu mistis (‘irfân) dan mengapa dia menulis risalah yang terkenal tentang masalah tersebut, Al-Qaishari berkata:
“Walaupun asas dan pilar ilmu ini adalah cita-rasa spiritual (dzauq), dan siapa pun tidak mampu menggunakannya selain orang-orang yang memiliki wajd (ekstase) dan ahli syuhûd, tetapi saya menemukan bahwa ahli ilmu-ilmu lahiriah mengira bahwa ilmu ini tidak memiliki landasan yang kokoh serta kesimpulan yang bijaksana dan baik, dan bahwa hal itu adalah khayalan semata-mata yang tidak memiliki dalil dan bukti, atau hanya pengakuan adanya penyingkapan-batin (mukâsyafah) dan makrifat yang dibuat-buat dimana orang yang mengaku memilikinya juga tidak bisa memahaminya. Oleh karena itu, saya ingin menjelaskan subjek ilmu ini serta berbagai masalah, prinsip-prinsip dan ajaran-ajarannya, lalu menuliskannya dalam risalah ini.”[7]
Kemudian, Al-Qushairi menambahkan:
“Dalam risalah ini saya tidak menyebutkan burhan atau dalil apapun kecuali untuk menjadi pegangan mereka (yakni ahli ilmu-ilmu lahiriah) dan dengan perantaraan ilmu-ilmu mereka sendiri. Hal itu karena penyingkapan-batin ahli syuhûd tidak dipandang sebagai hujjah apapun bagi mereka. Oleh karena itu, mereka cenderung untuk menakwilkan lahiriah ayat-ayat dan hadis-hadis yang juga menunjukkan kandungan-kandungan mistis.”[8]
5. Kepentingan pengajaran. Artinya, keharusan membimbing para penuntut ilmu dan memberitahukan kepada mereka apa yang akan mereka dapatkan dari bimbingan itu, serta apa yang akan mereka peroleh melalui penyingkapan-batin (mukâsyafah), manifestasi (tajalliyyât), dan penyaksian-batin (musyâhadât). Kemudian, penting dijelaskan akidah-akidah dan pengetahuan tentangnya untuk menghindari mereka dari salah menggunakan ungkapan-ungkapan yang dimaksud dan penakwilan-penakwilan yang tidak dikehendaki. Semua itu merupakan faktor lain di samping faktor-faktor yang karenanya diputuskan untuk menuliskan mistisisme teoretis (‘irfân nazharî) ini. Berkenaan dengan hal yang berkaitan dengan faedah-faedah ilmu teoretis untuk mendapatkan makrifat dan tidak bertentangan dengan usaha untuk mendapatkan pengetahuan dan karakter kognitif (al-malakât al-idrâkiyyah) dengan mengosongkan hati dari segala sesuatu, Sha’inuddin berkata, “Tidak ada keraguan sedikit pun terhadap ucapan ini. Tetapi keraguan terletak pada anggapan mereka bahwa ilmu-ilmu teoretis (al-‘ulûm al-nazhariyyah) dapat mengantarkan pada tujuan atau menilainya sebagai sesuatu yang harus dimiliki dalam perjalanan spiritual (sulûk) dan kebutuhan sulûk terhadapnya. Sementara itu, jika mereka tidak menganggap bahwa hal itu bukan suatu halangan atau hanya memandangnya sebagai suatu alat bantu, maka dalam hal ini, ilmu-ilmu tersebut dapat digunakan. Mereka benar, yaitu apa yang dikatakan oleh penulis Tamhîd Al-Qawâ‘id, ‘Sesungguhnya menyiapkan tempat yang sakral dengan gerakan-gerakan pemikiran yang dilandasi kerinduan bukanlah suatu halangan, bahkan berguna dalam menyingkap pengetahuan-pengetahuan dan himah-hikmah yang tersembunyi ketika kekuatan kudus mengalahkan kekuatan-kekuatan jasmani dan penguasaannya yang terus-menerus terhadap kekuatan keraguan (wahm) dan kekuatan imajinasi (mutakhayyilah)…’”[9]
Sebagian orang yang memberikan komentar (syarah) terhadap buku Tamhîd Al-Qawâ‘id menganggap bahwa mencari dan mempelajari ilmu-ilmu seperti itu merupakan suatu hal yang diperlukan. Mereka berkata, “Karena jalan sulûk itu sulit, maka pesuluk (penempuh jalan spiritual) harus mempelajari kaidah-kaidah akal yang dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah dan memisahkan antara setasiun spiritual (manzil) dan jalan spiritual (tharîq) sebelum dia bertekad untuk masuk ke jalan ini agar terhindar dari kejatuhan ke dalam jurang keraguan. Itu artinya, jalan yang ditempuh memerlukan metode pembuktian (burhân).”[10]
Demikianlah, faktor-faktor yang telah disebutkan itu, di samping pencarian dengan bahasa umum atau dengan bahasa yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka, membantu dalam memunculkan dan menuliskan mistisisme teoretis.
Penting disebutkan di sini bahwa mistisisme teoretis tidak memiliki metode khusus hingga kemunculan Ibn ‘Arabi, dan ketika itu hanya terbatas pada ucapan-ucapan para syaikh, perkataan ringkas mereka, dan ucapan ekstatik mereka yang tertuang di dalam puisi dan prosa, atau penakwilan-penakwilan yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Saw. Itulah yang kita saksikan menjadi kekhususan dalam ucapan para arif, seperti Al-Hallaj, Khwajah ‘Abdullah Al-Anshari, Ibn Junaid,[11] Sahl Al-Tustari, Abu Thalib Al-Makki, Al-Tirmidzi, Ahmad Al-Ghazali, ‘Ain Al-Qudah, ‘Aththar,[12] dan Najmuddin Kubra. Namun, setelah kemunculan Muhyiyuddin bin ‘Arabi (wafat 638 H/1240 M), prinsip-prinsip pemikiran yang tersebar itu menjadi tersusun, harmonis, dan koheren, serta berada dalam bentuk pandangan komprehensif dan metode pemikiran yang harmonis dalam memahami hakikat-hakikat alam semesta dan mendalami pengetahuan-pengetahuan Islam dengan menganggapnya sebagai pengganti atau penyempurna terhadap pemikiran-pemikiran filsafat dan kalam (teologi). Demikianlah, setelah Muhyiyuddin bin ‘Arabi, mistisisme teoretis dapat membubuhkan stempelnya pada kebanyakan arif, mazhab, aliran, dan jalan para sufi, di samping bagi para hukama dan para filosof, bahkan para mutakallim dan mufasir. Istilah-istilahnya, kaidah-kaidah komprehensifnya, metode penakwilannya terhadap teks-teks agama, dan pengalaman-pengalaman mistisnya dapat mempengaruhi mereka semua sedemikian rupa bersama buku Al-Hikmah Al-Muta‘âliyah karya Shadr Al-Muta’allihin Al-Sirazi (wafat 1050 H/1640 M)—seperti dikatakan, merupakan hasil gabungan antara burhan, mistisisme dan Al-Quran, dapat menjadikan buku itu satu-satunya metode filsafat yang paling sempurna di dunia Islam. Dalam buku Al-Hikmah Al-Muta‘âliyah sendiri, penulisnya sangat terpengaruh oleh pandangan-pandangan dan keyakinan-keyakinan Ibn ‘Arabi setelah berlalu empat abad dari wafatnya sang sufi agung itu. Bahkan, Shadr Al-Muta’allihin bersungguh-sungguh untuk memberikan penjelasan yang rasional terhadap bagian-bagian yang tidak mampu ditemukan pembenaran rasionalnya oleh Ibn ‘Arabi yang dianggapnya sebagai perkara mustahil. Dengan demikian, mistisisme teoretis—terutama yang disebutkan dalam buku-buku karya Ibn ‘Arabi dan orang-orang yang mengikuti jejaknya, seperti Al-Qunawi,[13] ‘Abdurrazzaq Al-Kasyani, Al-Qushairi, Ibn Finari, Ibn Turkah, Jami, Al-Syabastari, Al-Lahiji, dan Sayid Haidar Al-Amuli—masih menjadi referensi utama dan satu-satunya untuk menjelaskan pandangan mistis yang universal dalam metode klasik, pengajaran mistisisme teoretis, dan kajian-kajian yang khusus berkatian dengannya.
Berikutnya adalah kajian seputar universalitas tersebut, yaitu yang menjadi hasil dari kerja keras penulis. Metode yang digunakan dalam kajian-kajian tersebut—menurut apa yang telah dikemukakan sebelum ini—terdiri dari lima bagian. Kami akan membahas bagian-bagian tersebut yang berkaitan dengan mazhab mistisisme teoretis. Lima bagian itu adalah sebagai berikut.
1. prinsip ilmu makrifat.
2. prinsip-prinsip ontologi (‘ilm al-wujûd).
3. prinsip-prinsip makrifat tentang Allah Swt.
4. prinsip-prinsip pengetahuan tentang alam semesta.
5. prinsip-prinsip pengetahuan tentang manusia.
Asal dan Perkembangan Mistisisme Teoretis dalam Islam
Meskipun sebagian orientalis menganggap pengaruh agama-agama Timur dan ajaran-ajarannya yang ada di India atau mistisisme Neo-Platonisme merupakan faktor terpenting dari awal kemunculan tasawuf, tetapi pertanyaan berikutnya yang muncul adalah: dengan adanya sumber-sumber tersebut (yakni Al-Quran, Sunnah, dan doa-doa dalam Islam), apakah kita dibenarkan untuk mengkaji sumber-sumber lain dari luar selain sumber-sumber tersebut? Atau, seperti dikatakan oleh George Jordack, bukankah mengherankan tempat kita menemukan seseorang yang sedang duduk di tepi sungai atau di tepi pantai, lalu kita berkata, “Dari kolam yang mana orang ini akan mengisi embernya?” sambil berpura-pura tidak tahu bahwa sungai atau lautan di sana.
Demikian pula dengan masalah yang kita bahas ini. Sebab, terlebih dahulu kita harus memastikan tempat adanya kolam. Inilah yang diklaim oleh ahli makrifat, bahwa pengetahuan mereka hanyalah refleksi dari Al-Quran, makna-makna lahiriah dan batiniah Al-Quran dan riwayat-riwayat yang dikutip dari sumber-sumber yang maksum (para imam as.), dan pengalaman-pengalaman mistis mereka yang bernilai. Jika memang ada faktor-faktor lain seperti universalitas, rasionalitas, dan alamiah dalam semua agama, seperti Kristen, Brahma, Yahudi, dan Islam, hal itu karena mistisisme berlandaskan pada asas-asas yang kekuatannya bersumber dari ilham Ilahi di samping adanya faktor kolektif di antara agama-agama tersebut yang muncul dalam sumber limpahan anugerah Ilahi yang menjadi sandarannya. Bagaimanapun keadaannya, para arif Muslim memandang Al-Quran dan Sunnah sebagai dua faktor penting bagi pengetahuan mistis, bahkan merupakan pendukung dan dalil terhadap pandangan universalitas dan metode kehidupan dan sulûk mereka, di samping pengalaman-pengalaman mistis yang khusus bagi mereka.
1. Al-Quran
Sebagai contoh, dapat kami sebutkan beberapa ayat berikut:
1.
1. Ayat-ayat yang berisi tentang sifat-sifat Allah Swt., seperti Mahaawal (Al-Awwal), Mahaakhir (Al-Akhîr), Mahalahir (Al-Zhâhir), dan Mahabatin (Al-Bâthin), serta seluruhnya menunjukkan keesaan Tuhan yang mutlak.[14]
2. Ayat-ayat yang menyebut Allah sebagai Cahaya (Nûr)[15] dan berbicara tentang manifestasi-Nya.[16]
3. Ayat-ayat yang menunjukkan kedekatan Al-Haqq Swt. dan menegaskan kesertaan-Nya.[17]
4. Ayat-ayat yang menunjukkan kebinasaan dan kepunahan segala sesuatu,[18] dan Zat Allah Swt. tidak membutuhkan sesuatu apapun,[19] sedangkan segala maujud selalu berhajat kepada-Nya.[20]
5. Ayat-ayat yang menunjukkan pengetahuan Allah Swt. terhadap segala sesuatu.[21]
6. Ayat-ayat yang dengan satu bentuk dan bentuk lain menunjukkan gabungan antara tanzîh dan tasybîh.[22]
7. Ayat-ayat yang berbicara tentang pandangan hati,[23] pertemuan dengan Allah,[24] dan melihat alam malakut.[25]
8. Ayat-ayat yang menunjukkan keutamaan Adam as. (manusia) dan ketinggian martabatnya dibandingkan dengan malaikat karena telah diajari nama-nama yang terindah (al-asmâ’ al-husnâ).[26]
9. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang tauhid aktivitas-aktivitas Ilahi.[27]
10. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwa akhirat adalah batin yang menyertai kehidupan di dunia yang merupakan lahir saja,[28] dan juga menunjukkan kepentingan ilmu yakin (‘ilm al-yaqîn).[29]
11. Ayat-ayat yang menunjukkan ilmu ladunni.[30]
12. Ayat-ayat yang menjelaskan benih-benih ketakwaan dalam usaha mencari ilmu dan makrifat.[31]
13. Ayat-ayat yang membahas tentang berbagai derajat lahiriah dan batiniah bagi orang-orang yang beriman.[32]
2. Sunnah
Mencakup hadis-hadis yang menunjukkan beberapa tema berikut.
1.
1. Eksistensi hanya terbatas pada Allah Swt. saja.
2. Pandangan hati terhadap Al-Haqq Swt.
3. Perbedaan tingkatan para sahabat, para wali dan kaum Mukmin.
4. Pendekatan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah.
5. Sebagian Mukmin dapat melihat Barzakh dan Malakut.
6. Ilmu disebut cahaya Ilahi yang dimunculkan di dalam hati.
7. Penyingkapan tabir-tabir bagi para maksum dan sahabat-sahabat mereka.
8. Orang maksum disebut insan kami (manusia paripurna) dan bahwa dia menjadi perantara datangnya limpahan anugerah (tangan Allah – wajah Allah).
9. Makna-makna lahiriah dan batiniah Al-Quran dan jumlah batiniah Kitab Allah itu.
10. Jalinan yang erat antara pengenalan diri dan pengenalan Tuhan.
11. Pengaruh keikhlasan terhadap pengetahuan hikmah dan alirannya pada lidah manusia.
12. Hadis-hadis qudsi, seperti hadis tentang kanz khafî (pusaka terpendam) dan penciptaan Adam dalam rupa Al-Haqq, di samping banyak tema yang dideduksi dari buku-buku ahli makrifat tentang masalah ini dan argumentasinya.
13. Doa-doa ma’tsûr dan khusus seputar tema al-asmâ’ al-husnâ yang dianggap sebagai pilar yang berpengaruh terhadap semua alam.
14. Meskipun masih bisa diperdebatkan tentang penafsiran dan penakwilan ayat-ayat Al-Quran atau perdebatan tentang sanad suatu riwayat atau penjelasan-penjelasannya, tetapi yang penting bagi kita di sini adalah sandaran para arif pada Al-Quran dan Sunnah bukan menjadikannya sebagai hakim. Adapun hal yang berkaitan dengan sahih dan cacatnya penyandaran ini, sebagaimana ditunjukkan oleh para muhaqqiq, adalah karena karakter dan ruh yang menguasai mistisisme dan tasawuf Islam adalah karakter dan ruh Islam. Inilah yang membedakannya dari mistisisme yang dikenal di Timur dan Barat. Perbedaan itu juga terletak pada bahasa, konsep, istilah dan kandungannya. Bahkan, kadang-kadang perbedaan itu terletak pada prinsipnya. Di sini, kami harus menunjukkan bahwa bisa saja hal itu dibahas dan didiskusikan secara tersendiri.
Hubungan Antara Agama dan Mistisisme
Tanpa melihat asal mistisisme dan pertumbuhan tasawuf Islam, akan muncul dalam pikiran kita suatu pertanyaan: apa hubungan yang sebenarnya antara agama dan mistisisme yang berkaitan dengannya atau yang menjadi turunannya? Dapatkah hubungan di antara keduanya dianggap sebagai hubungan yang bertolak belakang dan terpisah? Atau, apakah hubungan itu merupakan pertentangan dan kontradiksi, hubungan harmonis atau hubungan saling menyempurnakan, ataukah ada hubungan lain selain yang telah disebutkan?
Dalam buku ini, kami akan terfokus pada landasan hubungan yang ada antara Islam dan mistisisme Islam melalui pembahasan yang universal tentang bab ini, serta menjelaskan berbagai aspeknya.
Tidak diragukan bahwa untuk mencermati suatu pertanyaan, terlebih dahulu kita harus memastikan bahwa pertanyaan itu jelas. Jika pertanyaan itu tidak jelas, maka kita akan menghadapi berbagai pertanyaan lain (sebagai akibat perbandingan antara tiga bagian agama dan lima bagian mistisisme). Jika kita memisahkan ketiga makna agama—yakni, validitas (tsubût), konfirmasi (itsbât) dan verifikasi historis atau disebut juga agama pada tingkatan pertama (nash-nash agama), agama pada tingkatan kedua (berbagai konsensus ulama tentang agama), dan agama pada tingkatan ketiga (verifikasi historis agama dalam masyarakat serta sejarah dan institusi-institusinya)—sebagiannya dari sebagian yang lain dan mengambil mistisisme dengan lima bagiannya yang telah disebutkan sebelum ini.
Agar kita terhindar dari pembahasan yang bertele-tele, kami akan membahas subjek pertanyaan itu dalam lima bagian berikut.
1. Hubungan wahyu dengan penyaksian-batin (syuhûd)—dari aspek persepsi mistisisme
Hal ini karena sebagian arif menganggap wahyu dan penyaksian (syuhûd) berasal dari asal yang sama, dan mereka mengklasifikasikan keduanya ke dalam jenis ilmu hudhûrî,[33] walaupun kadang-ladang mereka menunjukkan adanya beberapa perbedaan di antara keduanya dalam hal tingkatan, jenis hubungan, dan beberapa syaratnya. Sementara itu, sebagian yang lain menegaskan bahwa hakikat wahyu masih merupakan misteri dan tidak mungkin diketahui. Mereka menganggap bahwa hubungan kedua unsur ini merupakan hubungan kontradiksi, atau setidaknya tidak diketahui.
2. Hakikat agama dan mistisisme—dari aspek edukasi
Dalam hal ini, hubungan atau jalinan antara ajaran-ajaran agama dan ajaran-ajaran mistisisme berasal dari akar hubungan yang umum dan khusus. Hal itu karena agama, di samping pengetahuan-pengetahuan batiniah dan hakikat-hakikat mistis, meliputi dimensi-dimensi lain termasuk dimensi fiqih, hukum-hukum lahiriah, masalah-masalah sosial, moral, dan prinsip-prinsip akidah yang umum.
3. Agama dan kajian-kajian mistis
Karena banyak sudut pandang terhadap sumber-sumber agama, yakni Al-Quran dan Sunnah, dan selanjutnya adalah penafsirannya sesuai dengan berbagai kajian, maka wajarlah bila dimensi kedua mistisisme (pandangan mistis) menjadi bagian dari kajian-kajian tersebut. Selanjutnya, hal itu dipandang sebagai kajian terhadap agama secara umum. Sebagaimana hal tersebut merupakan hubungan alamiah yang mengikat orientasi-orientasi kalam-filsafat, demikian pula hal itu mengikat bentuk fenomenal pada kaum Salafiyyah, Hanbali, Zhahiriyyah, dan ahli hadis dengan agama.
4. Kehidupan beragama dan mistisisme
Para arif memandang bagian ketiga dari mistisisme (yang disebut tharîqah atau mistisisme praktis) sebagai salah satu jalan yang mendorong pada keberagamaan. Namun, mereka tidak memandangnya sebagai jalan satu-satunya, sebagaimana mereka juga yakin bahwa kezuhudan, riyâdhah, takut (khauf), harapan (rajâ’), cinta (mahabbah), dan makrifat semuanya merupakan jalan yang mengantarkan pada keberagamaan. Mereka percaya bahwa penamaan khusus dengan kehidupan mistis direpresentasikan dalam gabungan antara syariat, tarekat (tharîqah), dan hakikat (haqîqah). Artinya, mencapai hakikat adalah dengan berpegang pada substansi agama dan hukum-hukumnya dengan memelihara lahiriah syariat, dan melalui jalan yang sama. Tentu saja, kehidupan mistis memiliki beberapa aspek dan ragam, dan di antaranya adalah mistisisme yang didasarkan pada asas cinta (mahabbah), riyâdhah, atau takut (khauf). Ada juga mistisisme munajat, mistisisme anggur (mudâm), bar (hânât) dan pembuat hukum (mutasyarri‘ah), mistisisme kebijaksanaan (hashâfah), mistisisme para darwisy, dan mistisisme para pezuhud. Demikian pula, mistisisme yang didasarkan pada tarikan Ilahi (jadzbah) atau sulûk, dan sebagainya.
5. Institusi agama dan institusi-institusi historis mistisisme
Kadang-kadang terjadi beberapa perbedaan di antara bagian kelima dari mistisisme—yakni silsilah-silsilah dan kelompok-kelompok sufi, shawâmi‘, khanqâh, kebiasaan-kebiasaan, dan tradisi-tradisi sufi—di satu sisi, dan agama, masjid-masjid, fukaha, hakim syariat, dan muhtasib yang muncul sepanjang sejarah. Kisah-kisah tentang tuduhan kafir dan fasik, berbagai penyiksaan berkaitan dengan hal-hal tersebut. Sebagian besar perdebatan dan polemik teologis kadang-kadang bermula dari kesalahpahaman atau karena hal-hal yang tidak esensial dari pihak orang-orang yang berpegang pada syariat, dan kadang-kadang juga disebabkan oleh ucapan-ucapan ekstatik (syathahât) dari kaum sufi yang dinilai tidak pantas, atau penyimpangan sebagian kelompok dari postulat-postulat syariat.
Dari uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa jika kita ingin menjelaskan karakter hubungan antara agama dan mistisisme, maka ketika itu kita harus memisahkan berbagai aspek dari masing-masing agar bisa mendapatkan jawaban-jawaban yang jelas dan tepat. Tetapi pada umumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada keraguan tentang adanya ikatan khusus mistisisme dengan agama, seperti mistisisme Islam—setidaknya menurut beberapa dimensi yang telah disebutkan tadi.
[1] Perhatian penulis terfokus pada definisi mistisisme (‘irfân) Islam yang diyakini oleh para arif (urafa) bahwa asas dan perkembangannya didasarkan pada ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis-hadis dari para maksum. Namun pada pasal-pasal pendahuluan dalam pembahasan ini, kami akan membicarakannya dari sisi yang umum. Hal itu untuk menjelaskan prinsip-prinsip dan pengetahuan ‘irfân, lalu kami mengkhususkan pembahasan tersebut pada mistisisme Islam.
[2] Syarafuddin Mahmud Al-Qaishari, Rasâ’il Al-Qaisharî, Risâlah Al-Tauhîd wa Al-Nubuwwah dan Al-Wilâyah, hal. 7.
[3] Murtadha Muthahhari, Kuliyyât ‘Ulûm Islâmî, hal. 76-77.
[4] ‘Abdurrazzaq Lahiji, Gauhar Murâd, hal. 14-16.
[5] Al-Mula Hadi Al-Sabziwari, Syarh Al-Asmâ’ Al-Husnâ, hal. 76.
[6] Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh Muhammad Iqbal dalam bukunya, Sair Al-Falsafah fî Irâm, hal. 100 dan seterusnya, Al-Suhrawardi, penulis buku Hikmah Al-Isyrâq wa Falsafah Al-Nûr, dapat dianggap termasuk ke dalam kelompok sufi hikmah (al-hikmah al-shûfiyyah). Bahkan, Al-Suhrawardi, dalam bukunya tersebut hal. 9-10, memandang bahwa hikmahnya hanyalah usaha untuk menuliskan mistisisme teoretis dan menjelaskan pemahaman-pemahaman tentang hal-hal yang dihasilkan dari ilmu hudhûrî. Namun, ushanya itu—sebagaimana akan kita ketahui setelah ini—masih belum sempurna dan belum tuntas akibat kekeliruan dalam membedakan antara ilmu makrifat ‘irfani (yang di dalamnya nûr, isyrâq dan syuhûd menempati kedudukan sebagai sentral) dan dimensi ontologi (‘ilm al-wujûd) (dimana eksistensi [wujûd] dan kesatuan [wahdah] menjadi poros dan sentral), di samping perpindahan dari otentisitas eksistensi ke otentisitas esensi (dan terutama yang berkaitan dengan masalah kesampaian [wushûl] ke wahdah al-wujûd dan penjelasannya)
[7] Rasâ’il Al-Qushairiyyah, Risâlah Al-Tauhîd wa Al-Nubuwwah wa Al-Wilâyah, hal. 7.
[8] Rasâ’il Al-Qushairiyyah, Risâlah Al-Tauhîd wa Al-Nubuwwah wa Al-Wilâyah, hal. 7.
[9] Sha’inuddin bin Turkah, Tamhîd Al-Qawâ‘id, koreksi: Ustad Asytiyani, hal. 262.
[10] ‘Abdullah Jawadi Amuli, Tahrîr Tamhîd Al-Qawâ‘id, hal. 687.
[11] Muhammad bin Ahmad bin Al-Junaid Abu ‘Ali, penulis Al-Iskâfî. Beliau adalah seorang syaikh dalam mazhab Imamiyyah, dan penulis yang handal, seperti yang dikatakan oleh Al-‘Allamah. Al-Najasyi berkata, “Dia adalah orang yang tepercaya di antara sahabat-sahabat kami. Saya mendengar dari para syaikh kami bahwa dia pernah mempraktikkan qiyas. Oleh karena itu, saya enggan membaca buku-bukunya dan tidak mempercayai isinya. Al-‘Allamah juga menilainya tsiqah, dan semua orang mengutip hadis darinya. (Penerj.)
[12] Fariduddin ‘Aththar (wafat 1230 M), salah seorang penyair sufi Persia terkemuka. Ia tumbuh dewasa di Mayhad. Di antara buku-buku karyanya adalah Manthiq Al-Thair dan Tadzkirah Al-Auliyâ’ tentang biografi para arif dan sufi. (Penerj.)
[13] Shadruddin Al-Rumi (wafat 673 H/1275 M), seorang sufi terkemuka dalam mazhab Al-Syafi‘i, dilahirkan dan wafat di Quniyah. Ia pernah belajar kepada Ibn ‘Arabi yang menjadi ayah tirinya. Ia sempat melakukan korespondensi dengan Nashiruddin Al-Thusi dalam masalah-masalah filsafat. Di antara karya-karyanya adalah I‘jâz Al-Bayân fî Tafsîr Umm Al-Qur’ân, yakni tafsir Surah Al-Fâtihah. (Penerj.)
[14] Surah Al-Hadîd [57] ayat 3: Dialah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Zahir dan Yang Batin; dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.
[15] Surah Al-Nûr [24]: 35: Allah Cahaya langit dan bumi…
[16] Surah Al-A‘râf [7]: 143: Dan tatkala Musa datang untuk [munajat dengan Kami] pada waktu yang telah Kami tentukan dan Tuhan telah berfirman [langsung] kepadanya, berkatalah Musa, “Ya Tuhanku, tampakkanlah [diri-Mu] kepadaku agar aku dapat melihat-Mu.” Tuhan berfirman, “Kamu sekali-kali tidak sanggup melihat-Ku, tetapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya (seperti sediakala) niscaya kamu dapat melihat-Ku.” Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan.
[17] Surah Al-Hadîd [57]: 4: Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
[18] Surah Al-Rahmân [55]: 25: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
[19] Surah Al-Rahmân [55]: 29: Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepada-Nya.
[20] Surah Fâthir [35]: 15: Hai manusia, kamulah yang berhajat kepada Allah; dan Allah Dia-lah Yang Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dan Maha Terpuji.
[21] Surah Al-Baqarah [2]: 115: Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka ke manapun kamu menghadap di situlah wajah Allah.
[22] Surah Al-Syûrâ [42]: 11: Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar dan Maha Melihat.
[23] Surah Al-Najm [53]: 11: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.
[24] Surah Al-Kahfi [18]: 110: Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh.
[25] Surah Al-An‘âm [6]: 75: Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan (Kami yang terdapat) di langit dan bumi.
[26] Surah Al-Baqarah [2]: 31: Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya.
[27] Surah Al-Anfâl [8]: 17: dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah-lah yang melempar.
[28] Surah Al-Rûm [30]: 7: Mereka hanya mengetahui yang lahir (saja) dari kehidupan dunia; sedang mereka tentang (kehidupan) akhirat adalah lalai.
[29] Surah Al-Takâtsur [102]: 5-6: Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim.
[30] Surah Al-Kahfi [18]: 65: Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba Kami, yang telah Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami.
[31] Surah Al-Baqarah [2]: 282: Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu.
[32] Surah Ali ‘Imrân [3]: 163: (Kedudukan) mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.
[33] Yaitu yang ditunjukkan oleh Jalaluddin Al-Rumi dalam buku Al-Matsnawî, bab ke-4, bait 1851 dan 1852. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat pasal pertama dalam pembahasan Wahyu dan Pengalaman Mistis(by Ahmad Samantho)