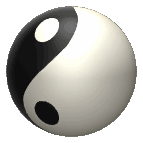Tasawuf dan Tarikat Dalam Islam
Allahumma shalli wasallim alaa hazarroosuulil 'aziim
wa'ala alihi wa ashaabihi waman tabiahum ilaa yaumiddin.
Ya Allah, salam dan salawat pada junjungan nabi besar Rasulullah saw, para keluarganya, para sahabatnya dan kepada siapa saja yang mengikuti mereka sampai akhir zaman.
Pendahuluan
Umat Islam dalam perjalanan sejarahnya tidak pernah bebas dari perselisihan antarsesama yang kadang-kadang memuncak sampai pada level yang sangat memprihatinkan. Banyak sekali faktor-faktor yang memicu kondisi semacam ini. Selain kepentingan politik dan ekonomi, salah satu faktor yang sangat dominan dan menghambat terciptanya kesatuan dan persatuan umat Islam dalam suasana ukhuwah yang mesra adalah sikap tamaththu’ (sok suci, konsekuen), tatharruf (ekstrem) dan ta’ashshub (fanatik), sebuah sikap yang membuat pemiliknya cenderung memutlakkan pendapat dan pemahaman sendiri sebagai yang paling benar tanpa mencoba memahami secara bijak pendapat dan pemahaman orang lain. Sikap ini bahkan kerapkali melahirkan kegemaran menghakimi dan memvonis orang lain sebagai sesat dan menyesatkan. Faktor lain yang justru menjadi pangkal dari sikap ini adalah literatur dan informasi yang tidak memadai sehingga menimbulkan pemahaman yang tidak utuh.
Tasawuf dan tarikat adalah korban yang paling sering dihujat sesat oleh saudara-saudara seiman yang didominasi oleh sikap tersebut. Mereka memandang tasawuf dan tarikat sebagai sarang bid’ah – hal-hal yang baru yang diklaim tidak pernah diajarkan dalam Islam atau tidak pernah dilakukan dan diperintahkan oleh Rasul Dalil utama yang sering dikemukakan mereka adalah hadis Nabi saw yang sangat terkenal dan diriwayatkan oleh banyak imam hadis,
“Hindarilah perkara-perkara yang baru (diada-adakan), karena setiap perkara yang baru adalah bid’ah, dan bid’ah adalah sesat.”
Benarkah tasawuf dan tarikat itu bid’ah?
Makalah ini sebagaimana tampak dalam judulnya mencoba menyingkap dalil-dalil naqli (al-Qur’an dan al-Sunnah) yang mendasari keabsahan tasawuf dan tarikat, didukung oleh pendapat dan penjelasan para ulama mengenai hal-hal terkait.
Pengertian Tasawuf
Banyak sekali definisi tasawuf yang telah dikemukakan, dan masing-masing berusaha menggambarkan apa yang dimaksud dengan tasawuf. Tetapi pada umumnya definisi yang dikemukakan hanya menyentuh sebagian dari keseluruhan bangunan tasawuf yang begitu besar dan luas.
Definisi-definisi yang dikemukakan sama dengan yang dilakukan empat orang buta, dalam kisah Rumi, ketika mereka menggambarkan bentuk gajah. Masing-masing menggambarkan bentuk gajah sesuai dengan bagian tubuh yang disentuhnya. Bagi yang pertama, bentuk gajah seperti mahkota, bagi yang kedua seperti pipa air, bagi yang ketiga, seperti kipas, dan bagi yang terakhir seperti tiang.
Imam al-Qusyairi dalam al-Risalah-nya mengutip 50 definisi dari ulama Salafi; sementara Imam Abu Nu'aim al-Ishbahani dalam "Ensiklopedia Orang-Orang Suci"-nya Hikayat al-awliya' mengutip sekitar 141 definisi, antara lain:
"Tasawuf adalah bersungguh-sungguh melakukan suluk yaitu `perjalanan' menuju malik al muluk `Raja semua raja' (Allah `assa wa jalla)."
"Tasawuf adalah mencari wasilah `alat yang menyampaikan' ke puncak fadhilah `keutamaan'."
Definisi paling panjang yang dikutip Abu Nu'aim berasal dari perkataan Imam al-Junaid ra. ketika ditanya orang mengenai makna tasawuf:
"Tasawuf adalah sebuah istilah yang menghimpun sepuluh makna: 1. tidak terikat dengan semua yang ada di dunia sehingga tidak berlomba- lomba mengerjarnya. 2. Selalu bersandar kepada Allah `azza wa jalla,. 3. Gemar melakukan ibadah ketika sehat. 4. Sabar kehilangan dunia (harta). 5. Cermat dan berhati-hati membedakan yang hak dan yang batil. 6. Sibuk dengan Allah dan tidak sibuk dengan yang lain. 7. Melazimkan dzikir khafi (dzikir hati). 8. Merealisasikan rasa ikhlas ketika muncul godaan. 9. Tetap yakin ketika muncul keraguan dan 10. Teguh kepada Allah dalam semua keadaan. Jika semua ini berhimpun dalam diri seseorang, maka ia layak menyandang istilah ini; dan jika tidak, maka ia adalah pendusta. [Hilayat al-Awliya]
Beberapa fuqaha `ahli fikih' juga mengemukakan definisi tasawuf dan mengakui keabsahan tasawuf sebagai ilmu kerohanian Islam. Di antara mereka adalah: Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Jazi al-Kalabi al-Gharnathi (w. 741 H.) dalam kitabnya al Qawanin al Fiqhiyyah li Ibn Jazi hal. 277 menegaskan:
"Tasawuf masuk dalam jalur fiqih, karena ia pada hakikatnya adalah fiqih batin (rohani), sebagaimana fiqih itu sendiri adalah hukum-hukum yang berkenaan dengan perilaku lahir."
Imam `Abd al-Hamid al-Syarwani, dalam kitabnya Hawasyi al-Syarwani VII, menyatakan: "Ilmu batin (kerohanian), yaitu ilmu yang mengkaji hal ihwal batin (rohani), yakni yang mengkaji perilaku jiwa yang buruk dan yang baik (terpuji),itulah ilmu tasawuf."
Imam Muhammad `Amim al-Ihsan dalam kitabnya Qawa'id al-Fiqih, dengan mengutip pendapat Imam al-Ghazali, menyatakan:
"Tasawuf terdiri atas dua hal: Bergaul dengan Allah secara benar dan bergaul dengan manusia secara baik. Setiap orang yang benar bergaul dengan Allah dan baik bergaul dengan mahluk, maka ia adalah sufi."
Definisi-definisi tersebut pada dasarnya saling melengkapi satu sama lain, membentuk satu kesatuan yang tersimpul dalam satu buhul: "Tasawuf adalah perjalanan menuju Tuhan melalui penyucian jiwa yang dilakukan dengan intensifikasi dzikrullah".
Penyucian jiwa (tazkiyah an-nafs) merupakan ruh dari takwa, sementara takwa merupakan sebaik-baik bekal (dalam perjalanan menuju Allah), sehingga dikatakan oleh Imam Muhammad Zaki Ibrahim, pemimpin tarikat sufi Al-Asyirah Al-Muhammadiyyah di Mesir, bahwa "tasawuf adalah takwa. Takwa tidak hanya berarti "mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-Nya. Takwa juga meliputi "cinta, ikhlas, sabar, zuhud, qana'ah, tawadhu', dan perilaku-perilaku batin lainnya yang masuk ke dalam kategori makarim al-akhlaq (alkhlak yang mulia) atau al-akhlaq al-mahmudah (akhlak yang terpuji)".
Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila tasawuf juga sering didefinisikan sebagai akhlak, yaitu akhlak bergaul dengan Allah dan akhlak bergaul dengan semua makhluk-Nya. Imam Muhammad ibn `Ali al-Kattani, sebagaimana dikutip oleh Imam al-Qusyairi dalam al-Risalah-nya, menegaskan bahwa "tasawuf adalah akhlak". Imam Abu Nu'aim al-Ishbahani juga mengutip definisi senada dalam Hilyat al-Awliya-nya:
"Tasawuf adalah berakhlak dengan akhlak (orang-orang ) mulia."
Definisi terakhir di atas sejalan dengan keberadaan Nabi SAW yang diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia sebagaimana ditegaskan oleh beliau sendiri dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal
"Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik." Para perawi hadis ini adalah para perawi sahih (rijal al-shahih). [Majma' al-Zawaid, VIII:188]
Akhlak itu sendiri merupakan perilaku batin yang melahirkan berbagai perbuatan secara otomatis tanpa melalui pertimbangan yang disengaja, atau dalam definisi Imam al-Ghazali diungkapkan dengan redaksi: "Akhlak merupakan ungkapan tentang kondisi yang berakar kuat dalam jiwa; dari kondisi itu lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikirkan dan pertimbangan."
Apa pun definisi yang dikemukakan para ulama mengenai tasawuf, satu hal pasti adalah bahwa tasawuf merupakan sisi rohani Islam yang sangat fundamental dan esensial; bahkan ia merupakan inti ajaran yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul.
Pernyataan Imam Muhammad Zaki Ibrahim barangkali sudah cukup sebagai penjelasan terakhir: "Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai definisi tasawuf, semua definisi yang ada mengarah kepada satu titik yang sama, yaitu taqwa dan tazkiyah. Tasawuf adalah hijrah menuju Allah SWT, dan pada hakikatnya semua definisi yang ada bersifat saling melengkapi." [Abjadiyyah al-Tashawwuf al-Islami, atau Tasawuf Salafi, hlm 7.]
Tidak satu definisi-pun yang mampu menggambarkan secara utuh apa yang disebut dengan tasawuf. Demikian pula, tidak ada satu penjelasan pun yang mampu menggambarkan apa yang disebut denga ihsan `beribadah seolah-olah melihat Allah', karena hal itu menyangkut soal rasa dan "pengalaman", bukan penalaran atau pemikiran. Pemahaman yang utuh mengenai tasawuf dan sekaligus ihsan hanya muncul setelah seseorang "mengalami" dan tidak sekadar "membaca" definisi-definisi yang dikemukakan orang.
“Tasawuf adalah sebuah istilah yang menghimpun sepuluh makna: 1. tidak terikat dengan semua yang ada di dunia sehingga tidak berlomba-lomba mengerjarnya. 2. Selalu bersandar kepada Allah ‘azza wa jalla,. 3. Gemar melakukan ibadah ketika sehat. 4. Sabar kehilangan dunia (harta). 5. Cermat dan berhati-hati membedakan yang hak dan yang batil. 6. Sibuk dengan Allah dan tidak sibuk dengan yang lain. 7. Melazimkan dzikir khafi (dzikir hati). 8. Merealisasikan rasa ikhlas ketika muncul godaan. 9. Tetap yakin ketika muncul keraguan dan 10. Teguh kepada Allah dalam semua keadaan. Jika semua ini berhimpun dalam diri seseorang, maka ia layak menyandang istilah ini; dan jika tidak, maka ia adalah pendusta. [Hilayat al-Awliya]
Beberapa fuqaha ‘ahli fikih’ juga mengemukakan definisi tasawuf dan mengakui keabsahan tasawuf sebagai ilmu kerohanian Islam. Di antara mereka adalah: Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Jazi al-Kalabi al-Gharnathi (w. 741 H.) dalam kitabnya al Qawanin al Fiqhiyyah li Ibn Jazi hal. 277 menegaskan:
“Tasawuf masuk dalam jalur fiqih, karena ia pada hakikatnya adalah fiqih batin (rohani), sebagaimana fiqih itu sendiri adalah hukum-hukum yang berkenaan perilaku lahir.”
Imam ‘Abd al-Hamid al-Syarwani, dalam kitabnya Hawasyi al-Syarwani VII, menyatakan: “Ilmu batin (kerohanian), yaitu ilmu yang mengkaji hal ihwal batin (rohani), yakni yang mengkaji perilaku jiwa yang buruk dan yang baik (terpuji), itulah ilmu tasawuf.”
Imam Muhammad ‘Amin al-Ihsan dalam kitabnya Qawa’id al-Fiqih, dengan mengutip pendapat Imam al-Ghazali, menyatakan:
“Tasawuf terdiri atas dua hal: Bergaul dengan Allah secara benar dan bergaul dengan manusia secara baik. Setiap orang yang benar bergaul dengan Allah dan baik bergaul dengan mahluk, maka ia adalah sufi.”
Definisi-definisi tersebut pada dasarnya saling melengkapi satu sama lain, membentuk satu kesatuan yang tersimpul dalam satu buhul: “Tasawuf adalah perjalanan menuju Tuhan melalui penyucian jiwa yang dilakukan dengan intensifikasi dzikrullah”. Penyucian jiwa (tazkiyah an-nafs) merupakan ruh dari takwa, sementara takwa merupakan sebaik-baik bekal (dalam perjalanan menuju Allah), sehingga dikatakan oleh Imam Muhammad Zaki Ibrahim, pemimpin tarikat sufi Al-Asyirah Al-Muhammadiyyah di Mesir, bahwa “tasawuf adalah takwa".
Takwa tidak hanya berarti “mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-Nya. Takwa juga meliputi “cinta, ikhlas, sabar, zuhud, qana’ah, tawadhu’, dan perilaku-perilaku batin lainnya yang masuk ke dalam kategori makarim al-akhlaq (alkhlak yang mulia) atau al-akhlaq al-mahmudah (akhlak yang terpuji)”. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila tasawuf juga sering didefinisikan sebagai akhlak, yaitu akhlak bergaul dengan Allah dan akhlak bergaul dengan semua makhluk-Nya. Imam Muhammad ibn ‘Ali al-Kattani, sebagaimana dikutip oleh Imam al-Qusyairi dalam al-Risalah-nya, menegaskan bahwa “tasawuf adalah akhlak”. Imam Abu Nu’aim al-Ishbahani juga mengutip definisi senada dalam Hilyat al-Awliya-nya: “Tasawuf adalah berakhlak dengan akhlak (orang-orang ) mulia.”
Definisi terakhir di atas sejalan dengan keberadaan Nabi saw yang diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia sebagaimana ditegaskan oleh beliau sendiri dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal:
“Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik.”
Para perawi hadis ini adalah para perawi sahih (rijal al-shahih). [Majma’ al-Zawaid, VIII:188] Akhlak itu sendiri merupakan perilaku batin yang melahirkan berbagai perbuatan secara otomatis tanpa melalui pertimbangan yang disengaja, atau dalam definisi Imam al-Ghazali diungkapkan dengan redaksi: “Akhlak merupakan ungkapan tentang kondisi yang berakar kuat dalam jiwa; dari kondisi itu lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikirkan dan pertimbangan.”
Apa pun definisi yang dikemukakan para ulama mengenai tasawuf, satu hal pasti adalah bahwa tasawuf merupakan sisi rohani Islam yang sangat fundamental dan esensial; bahkan ia merupakan inti ajaran yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul. Perbedaan-perbedaan penggambaran bentuk gajah yang dilakukan oleh empat orang buta dalam kisah Rumi. Pernyataan Imam Muhammad Zaki Ibrahim mengenai perbedaan-perbedaan ini barangkali sudah cukup sebagai penjelasan terakhir: “Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai definisi tasawuf, semua definisi yang ada mengarah kepada satu titik yang sama, yaitu taqwa dan tazkiyah. Tasawuf adalah hijrah menuju Allah SWT, dan pada hakikatnya semua definisi yang ada bersifat saling melengkapi.” [Abjadiyyah al-Tashawwuf al-Islami, atau Tasawuf Salafi, hlm 7.]
Tidak satu definisi pun yang mampu menggambarkan secara utuh apa yang disebut dengan tasawuf. Demikian pula, tidak ada satu penjelasan pun yang mampu menggambarkan apa yang disebut denga ihsan ‘beribadah seolah-olah melihat Allah’, karena hal itu menyangkut soal rasa dan “pengalaman”, bukan penalaran atau pemikiran. Pemahaman yang utuh mengenai tsawuf dan sekaligus ihsan hanya muncul setelah seseorang “mengalami” dan tidak sekadar “membaca” definisi-definisi yang dikemukakan orang.
Posisi Tasawuf dalam Ilmu-Ilmu Islam
Prof. Dr. H. S.S. Kadirun Yahya Al-Khalidi menyatakan bahwa Tasawuf adalah “Saudara Kembar” Fiqih. Pernyataan ini tampaknya berdasarkan pada kenyataan bahwa Fiqih pada hakikatnya merupakan formulasi lebih lanjut dari konsep Islam, sementara Tasawuf merupakan perwujudan konkret dari konsep Ihsan. Dua konsep ini tercetus bersama-sama dengan konsep Iman (diformulasikan lebih jauh dalam ilmu kalam) dalam dialog antara Jibril AS dan Nabi SAW sebagaimana dikemukakan dalam hadist Abu Hurairah yang sangat terkenal. [Shahih al-Bukhari, I:27; Shahih Muslim, L:39]
Penjelasan lebih gamblang mengenai posisi Tasawuf sebagai “saudara kembar” Fiqih dikemukakan oleh Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka) dalam bukunya Tasawuf, Perkembangan dan Pemurniannya:
“Alhasil kemurnian dan cita-cita Islam yang tinggi adalah gabungan Tasauf dan Fiqih: gabungan otak dan hati. Dengan Fiqih kita menentukan batas-batas hukum, dan dengan Tasauf kita memberi pelita dalam jiwa, sehingga tidak terasa berat di dalam melakukan segala kehendak agama.
“Kalau kita tilik kepada bunyi Hadist tentang Islam, Iman dan Ihsan tampaklah bahwa ketiga Ilmu Islam yaitu Ilmu Fiqih, Ilmu Ushuluddin dan Ilmu Tasawuf telah dapat menyempurnakan ketiga simpulan agama itu (Islam, Iman dan Ihsan).
“Islam diartikan oleh hadist itu ialah mengucapkan Syahadat, mengerjakan Shalat lima waktu, Puasa bulan Ramadhan, mengeluarkan Zakat dan Naik Haji. Untuk mengetahui, sehingga kita mengerjakan suruhan agama dengan tidak membuta: Kita pelajarilah Fiqih.
“Iman adalah Iman kepada Allah, kepada Malaikat, kepada Rasul-Rasul dan Kitab-Kitab, dan iman kepada Hari Kiamat dan Takdir, buruk dan baik, Kita pelajarilah Ushuluddin atau Ilmu Kalaam."
“Ihsan adalah kunci daripada semuanya, yaitu: Bahwa kita mengabdi kepada Allah SWT, seakan-akan Allah SWT itu kita lihat di hadapan kita sendiri. Karena meskipun mata kita tidak dapat melihatNya, namun Allah SWT tetap melihat kita. Untuk menyempurnakan ihsan itu, kita masuki alam Tasawuf.
“Itulah tali berpilah tiga: Iman, Islam dan Ihsan. Dicapai dengan tiga ilmu: Fiqih, Ushuluddin dan Tasawuf. [Tasawuf, Perkembangan dan Pemurniannya, hal. 94-95]
Jadi, sebagai sebuah ilmu, posisi Tasawuf terhadap ilmu-ilmu Islam lainnya sangat jelas dan gamblang. Tasawuf merupakan bagian tak berpisahkan dari keseluruhan bangunan Syari’ah; bahkan ia merupakan ruh/hakikat/inti dari syariah.
Syariah sendiri dapat didefinisikan sebagai “segala sesuatu yang terbit dari diri Nabi SAW yang berupa sikap, perbuatan, dan perkataan (al-Qur’an dan al-Hadist)”; atau dengan bahasa yang lebih umum: Syariah adalah segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Namun begitu, syariah pada dasarnya merupakan produk dari hakikat Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Allah.
Adalah mustahil memahami syariah (produk) secara sempurna tanpa memahami hakikatnya. Ilmu yang menyajikan jalan untuk mengenal hakikat ini adalah Tasawuf, sedangkan ilmu-ilmu (keislaman) lainnya, seperti ilmu Fiqih dan hadist misalnya, semuanya menyajikan jalan untuk memahami produk. Tasawuf melibatkan hati atau qalbu (ruhani), sedangkan ilmu-ilmu lainnya melibatkan otak atau akal (jasmani).
Fiqih dan Tasawuf ibarat dua sisi mata uang, jika salah satu rusak maka yang lain menjadi tidak berfungsi, sehingga kedua-duanya harus dipegang secara utuh untuk mencapai kesempurnaan. Dalam kaitan ini, Imam Abu Abdillah al-Dzahabi (w. 748 H), penulis kitab Siyar A’lam al-Nubala’ (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1413) yang terdiri dari 23 jilid menegaskan:
“Jika seorang ulama tidak ber-Tasawuf, maka ia kosong; sebagaimana jika seorang sufi tidak mengenal sunnah (baca bersyariat), maka ia tergelincir dari jalan yang lurus.”
Imam Malik ibn Anas, pemimpin madzhab Maliki yang sangat terkenal, sebagaimana dikutip oleh Syeikh Amin al-Kurdi, juga mengungkapkan hal senada:
“Barangsiapa yang bersyariat tetapi tidak berhakikat (ber-Tasawuf) maka ia telah fasik; dan barangsiapa yang berhakikat (ber-Tasawuf) tetapi tidak bersyariat maka ia telah zindik.” [Tanwir al-Qulub, hal. 408]
Di samping itu, tidak salah apabila dikatakan bahwa Tasawuf adalah sebuah madzhab sebagaimana Ilmu Fiqih yang mengenal (minimal) empat mazhab, sehingga tidak jarang para ulama melibatkan pendapat kaum sufi ketika membahas hukum suatu perkara. Syeikh al-Islam Ibn Taymiyah menempatkan kaum sufi dalam deretan fuqaha’ dan ahli hadist. Hal ini dapat disimak misalnya dari pernyataan beliau ketika menetapkan hukum larangan menikahi orang yang menolak kekhalifahan Sayyidina Ali setelah ‘Utsman ibn ‘Affan:
Hal itu (larangan menikahi orang yang tidak menerima kekhalifahan Ali ibn Abi Thalib) telah disepakati oleh para fuqaha, ahli hadist, dan juga oleh ahli ma’rifat dan Tasawuf. [Kutub wa Rasail wa Fatawa Ibn Taimiyah, XXXV:19]
Pandangan Ibn Taimiyah dan Ibn al-Qayyim
Syeikh al-Islam Ibn Taimiyah dan Ibn al-Qayyim al-Jawziyah adalah sepasang guru-murid yang mendukung dan mengakui kebenaran Tasawuf sebagai ilmu yang dapat membersihkan jiwa.
Ibn Taimiyah, misalnya, menyebut para sufi dengan sebutan ahl ‘ulum al-qulub/pakar-pakar ilmu hati’ yang perkataanya paling tepat dan paling baik realisasinya (asaddu wa ajwadu tahqiqan) serta paling jauh dari bid’ah (ab’adu minal bid’ah). Dalam kitabnya yang sangat terkenal Majmu’ al-Fatawa (Beirut: Dar al-Kitab al Arabi, 1973).
Dalam kitabnya Amradh al-Qulub wa Syifauha (Kairo: al-Mathba’ah al-Salafiyyah, 1399), hal. 62, ketika berbicara surah al-Kafirun), Ibn Taimiyah berkata: “Adapun qul ya ayyuhal kafiruun mengundang tauhid amali iradi, tauhid praktis yang didasarkan pada kehendak, yaitu keikhlasan beragama semata-mata untuk Allah dengan sengaja dan dikehendaki; dan itulah yang dibicarakan oleh syeikh-syeikh Tasawuf pada umumnya.
“Imam-imam Tasawuf menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang dicintai dengan cinta yang hakiki, bahkan dengan cinta yang paling sempurna.” [Amradh al-Qulub, hal. 68]
Adapun Ibn al-Qayyim, dalam kitabnya Madarij al-Salikhln, I:464 (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1973), memperkatakan mengenai Abu Yazid al-Busthami dengan redaksi:
“Ini (memelihara dan menjauhkan keinginan dari selain Allah yang Maha Suci) seperti kondisi Abu Yazid al-Busthami – semoga Allah merahmatinya – menganai berita tentang dirinya ketika ia ditanya, ‘Apa yang engkau inginkan (kehendak)?’; ia menjawab, ‘Aku ingin agar aku tidak ingin yang kedua (setelah Allah),’ inilah hakikat Tasawuf.”
Dalam kitabnya yang lain Badai al-Fawaid, III:756 (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Nizar Mushthafa al-Baz, 1996), Ibn al-Qayyim berkata:
“Tasawuf dan kefakiran (baca: hanya butuh kepada Allah) berada pada wilayah hati”.
Thariqah dalam Al-Quran dan al-Hadis
Thariqah (Ind. Tarekat) adalah jalan yang dilalui oleh orang sufi dalam perjalanannya menuju Tuhan, dan digambarkan sebagai jalan yang berpangkal pada syari’ah, sebab jalan utama disebut syar’ sedangkan anak jalan disebut thariq. Kata ini terambil dari kata tharq yang di antara maknanya adalah “mengetuk” seperti dalam ungkapan tharq al-bab yang berarti “mengetuk pintu”; karena itu, cara beribadah seorang sufi disebut thriqah karena ia dalam ibadahnya selalu mengetuk pintu hatinya dengan dzikrullah. Cara beribadah semacam ini oleh Nabi disebut dengan thariqah hasanah ‘cara yang baik’. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dalam Musnadnya dengan perawi-perawi tsiqat ‘dipercaya’ Nabi saw bersabda:
“Sesungguhnya seorang hamba jika berpijak pada thariqah yang baik dalam beribadah, kemudian ia sakit, maka dikatakan (oleh Allah) kepada malaikat yang mengurusnya, ‘Tulislah untuk orang itu pahala yang sepadan dengan amalnya apabila ia sembuh sampai Aku menyembuhkannya atau mengembalikannya kepada-Ku.’(Musnad Ahmad, 11: 203.)
Ungkapan thariqah hasanah dalam hadis tersebut menunjukan kepada perlaku hati yang diliputi kondisi ihsan’beribadah seolah –olah melihat Tuhan atau kondisi khusyu’ yakin berjumpa dengan Tuhan dan kembali kepada-Nya,’ (Al-Baqarah, 2: 46) sebab ibadah (misalnya salat) yang dilakukan dengan hati yang lalai oleh Nabi disebut sebagai shalat al-munafiq ‘salatnya orang munafik’, yaitu yang didalamnya ia tidak berdzikir kepada Allah kecuali sedikit (la yadzkurullaha fiha illa qalilan) Shahih Muslim, 1: 434, dan pelakunya oleh Tuhan diancam dengan al-wayl. (Al-Maun, 107: 4-5).
Didalam al-Quran pun kata thariqah muncul dalam konteks dzikrullah sebagai aktualisasi tauhid yang sempurna.
Setelah Allah menjanjikan karunia yang banyak kepada orang-orang yang istiqamah di atas thariqah, Dia langsung memberikan ancaman siksa yang sangat pedih kepada orang yang tidak mau berdzikir kepada-Nya:
“Seandainya mereka istiqamah di atas thariqah niscaya Kami beri minum mereka dengan air yng melimpah (karunia yang banyak): untuk Kami uji mereka di dalamnya, dan barang siapa tidak mau berdzikir kepada Tuhannya, niscaya Dia menimpakan azab yang sangat pedih.” (Al-Jinn, 72: 16-17)
Ibn al-Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarij al-Salikin mengutip perkataan Abu Bakar al-Shiddiq r.a. ketika menyingung ayat tersebut. Sahabat agung ini pernah ditanya mengenai maksud al-istiqamah ala al-thariqah dan ia menjawab, “hendaknya engkau tidak menyekutukan Allah dengan sesuat (an la tusyrika billahi syay-an).” Jadi, kata Ibn al-Qayyim, yang dimaksud (al-istiqamah ‘ala al-thariqah) oleh Abu Bakar al-Shiddiq r.a. adalah al-istiqamah ala mahdhi al-tauhid konsisten di atas tauhid yang murni artinya, thariqah dalam ayat tersebut adalah”jalan menuju tauhid yang murni”.
Tauhid yang murni ini pulalah yang menjadi tujuan syekh-syekh tarekat sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibn Taimiyah:
“Tauhid inilah yang dibawa oleh para rasul dan kitab-kitab Allah dan yang diisyaratkan oleh syeikh-syeikh tarekat dan pakar-pakar agama."
Dalam ayat yang lain thariqah disandingkan dengan syari’ah yaitu ketika Allah berfirman:
“Bagi tiap-tiap umat di antara kamu Kami berikan syir’ah (peraturan) dan minhaj (metode).” (Al-Maidah, 5:48)
Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa syir’ah dalam ayat tersebut adalah syari’ah (peraturan) sedangkan minhaj adalah thariqah (metode pelaksanaan syari’ah), dan kedua-dua (syari’ah dan thariqah) secara simultan bermuara pada tujuan pokok yang merupakan haqiqat al-din (hakikat agama), yaitu tauhid yang murni, atau hanya menyembah Allah semata (ibadat Allah wahdah).
Thariqah dalam pandangan Ibn Taimiyah
Penjelasan Ibn Taimiyah mengenai tarekat sangat penting untuk dikemukakkan lebih jauh disini, sebab sekali lagi selama ini ia sering dituding sebagai anti tarekat dan bahkan dijadikan rujukan utama oleh sebagian kecil umat untuk menentang tarekat, padahal Ibn Taimiyah tidak pernah menentang tarekat/tasawuf kecuali yang nyata sekali bertentangan dengan Al-Quran dan al-Sunnah.
Ketika memuji Imam al-Junaid al-Baghdadi berkenaan dengan kewajiban seorang salik orang yang berjalan menuju Tuhan agar mengenal Sang Pencipta (ma’rifat al-shani) sehingga dapat beramal dan berubudiyah secara ikhlas, Ibn Taimiyah menegaskan dalam kitabnya al-Istiqamah:
“Ini (mengenal sang Pencipta) termasuk di antara pokok-pokok akidah ahlu-sunnah dan imam-imam para Syeikh, khususnya syekh-syekh sufi, karena pokok pangkal tarekat para sufi adalah kehendak (al-iradah), yang merupakan fondasi amal. Mereka dalam hal kehendak, ibadah, amal dan akhlak lebih besar ketehuhannya daripada dalam hal perkataan dan ilmu pengetahuannya. Mereka dengan semua itu lebih besar perhatiannya dan lebih banyak pemeliharaanya. Orang yang belum memasuki semua itu tidak dapat serta merta menjadi ahli tarekat mereka."
Dalam kitabnya yang lain al-Hasanah wa al-Sayyiah, Ibn Taimiyah menegaskan lebih lanjut bahwa orang yang mengikuti Imam al-Junaid adalah orang yang memperoleh hidayah, selamat dan bahagia:
“Barang siapa menempuh jalan yang ditempuh oleh al-Junaid yang merupakan salah seorang pakar tasawuf dan ma’rifah, maka ia benar-benar telah mendapat hidayah, selamat dan bahagia."
Selain Imam al-Junaid al-Baghdadi, Ibn Taimiyah juga memuji dan membela syekh syekh tarekat lainnya, seperti: Abu Yazid al-Busthami, Syekh Abd al-Qadir al-Jailani, dan bahkan juga Imam al-Ghazali. Tentang Syekh Abd al-Qadir al-Jailani, misalnya, Ibn Taimiyah menggambarkannnya sebagai berikut:
“Syekh Abd al-Qadir al-Jailani, misalnya, Ibn Taimiyah menggambarkannya sebagai berikut: “Shekh Abd al-Qadir al-Jailani dan Syekh tarekat seperti beliau merupakan syekh yang paling gigih memerintahkan menetapi syara, perintah dan larangan, serta mengedepankan agar meninggalkan keinginan dan kehendak nafsu, karena kesalahan dalam berkehendak dilihat dari segi kehendak itu sendiri hanya terjadi dari sisi hawa nafsu ini. Beliau memerintahkan seorang salik ‘murid yang menempuh suluk (perjalanan) menuju Tuhan’ agar tidak memiliki sama sekali kehendak yang bersumber dari hawa nafsu melainkan ia berkehendak sesuai dengan yang dikehendaki Allah ‘azza wa jalla."
Pada bagian sebelumnya sudah disinggung bahwa Ibn Taimiyah menyebut para sufi sebagai ahl ulum al-qulub ‘pakar-pakar ilmu hati yang bebas dari bid’ah ketika ia mengatakan:
“Perkataan pakar-pakar ilmu hati dari kalangan sufi dan yang selain mereka, seperti Abu Hamid al-Ghazali pula Ibn Taimiyah mengutip pernyataan yang mengukuhkan kebenaran tarikat para sufi:
“Tarekat para sufi adalah tujuan (ghayah), karena mereka menyucikan kalbu mereka dari hal-hal selain Allah dan memenuhinya dengan dzikrullah; dan ini merupakan prinsip dakwah para rasul. Pengakuan Ibn Taimiyah mengenai kebenaran tarekat para sufi juga mencuat dari pernyataanya yang dituangkan dalam kitabnya yang berjudul Syarh al-Aqidah al-Ishfahaniyah, yaitu ketika ia berbicara tentang mu’jizat para nabi: “ Tidak ada jalan bagi akal untuk memahami mukjizat para nabi hanya dengan komoditi akal semata. Hal-hal lain dari keistimewaan para nabi hanya dapat dipahami dengan rasa oleh orang yang menempuh tarekat tasawuf…"
Jika Nabi memiliki suatu keistimewaan yang Anda tidak punya modelnya, maka Anda sama sekali tidak akan memahami keistimewaan itu, apalagi membenarkannya, karena pembenaran hanya muncul setelah pemahaman, dan model yang dimaksudkan di sini terdapat di awal tarekat tasawuf…Adapun rasa (dzawq) maka ia seperti ‘menyaksikan’ dan ‘mengambil dengan tangan’dan hal itu tidak ada kecuali dalam tarekat para sufi.
Ibn Taimiyah bahkan tidak mengingkari konsep “mabuk” yang kadang-kadang melahirkan berbagai ungkapan yang sepintas terkesan berbau syirik tetapi sebenarnya tidak dimaksudkan demikian, ungkapan-ungkapan yang dikenal dengan syathahat.
Ungkapan-ungkapan pada dasarnya muncul secara otomatis dari kondisi fana (ekstase) yang sama sekali tidak dipengaruhi oleh pertimbangan atau kesadaran apa pun kecuali semata-mata karena terbuai oleh keagungan dan keindahan Tuhan. Dalam kaitan ini ia mengatakan:
“Sebagian tokoh sufi yang mengalami kondisi spiritual tertentu (dzawi al-ahwal) kadang-kadang mengalami ‘mabuk dan lenyap dari selain Allah’ dalam keadaaan fana’yang singkat. Keadaan mabuk seperti itu terjadi tanpa disengaja, tanpa pertimbangan. Kadang-kadang dalam keadaan itu ia berkata subhani (maha suci aku), atau ungkapan-ungkapan lain seperti yang mempengaruhi Abu Yazid al-Busthami dan orang-orang berjiwa sehat (al-ashihha) lainnya."
Hal itu menurut Ibn Taimiyah sejalan dengan makna-makna hadis qudsi yang diriwayatkan oleh al-Bukhari. Dalam hadis itu disebutkan bahwa apabila seorang hamba selalu berupaya menempuh jalan pendekatan diri kepada Allah dengan melaksanakan secara intensif al-faraidh (perkara-perkara yang diwajibkan) dan al-nawafil (perkara-perkara yang disunnahkan), sebuah upaya yang bermuara pada suatu keadaan (hal) yang dalam hadis itu diungkapkan dengan “sampai Aku mencintainya” (hatta uhibahu),“maka Akulah yang menjadi telinga, mata, tangan dan kakinya.” Semua ini dikemukakan Ibn Taimiyah ketika ia membela ahli tarekat yang sejalan dengan sunnah.
Di sela-sela pembelaan ini ia menegaskan: Polok-pokok madzab ahli tarekat yang Islami adalah mengikuti para nabi dan para rasul.
Thariqah, Cara Mengamalkan Syari’ah
Dengan mengacu pada uraian sebelumnya dapat dipahami bahwa thariqah atau thariq al-shafiyyah ‘jalan para sufi’ pada hakikatnya adalah “jalan yang ditempuh oleh para nabi dan rasul dalam merealisasikan penghambaan diri dan tauhid yang murni dengan cara mengosongkan kalbu dari hal-hal selain Allah serta memenuhinya dengan dzikrullah dalam setiap keadaan (berdiri, duduk, dan berbaring),” dengan kata lain, thariqah pada dasarnya adalah “pengamalan syari’ah dalam kerangka tauhid dan ubudiyah.”
Penjelasan yang lebih gamblang mengenai posisi thariqah sebagai pengamalan syari’ah dalam kerangka tauhid dan ubudiyah dapat disimak pula dari pernyataan Al-Mukarram Saidi Syekh Prof. Dr. H. Kadirun Yahya berikut:
“Tarikat adalah cara mengamalkan syariat dan menghayati inti daripada hakikat syariat itu sendiri serta menjauhkan diri dari hal-hal yang melalaikan pelaksanaannya serta menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh syariat itu sendiri.”
“Tarikat itu adalah pengamalan syariat itu sendiri. Kita harus masuk agama Islam secara keseluruahan, melaksanakan syariat dan hakikat zahir dan batin.”
“Tarikat itu harus berada dalam Islam, sesaui dengan Al Qur’an dan Al Hadis. Segala tarikat yang tidak sesuai dengan Islam adalah salah. Orang tarikat harus bersyariat, oleh sebab itu zaman dahulu selesai syariat dulu baru masuk tarikat. Dengan kata lain, Tarikat yang suci harus berdiri di atas syariat yang murni.”
“Sasaran orang yang bertarikat adalah mencari ridha Allah semata dan memurnikan tauhid kepada-Nya. Tauhid dijadikan pola pikir, dalam bersikap “Ilahi anta maqshuudii waridhaaka mathluubii” dalam bertindak sesuai dengan Al Qur’an dan Al Hadis.
Ketika beliau ditanya, “Apakah tarikat itu perlu?” beliau menjawab, “Perlu atau tidaknnya tarikat jangan dipersoalkan. Yang perlu adalah bagaimana janji Al Qur’an bisa kita realisasikan. Janji Al Qur’an ternyata selalu dapat direalisasikan oleh Syekh-Syekh tarikat.
Di dalam janji al-Quran yang seringkali terdengar kumandangnya di mimbar-mimbar-mimbar adalah bahwa umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (khair ummat ukhrijat li al-nas) [Ali Imran, 3:110], dan sekaligus umat pilihan yang adil untuk menjadi saksi atas manusia (ummat wasathan litakuna syuhada li al-nas) [Al-Baqarah, 2:143]. Agama mereka pun merupakan agama yang tidak tertanding dalam semua aspek sebagaimana ditegaskan oleh Nabi saw.: Al-Islam ya’lu wa la yu’la ‘alaih (Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih darinya)” [Shahih al-Bukhari 1:454]. Hal ini sekaligus mengandung arti bahwa umat Islam juga tidak tertandingi. Kenyataanya, hingga saat ini umat Islam masih terpuruk dan lebih banyak menjadi penonton daripada pemain di panggung peradaban.
Pernyataan al-Quran, “Betapa sering kelompok yang sedikit mampu …banyak “ [Al- Baqarah, 2:249], Justru sekarang lebih banyak berlaku untuk umat yang lain daripada umat Islam sendiri yang notabene merupakan mayoritas. Hal ini tiada lain karena umat Islam hanya terpaku pada formalitas agama (fikih atau syari’ah dalam arti sempit) yang saat ini justru selalu menjadi sumber khilafiah berkepanjangan. Pada umumnya mereka mengamalkan sya’riah tanpa melibatkan thariqah, padahal di dalam thariqah-sebagaimana ditegaskan dan dibuktikan oleh Al-Mukarram Said Syekh Prof. Dr. H. Kadirun Yahya-tersembunyi apa yang oleh beliau disebut “teknologi al-Quran,” suatu teknologi yang mampu melahirkan energi ketuhanan yang maha dahsyat sebagai sumber senjata untuk mengusir iblis la’natullah, musuh paling nyata setiap mukmin, sehingga pada gilirannya mereka mampu menegakkan shalat al khasyi’in yang juga menjadi kunci mutlak kemenangan itu sendiri. ...
Allahumma shalli wasallim alaa hazarroosuulil 'aziim
wa'ala alihi wa ashaabihi waman tabiahum ilaa yaumiddin.
Ya Allah, salam dan salawat pada junjungan nabi besar Rasulullah saw, para keluarganya, para sahabatnya dan kepada siapa saja yang mengikuti mereka sampai akhir zaman.
Pendahuluan
Umat Islam dalam perjalanan sejarahnya tidak pernah bebas dari perselisihan antarsesama yang kadang-kadang memuncak sampai pada level yang sangat memprihatinkan. Banyak sekali faktor-faktor yang memicu kondisi semacam ini. Selain kepentingan politik dan ekonomi, salah satu faktor yang sangat dominan dan menghambat terciptanya kesatuan dan persatuan umat Islam dalam suasana ukhuwah yang mesra adalah sikap tamaththu’ (sok suci, konsekuen), tatharruf (ekstrem) dan ta’ashshub (fanatik), sebuah sikap yang membuat pemiliknya cenderung memutlakkan pendapat dan pemahaman sendiri sebagai yang paling benar tanpa mencoba memahami secara bijak pendapat dan pemahaman orang lain. Sikap ini bahkan kerapkali melahirkan kegemaran menghakimi dan memvonis orang lain sebagai sesat dan menyesatkan. Faktor lain yang justru menjadi pangkal dari sikap ini adalah literatur dan informasi yang tidak memadai sehingga menimbulkan pemahaman yang tidak utuh.
Tasawuf dan tarikat adalah korban yang paling sering dihujat sesat oleh saudara-saudara seiman yang didominasi oleh sikap tersebut. Mereka memandang tasawuf dan tarikat sebagai sarang bid’ah – hal-hal yang baru yang diklaim tidak pernah diajarkan dalam Islam atau tidak pernah dilakukan dan diperintahkan oleh Rasul Dalil utama yang sering dikemukakan mereka adalah hadis Nabi saw yang sangat terkenal dan diriwayatkan oleh banyak imam hadis,
“Hindarilah perkara-perkara yang baru (diada-adakan), karena setiap perkara yang baru adalah bid’ah, dan bid’ah adalah sesat.”
Benarkah tasawuf dan tarikat itu bid’ah?
Makalah ini sebagaimana tampak dalam judulnya mencoba menyingkap dalil-dalil naqli (al-Qur’an dan al-Sunnah) yang mendasari keabsahan tasawuf dan tarikat, didukung oleh pendapat dan penjelasan para ulama mengenai hal-hal terkait.
Pengertian Tasawuf
Banyak sekali definisi tasawuf yang telah dikemukakan, dan masing-masing berusaha menggambarkan apa yang dimaksud dengan tasawuf. Tetapi pada umumnya definisi yang dikemukakan hanya menyentuh sebagian dari keseluruhan bangunan tasawuf yang begitu besar dan luas.
Definisi-definisi yang dikemukakan sama dengan yang dilakukan empat orang buta, dalam kisah Rumi, ketika mereka menggambarkan bentuk gajah. Masing-masing menggambarkan bentuk gajah sesuai dengan bagian tubuh yang disentuhnya. Bagi yang pertama, bentuk gajah seperti mahkota, bagi yang kedua seperti pipa air, bagi yang ketiga, seperti kipas, dan bagi yang terakhir seperti tiang.
Imam al-Qusyairi dalam al-Risalah-nya mengutip 50 definisi dari ulama Salafi; sementara Imam Abu Nu'aim al-Ishbahani dalam "Ensiklopedia Orang-Orang Suci"-nya Hikayat al-awliya' mengutip sekitar 141 definisi, antara lain:
"Tasawuf adalah bersungguh-sungguh melakukan suluk yaitu `perjalanan' menuju malik al muluk `Raja semua raja' (Allah `assa wa jalla)."
"Tasawuf adalah mencari wasilah `alat yang menyampaikan' ke puncak fadhilah `keutamaan'."
Definisi paling panjang yang dikutip Abu Nu'aim berasal dari perkataan Imam al-Junaid ra. ketika ditanya orang mengenai makna tasawuf:
"Tasawuf adalah sebuah istilah yang menghimpun sepuluh makna: 1. tidak terikat dengan semua yang ada di dunia sehingga tidak berlomba- lomba mengerjarnya. 2. Selalu bersandar kepada Allah `azza wa jalla,. 3. Gemar melakukan ibadah ketika sehat. 4. Sabar kehilangan dunia (harta). 5. Cermat dan berhati-hati membedakan yang hak dan yang batil. 6. Sibuk dengan Allah dan tidak sibuk dengan yang lain. 7. Melazimkan dzikir khafi (dzikir hati). 8. Merealisasikan rasa ikhlas ketika muncul godaan. 9. Tetap yakin ketika muncul keraguan dan 10. Teguh kepada Allah dalam semua keadaan. Jika semua ini berhimpun dalam diri seseorang, maka ia layak menyandang istilah ini; dan jika tidak, maka ia adalah pendusta. [Hilayat al-Awliya]
Beberapa fuqaha `ahli fikih' juga mengemukakan definisi tasawuf dan mengakui keabsahan tasawuf sebagai ilmu kerohanian Islam. Di antara mereka adalah: Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Jazi al-Kalabi al-Gharnathi (w. 741 H.) dalam kitabnya al Qawanin al Fiqhiyyah li Ibn Jazi hal. 277 menegaskan:
"Tasawuf masuk dalam jalur fiqih, karena ia pada hakikatnya adalah fiqih batin (rohani), sebagaimana fiqih itu sendiri adalah hukum-hukum yang berkenaan dengan perilaku lahir."
Imam `Abd al-Hamid al-Syarwani, dalam kitabnya Hawasyi al-Syarwani VII, menyatakan: "Ilmu batin (kerohanian), yaitu ilmu yang mengkaji hal ihwal batin (rohani), yakni yang mengkaji perilaku jiwa yang buruk dan yang baik (terpuji),itulah ilmu tasawuf."
Imam Muhammad `Amim al-Ihsan dalam kitabnya Qawa'id al-Fiqih, dengan mengutip pendapat Imam al-Ghazali, menyatakan:
"Tasawuf terdiri atas dua hal: Bergaul dengan Allah secara benar dan bergaul dengan manusia secara baik. Setiap orang yang benar bergaul dengan Allah dan baik bergaul dengan mahluk, maka ia adalah sufi."
Definisi-definisi tersebut pada dasarnya saling melengkapi satu sama lain, membentuk satu kesatuan yang tersimpul dalam satu buhul: "Tasawuf adalah perjalanan menuju Tuhan melalui penyucian jiwa yang dilakukan dengan intensifikasi dzikrullah".
Penyucian jiwa (tazkiyah an-nafs) merupakan ruh dari takwa, sementara takwa merupakan sebaik-baik bekal (dalam perjalanan menuju Allah), sehingga dikatakan oleh Imam Muhammad Zaki Ibrahim, pemimpin tarikat sufi Al-Asyirah Al-Muhammadiyyah di Mesir, bahwa "tasawuf adalah takwa. Takwa tidak hanya berarti "mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-Nya. Takwa juga meliputi "cinta, ikhlas, sabar, zuhud, qana'ah, tawadhu', dan perilaku-perilaku batin lainnya yang masuk ke dalam kategori makarim al-akhlaq (alkhlak yang mulia) atau al-akhlaq al-mahmudah (akhlak yang terpuji)".
Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila tasawuf juga sering didefinisikan sebagai akhlak, yaitu akhlak bergaul dengan Allah dan akhlak bergaul dengan semua makhluk-Nya. Imam Muhammad ibn `Ali al-Kattani, sebagaimana dikutip oleh Imam al-Qusyairi dalam al-Risalah-nya, menegaskan bahwa "tasawuf adalah akhlak". Imam Abu Nu'aim al-Ishbahani juga mengutip definisi senada dalam Hilyat al-Awliya-nya:
"Tasawuf adalah berakhlak dengan akhlak (orang-orang ) mulia."
Definisi terakhir di atas sejalan dengan keberadaan Nabi SAW yang diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia sebagaimana ditegaskan oleh beliau sendiri dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal
"Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik." Para perawi hadis ini adalah para perawi sahih (rijal al-shahih). [Majma' al-Zawaid, VIII:188]
Akhlak itu sendiri merupakan perilaku batin yang melahirkan berbagai perbuatan secara otomatis tanpa melalui pertimbangan yang disengaja, atau dalam definisi Imam al-Ghazali diungkapkan dengan redaksi: "Akhlak merupakan ungkapan tentang kondisi yang berakar kuat dalam jiwa; dari kondisi itu lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikirkan dan pertimbangan."
Apa pun definisi yang dikemukakan para ulama mengenai tasawuf, satu hal pasti adalah bahwa tasawuf merupakan sisi rohani Islam yang sangat fundamental dan esensial; bahkan ia merupakan inti ajaran yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul.
Pernyataan Imam Muhammad Zaki Ibrahim barangkali sudah cukup sebagai penjelasan terakhir: "Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai definisi tasawuf, semua definisi yang ada mengarah kepada satu titik yang sama, yaitu taqwa dan tazkiyah. Tasawuf adalah hijrah menuju Allah SWT, dan pada hakikatnya semua definisi yang ada bersifat saling melengkapi." [Abjadiyyah al-Tashawwuf al-Islami, atau Tasawuf Salafi, hlm 7.]
Tidak satu definisi-pun yang mampu menggambarkan secara utuh apa yang disebut dengan tasawuf. Demikian pula, tidak ada satu penjelasan pun yang mampu menggambarkan apa yang disebut denga ihsan `beribadah seolah-olah melihat Allah', karena hal itu menyangkut soal rasa dan "pengalaman", bukan penalaran atau pemikiran. Pemahaman yang utuh mengenai tasawuf dan sekaligus ihsan hanya muncul setelah seseorang "mengalami" dan tidak sekadar "membaca" definisi-definisi yang dikemukakan orang.
“Tasawuf adalah sebuah istilah yang menghimpun sepuluh makna: 1. tidak terikat dengan semua yang ada di dunia sehingga tidak berlomba-lomba mengerjarnya. 2. Selalu bersandar kepada Allah ‘azza wa jalla,. 3. Gemar melakukan ibadah ketika sehat. 4. Sabar kehilangan dunia (harta). 5. Cermat dan berhati-hati membedakan yang hak dan yang batil. 6. Sibuk dengan Allah dan tidak sibuk dengan yang lain. 7. Melazimkan dzikir khafi (dzikir hati). 8. Merealisasikan rasa ikhlas ketika muncul godaan. 9. Tetap yakin ketika muncul keraguan dan 10. Teguh kepada Allah dalam semua keadaan. Jika semua ini berhimpun dalam diri seseorang, maka ia layak menyandang istilah ini; dan jika tidak, maka ia adalah pendusta. [Hilayat al-Awliya]
Beberapa fuqaha ‘ahli fikih’ juga mengemukakan definisi tasawuf dan mengakui keabsahan tasawuf sebagai ilmu kerohanian Islam. Di antara mereka adalah: Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Jazi al-Kalabi al-Gharnathi (w. 741 H.) dalam kitabnya al Qawanin al Fiqhiyyah li Ibn Jazi hal. 277 menegaskan:
“Tasawuf masuk dalam jalur fiqih, karena ia pada hakikatnya adalah fiqih batin (rohani), sebagaimana fiqih itu sendiri adalah hukum-hukum yang berkenaan perilaku lahir.”
Imam ‘Abd al-Hamid al-Syarwani, dalam kitabnya Hawasyi al-Syarwani VII, menyatakan: “Ilmu batin (kerohanian), yaitu ilmu yang mengkaji hal ihwal batin (rohani), yakni yang mengkaji perilaku jiwa yang buruk dan yang baik (terpuji), itulah ilmu tasawuf.”
Imam Muhammad ‘Amin al-Ihsan dalam kitabnya Qawa’id al-Fiqih, dengan mengutip pendapat Imam al-Ghazali, menyatakan:
“Tasawuf terdiri atas dua hal: Bergaul dengan Allah secara benar dan bergaul dengan manusia secara baik. Setiap orang yang benar bergaul dengan Allah dan baik bergaul dengan mahluk, maka ia adalah sufi.”
Definisi-definisi tersebut pada dasarnya saling melengkapi satu sama lain, membentuk satu kesatuan yang tersimpul dalam satu buhul: “Tasawuf adalah perjalanan menuju Tuhan melalui penyucian jiwa yang dilakukan dengan intensifikasi dzikrullah”. Penyucian jiwa (tazkiyah an-nafs) merupakan ruh dari takwa, sementara takwa merupakan sebaik-baik bekal (dalam perjalanan menuju Allah), sehingga dikatakan oleh Imam Muhammad Zaki Ibrahim, pemimpin tarikat sufi Al-Asyirah Al-Muhammadiyyah di Mesir, bahwa “tasawuf adalah takwa".
Takwa tidak hanya berarti “mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-Nya. Takwa juga meliputi “cinta, ikhlas, sabar, zuhud, qana’ah, tawadhu’, dan perilaku-perilaku batin lainnya yang masuk ke dalam kategori makarim al-akhlaq (alkhlak yang mulia) atau al-akhlaq al-mahmudah (akhlak yang terpuji)”. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila tasawuf juga sering didefinisikan sebagai akhlak, yaitu akhlak bergaul dengan Allah dan akhlak bergaul dengan semua makhluk-Nya. Imam Muhammad ibn ‘Ali al-Kattani, sebagaimana dikutip oleh Imam al-Qusyairi dalam al-Risalah-nya, menegaskan bahwa “tasawuf adalah akhlak”. Imam Abu Nu’aim al-Ishbahani juga mengutip definisi senada dalam Hilyat al-Awliya-nya: “Tasawuf adalah berakhlak dengan akhlak (orang-orang ) mulia.”
Definisi terakhir di atas sejalan dengan keberadaan Nabi saw yang diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia sebagaimana ditegaskan oleh beliau sendiri dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal:
“Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik.”
Para perawi hadis ini adalah para perawi sahih (rijal al-shahih). [Majma’ al-Zawaid, VIII:188] Akhlak itu sendiri merupakan perilaku batin yang melahirkan berbagai perbuatan secara otomatis tanpa melalui pertimbangan yang disengaja, atau dalam definisi Imam al-Ghazali diungkapkan dengan redaksi: “Akhlak merupakan ungkapan tentang kondisi yang berakar kuat dalam jiwa; dari kondisi itu lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikirkan dan pertimbangan.”
Apa pun definisi yang dikemukakan para ulama mengenai tasawuf, satu hal pasti adalah bahwa tasawuf merupakan sisi rohani Islam yang sangat fundamental dan esensial; bahkan ia merupakan inti ajaran yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul. Perbedaan-perbedaan penggambaran bentuk gajah yang dilakukan oleh empat orang buta dalam kisah Rumi. Pernyataan Imam Muhammad Zaki Ibrahim mengenai perbedaan-perbedaan ini barangkali sudah cukup sebagai penjelasan terakhir: “Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai definisi tasawuf, semua definisi yang ada mengarah kepada satu titik yang sama, yaitu taqwa dan tazkiyah. Tasawuf adalah hijrah menuju Allah SWT, dan pada hakikatnya semua definisi yang ada bersifat saling melengkapi.” [Abjadiyyah al-Tashawwuf al-Islami, atau Tasawuf Salafi, hlm 7.]
Tidak satu definisi pun yang mampu menggambarkan secara utuh apa yang disebut dengan tasawuf. Demikian pula, tidak ada satu penjelasan pun yang mampu menggambarkan apa yang disebut denga ihsan ‘beribadah seolah-olah melihat Allah’, karena hal itu menyangkut soal rasa dan “pengalaman”, bukan penalaran atau pemikiran. Pemahaman yang utuh mengenai tsawuf dan sekaligus ihsan hanya muncul setelah seseorang “mengalami” dan tidak sekadar “membaca” definisi-definisi yang dikemukakan orang.
Posisi Tasawuf dalam Ilmu-Ilmu Islam
Prof. Dr. H. S.S. Kadirun Yahya Al-Khalidi menyatakan bahwa Tasawuf adalah “Saudara Kembar” Fiqih. Pernyataan ini tampaknya berdasarkan pada kenyataan bahwa Fiqih pada hakikatnya merupakan formulasi lebih lanjut dari konsep Islam, sementara Tasawuf merupakan perwujudan konkret dari konsep Ihsan. Dua konsep ini tercetus bersama-sama dengan konsep Iman (diformulasikan lebih jauh dalam ilmu kalam) dalam dialog antara Jibril AS dan Nabi SAW sebagaimana dikemukakan dalam hadist Abu Hurairah yang sangat terkenal. [Shahih al-Bukhari, I:27; Shahih Muslim, L:39]
Penjelasan lebih gamblang mengenai posisi Tasawuf sebagai “saudara kembar” Fiqih dikemukakan oleh Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka) dalam bukunya Tasawuf, Perkembangan dan Pemurniannya:
“Alhasil kemurnian dan cita-cita Islam yang tinggi adalah gabungan Tasauf dan Fiqih: gabungan otak dan hati. Dengan Fiqih kita menentukan batas-batas hukum, dan dengan Tasauf kita memberi pelita dalam jiwa, sehingga tidak terasa berat di dalam melakukan segala kehendak agama.
“Kalau kita tilik kepada bunyi Hadist tentang Islam, Iman dan Ihsan tampaklah bahwa ketiga Ilmu Islam yaitu Ilmu Fiqih, Ilmu Ushuluddin dan Ilmu Tasawuf telah dapat menyempurnakan ketiga simpulan agama itu (Islam, Iman dan Ihsan).
“Islam diartikan oleh hadist itu ialah mengucapkan Syahadat, mengerjakan Shalat lima waktu, Puasa bulan Ramadhan, mengeluarkan Zakat dan Naik Haji. Untuk mengetahui, sehingga kita mengerjakan suruhan agama dengan tidak membuta: Kita pelajarilah Fiqih.
“Iman adalah Iman kepada Allah, kepada Malaikat, kepada Rasul-Rasul dan Kitab-Kitab, dan iman kepada Hari Kiamat dan Takdir, buruk dan baik, Kita pelajarilah Ushuluddin atau Ilmu Kalaam."
“Ihsan adalah kunci daripada semuanya, yaitu: Bahwa kita mengabdi kepada Allah SWT, seakan-akan Allah SWT itu kita lihat di hadapan kita sendiri. Karena meskipun mata kita tidak dapat melihatNya, namun Allah SWT tetap melihat kita. Untuk menyempurnakan ihsan itu, kita masuki alam Tasawuf.
“Itulah tali berpilah tiga: Iman, Islam dan Ihsan. Dicapai dengan tiga ilmu: Fiqih, Ushuluddin dan Tasawuf. [Tasawuf, Perkembangan dan Pemurniannya, hal. 94-95]
Jadi, sebagai sebuah ilmu, posisi Tasawuf terhadap ilmu-ilmu Islam lainnya sangat jelas dan gamblang. Tasawuf merupakan bagian tak berpisahkan dari keseluruhan bangunan Syari’ah; bahkan ia merupakan ruh/hakikat/inti dari syariah.
Syariah sendiri dapat didefinisikan sebagai “segala sesuatu yang terbit dari diri Nabi SAW yang berupa sikap, perbuatan, dan perkataan (al-Qur’an dan al-Hadist)”; atau dengan bahasa yang lebih umum: Syariah adalah segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Namun begitu, syariah pada dasarnya merupakan produk dari hakikat Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Allah.
Adalah mustahil memahami syariah (produk) secara sempurna tanpa memahami hakikatnya. Ilmu yang menyajikan jalan untuk mengenal hakikat ini adalah Tasawuf, sedangkan ilmu-ilmu (keislaman) lainnya, seperti ilmu Fiqih dan hadist misalnya, semuanya menyajikan jalan untuk memahami produk. Tasawuf melibatkan hati atau qalbu (ruhani), sedangkan ilmu-ilmu lainnya melibatkan otak atau akal (jasmani).
Fiqih dan Tasawuf ibarat dua sisi mata uang, jika salah satu rusak maka yang lain menjadi tidak berfungsi, sehingga kedua-duanya harus dipegang secara utuh untuk mencapai kesempurnaan. Dalam kaitan ini, Imam Abu Abdillah al-Dzahabi (w. 748 H), penulis kitab Siyar A’lam al-Nubala’ (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1413) yang terdiri dari 23 jilid menegaskan:
“Jika seorang ulama tidak ber-Tasawuf, maka ia kosong; sebagaimana jika seorang sufi tidak mengenal sunnah (baca bersyariat), maka ia tergelincir dari jalan yang lurus.”
Imam Malik ibn Anas, pemimpin madzhab Maliki yang sangat terkenal, sebagaimana dikutip oleh Syeikh Amin al-Kurdi, juga mengungkapkan hal senada:
“Barangsiapa yang bersyariat tetapi tidak berhakikat (ber-Tasawuf) maka ia telah fasik; dan barangsiapa yang berhakikat (ber-Tasawuf) tetapi tidak bersyariat maka ia telah zindik.” [Tanwir al-Qulub, hal. 408]
Di samping itu, tidak salah apabila dikatakan bahwa Tasawuf adalah sebuah madzhab sebagaimana Ilmu Fiqih yang mengenal (minimal) empat mazhab, sehingga tidak jarang para ulama melibatkan pendapat kaum sufi ketika membahas hukum suatu perkara. Syeikh al-Islam Ibn Taymiyah menempatkan kaum sufi dalam deretan fuqaha’ dan ahli hadist. Hal ini dapat disimak misalnya dari pernyataan beliau ketika menetapkan hukum larangan menikahi orang yang menolak kekhalifahan Sayyidina Ali setelah ‘Utsman ibn ‘Affan:
Hal itu (larangan menikahi orang yang tidak menerima kekhalifahan Ali ibn Abi Thalib) telah disepakati oleh para fuqaha, ahli hadist, dan juga oleh ahli ma’rifat dan Tasawuf. [Kutub wa Rasail wa Fatawa Ibn Taimiyah, XXXV:19]
Pandangan Ibn Taimiyah dan Ibn al-Qayyim
Syeikh al-Islam Ibn Taimiyah dan Ibn al-Qayyim al-Jawziyah adalah sepasang guru-murid yang mendukung dan mengakui kebenaran Tasawuf sebagai ilmu yang dapat membersihkan jiwa.
Ibn Taimiyah, misalnya, menyebut para sufi dengan sebutan ahl ‘ulum al-qulub/pakar-pakar ilmu hati’ yang perkataanya paling tepat dan paling baik realisasinya (asaddu wa ajwadu tahqiqan) serta paling jauh dari bid’ah (ab’adu minal bid’ah). Dalam kitabnya yang sangat terkenal Majmu’ al-Fatawa (Beirut: Dar al-Kitab al Arabi, 1973).
Dalam kitabnya Amradh al-Qulub wa Syifauha (Kairo: al-Mathba’ah al-Salafiyyah, 1399), hal. 62, ketika berbicara surah al-Kafirun), Ibn Taimiyah berkata: “Adapun qul ya ayyuhal kafiruun mengundang tauhid amali iradi, tauhid praktis yang didasarkan pada kehendak, yaitu keikhlasan beragama semata-mata untuk Allah dengan sengaja dan dikehendaki; dan itulah yang dibicarakan oleh syeikh-syeikh Tasawuf pada umumnya.
“Imam-imam Tasawuf menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang dicintai dengan cinta yang hakiki, bahkan dengan cinta yang paling sempurna.” [Amradh al-Qulub, hal. 68]
Adapun Ibn al-Qayyim, dalam kitabnya Madarij al-Salikhln, I:464 (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1973), memperkatakan mengenai Abu Yazid al-Busthami dengan redaksi:
“Ini (memelihara dan menjauhkan keinginan dari selain Allah yang Maha Suci) seperti kondisi Abu Yazid al-Busthami – semoga Allah merahmatinya – menganai berita tentang dirinya ketika ia ditanya, ‘Apa yang engkau inginkan (kehendak)?’; ia menjawab, ‘Aku ingin agar aku tidak ingin yang kedua (setelah Allah),’ inilah hakikat Tasawuf.”
Dalam kitabnya yang lain Badai al-Fawaid, III:756 (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Nizar Mushthafa al-Baz, 1996), Ibn al-Qayyim berkata:
“Tasawuf dan kefakiran (baca: hanya butuh kepada Allah) berada pada wilayah hati”.
Thariqah dalam Al-Quran dan al-Hadis
Thariqah (Ind. Tarekat) adalah jalan yang dilalui oleh orang sufi dalam perjalanannya menuju Tuhan, dan digambarkan sebagai jalan yang berpangkal pada syari’ah, sebab jalan utama disebut syar’ sedangkan anak jalan disebut thariq. Kata ini terambil dari kata tharq yang di antara maknanya adalah “mengetuk” seperti dalam ungkapan tharq al-bab yang berarti “mengetuk pintu”; karena itu, cara beribadah seorang sufi disebut thriqah karena ia dalam ibadahnya selalu mengetuk pintu hatinya dengan dzikrullah. Cara beribadah semacam ini oleh Nabi disebut dengan thariqah hasanah ‘cara yang baik’. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dalam Musnadnya dengan perawi-perawi tsiqat ‘dipercaya’ Nabi saw bersabda:
“Sesungguhnya seorang hamba jika berpijak pada thariqah yang baik dalam beribadah, kemudian ia sakit, maka dikatakan (oleh Allah) kepada malaikat yang mengurusnya, ‘Tulislah untuk orang itu pahala yang sepadan dengan amalnya apabila ia sembuh sampai Aku menyembuhkannya atau mengembalikannya kepada-Ku.’(Musnad Ahmad, 11: 203.)
Ungkapan thariqah hasanah dalam hadis tersebut menunjukan kepada perlaku hati yang diliputi kondisi ihsan’beribadah seolah –olah melihat Tuhan atau kondisi khusyu’ yakin berjumpa dengan Tuhan dan kembali kepada-Nya,’ (Al-Baqarah, 2: 46) sebab ibadah (misalnya salat) yang dilakukan dengan hati yang lalai oleh Nabi disebut sebagai shalat al-munafiq ‘salatnya orang munafik’, yaitu yang didalamnya ia tidak berdzikir kepada Allah kecuali sedikit (la yadzkurullaha fiha illa qalilan) Shahih Muslim, 1: 434, dan pelakunya oleh Tuhan diancam dengan al-wayl. (Al-Maun, 107: 4-5).
Didalam al-Quran pun kata thariqah muncul dalam konteks dzikrullah sebagai aktualisasi tauhid yang sempurna.
Setelah Allah menjanjikan karunia yang banyak kepada orang-orang yang istiqamah di atas thariqah, Dia langsung memberikan ancaman siksa yang sangat pedih kepada orang yang tidak mau berdzikir kepada-Nya:
“Seandainya mereka istiqamah di atas thariqah niscaya Kami beri minum mereka dengan air yng melimpah (karunia yang banyak): untuk Kami uji mereka di dalamnya, dan barang siapa tidak mau berdzikir kepada Tuhannya, niscaya Dia menimpakan azab yang sangat pedih.” (Al-Jinn, 72: 16-17)
Ibn al-Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarij al-Salikin mengutip perkataan Abu Bakar al-Shiddiq r.a. ketika menyingung ayat tersebut. Sahabat agung ini pernah ditanya mengenai maksud al-istiqamah ala al-thariqah dan ia menjawab, “hendaknya engkau tidak menyekutukan Allah dengan sesuat (an la tusyrika billahi syay-an).” Jadi, kata Ibn al-Qayyim, yang dimaksud (al-istiqamah ‘ala al-thariqah) oleh Abu Bakar al-Shiddiq r.a. adalah al-istiqamah ala mahdhi al-tauhid konsisten di atas tauhid yang murni artinya, thariqah dalam ayat tersebut adalah”jalan menuju tauhid yang murni”.
Tauhid yang murni ini pulalah yang menjadi tujuan syekh-syekh tarekat sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibn Taimiyah:
“Tauhid inilah yang dibawa oleh para rasul dan kitab-kitab Allah dan yang diisyaratkan oleh syeikh-syeikh tarekat dan pakar-pakar agama."
Dalam ayat yang lain thariqah disandingkan dengan syari’ah yaitu ketika Allah berfirman:
“Bagi tiap-tiap umat di antara kamu Kami berikan syir’ah (peraturan) dan minhaj (metode).” (Al-Maidah, 5:48)
Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa syir’ah dalam ayat tersebut adalah syari’ah (peraturan) sedangkan minhaj adalah thariqah (metode pelaksanaan syari’ah), dan kedua-dua (syari’ah dan thariqah) secara simultan bermuara pada tujuan pokok yang merupakan haqiqat al-din (hakikat agama), yaitu tauhid yang murni, atau hanya menyembah Allah semata (ibadat Allah wahdah).
Thariqah dalam pandangan Ibn Taimiyah
Penjelasan Ibn Taimiyah mengenai tarekat sangat penting untuk dikemukakkan lebih jauh disini, sebab sekali lagi selama ini ia sering dituding sebagai anti tarekat dan bahkan dijadikan rujukan utama oleh sebagian kecil umat untuk menentang tarekat, padahal Ibn Taimiyah tidak pernah menentang tarekat/tasawuf kecuali yang nyata sekali bertentangan dengan Al-Quran dan al-Sunnah.
Ketika memuji Imam al-Junaid al-Baghdadi berkenaan dengan kewajiban seorang salik orang yang berjalan menuju Tuhan agar mengenal Sang Pencipta (ma’rifat al-shani) sehingga dapat beramal dan berubudiyah secara ikhlas, Ibn Taimiyah menegaskan dalam kitabnya al-Istiqamah:
“Ini (mengenal sang Pencipta) termasuk di antara pokok-pokok akidah ahlu-sunnah dan imam-imam para Syeikh, khususnya syekh-syekh sufi, karena pokok pangkal tarekat para sufi adalah kehendak (al-iradah), yang merupakan fondasi amal. Mereka dalam hal kehendak, ibadah, amal dan akhlak lebih besar ketehuhannya daripada dalam hal perkataan dan ilmu pengetahuannya. Mereka dengan semua itu lebih besar perhatiannya dan lebih banyak pemeliharaanya. Orang yang belum memasuki semua itu tidak dapat serta merta menjadi ahli tarekat mereka."
Dalam kitabnya yang lain al-Hasanah wa al-Sayyiah, Ibn Taimiyah menegaskan lebih lanjut bahwa orang yang mengikuti Imam al-Junaid adalah orang yang memperoleh hidayah, selamat dan bahagia:
“Barang siapa menempuh jalan yang ditempuh oleh al-Junaid yang merupakan salah seorang pakar tasawuf dan ma’rifah, maka ia benar-benar telah mendapat hidayah, selamat dan bahagia."
Selain Imam al-Junaid al-Baghdadi, Ibn Taimiyah juga memuji dan membela syekh syekh tarekat lainnya, seperti: Abu Yazid al-Busthami, Syekh Abd al-Qadir al-Jailani, dan bahkan juga Imam al-Ghazali. Tentang Syekh Abd al-Qadir al-Jailani, misalnya, Ibn Taimiyah menggambarkannnya sebagai berikut:
“Syekh Abd al-Qadir al-Jailani, misalnya, Ibn Taimiyah menggambarkannya sebagai berikut: “Shekh Abd al-Qadir al-Jailani dan Syekh tarekat seperti beliau merupakan syekh yang paling gigih memerintahkan menetapi syara, perintah dan larangan, serta mengedepankan agar meninggalkan keinginan dan kehendak nafsu, karena kesalahan dalam berkehendak dilihat dari segi kehendak itu sendiri hanya terjadi dari sisi hawa nafsu ini. Beliau memerintahkan seorang salik ‘murid yang menempuh suluk (perjalanan) menuju Tuhan’ agar tidak memiliki sama sekali kehendak yang bersumber dari hawa nafsu melainkan ia berkehendak sesuai dengan yang dikehendaki Allah ‘azza wa jalla."
Pada bagian sebelumnya sudah disinggung bahwa Ibn Taimiyah menyebut para sufi sebagai ahl ulum al-qulub ‘pakar-pakar ilmu hati yang bebas dari bid’ah ketika ia mengatakan:
“Perkataan pakar-pakar ilmu hati dari kalangan sufi dan yang selain mereka, seperti Abu Hamid al-Ghazali pula Ibn Taimiyah mengutip pernyataan yang mengukuhkan kebenaran tarikat para sufi:
“Tarekat para sufi adalah tujuan (ghayah), karena mereka menyucikan kalbu mereka dari hal-hal selain Allah dan memenuhinya dengan dzikrullah; dan ini merupakan prinsip dakwah para rasul. Pengakuan Ibn Taimiyah mengenai kebenaran tarekat para sufi juga mencuat dari pernyataanya yang dituangkan dalam kitabnya yang berjudul Syarh al-Aqidah al-Ishfahaniyah, yaitu ketika ia berbicara tentang mu’jizat para nabi: “ Tidak ada jalan bagi akal untuk memahami mukjizat para nabi hanya dengan komoditi akal semata. Hal-hal lain dari keistimewaan para nabi hanya dapat dipahami dengan rasa oleh orang yang menempuh tarekat tasawuf…"
Jika Nabi memiliki suatu keistimewaan yang Anda tidak punya modelnya, maka Anda sama sekali tidak akan memahami keistimewaan itu, apalagi membenarkannya, karena pembenaran hanya muncul setelah pemahaman, dan model yang dimaksudkan di sini terdapat di awal tarekat tasawuf…Adapun rasa (dzawq) maka ia seperti ‘menyaksikan’ dan ‘mengambil dengan tangan’dan hal itu tidak ada kecuali dalam tarekat para sufi.
Ibn Taimiyah bahkan tidak mengingkari konsep “mabuk” yang kadang-kadang melahirkan berbagai ungkapan yang sepintas terkesan berbau syirik tetapi sebenarnya tidak dimaksudkan demikian, ungkapan-ungkapan yang dikenal dengan syathahat.
Ungkapan-ungkapan pada dasarnya muncul secara otomatis dari kondisi fana (ekstase) yang sama sekali tidak dipengaruhi oleh pertimbangan atau kesadaran apa pun kecuali semata-mata karena terbuai oleh keagungan dan keindahan Tuhan. Dalam kaitan ini ia mengatakan:
“Sebagian tokoh sufi yang mengalami kondisi spiritual tertentu (dzawi al-ahwal) kadang-kadang mengalami ‘mabuk dan lenyap dari selain Allah’ dalam keadaaan fana’yang singkat. Keadaan mabuk seperti itu terjadi tanpa disengaja, tanpa pertimbangan. Kadang-kadang dalam keadaan itu ia berkata subhani (maha suci aku), atau ungkapan-ungkapan lain seperti yang mempengaruhi Abu Yazid al-Busthami dan orang-orang berjiwa sehat (al-ashihha) lainnya."
Hal itu menurut Ibn Taimiyah sejalan dengan makna-makna hadis qudsi yang diriwayatkan oleh al-Bukhari. Dalam hadis itu disebutkan bahwa apabila seorang hamba selalu berupaya menempuh jalan pendekatan diri kepada Allah dengan melaksanakan secara intensif al-faraidh (perkara-perkara yang diwajibkan) dan al-nawafil (perkara-perkara yang disunnahkan), sebuah upaya yang bermuara pada suatu keadaan (hal) yang dalam hadis itu diungkapkan dengan “sampai Aku mencintainya” (hatta uhibahu),“maka Akulah yang menjadi telinga, mata, tangan dan kakinya.” Semua ini dikemukakan Ibn Taimiyah ketika ia membela ahli tarekat yang sejalan dengan sunnah.
Di sela-sela pembelaan ini ia menegaskan: Polok-pokok madzab ahli tarekat yang Islami adalah mengikuti para nabi dan para rasul.
Thariqah, Cara Mengamalkan Syari’ah
Dengan mengacu pada uraian sebelumnya dapat dipahami bahwa thariqah atau thariq al-shafiyyah ‘jalan para sufi’ pada hakikatnya adalah “jalan yang ditempuh oleh para nabi dan rasul dalam merealisasikan penghambaan diri dan tauhid yang murni dengan cara mengosongkan kalbu dari hal-hal selain Allah serta memenuhinya dengan dzikrullah dalam setiap keadaan (berdiri, duduk, dan berbaring),” dengan kata lain, thariqah pada dasarnya adalah “pengamalan syari’ah dalam kerangka tauhid dan ubudiyah.”
Penjelasan yang lebih gamblang mengenai posisi thariqah sebagai pengamalan syari’ah dalam kerangka tauhid dan ubudiyah dapat disimak pula dari pernyataan Al-Mukarram Saidi Syekh Prof. Dr. H. Kadirun Yahya berikut:
“Tarikat adalah cara mengamalkan syariat dan menghayati inti daripada hakikat syariat itu sendiri serta menjauhkan diri dari hal-hal yang melalaikan pelaksanaannya serta menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh syariat itu sendiri.”
“Tarikat itu adalah pengamalan syariat itu sendiri. Kita harus masuk agama Islam secara keseluruahan, melaksanakan syariat dan hakikat zahir dan batin.”
“Tarikat itu harus berada dalam Islam, sesaui dengan Al Qur’an dan Al Hadis. Segala tarikat yang tidak sesuai dengan Islam adalah salah. Orang tarikat harus bersyariat, oleh sebab itu zaman dahulu selesai syariat dulu baru masuk tarikat. Dengan kata lain, Tarikat yang suci harus berdiri di atas syariat yang murni.”
“Sasaran orang yang bertarikat adalah mencari ridha Allah semata dan memurnikan tauhid kepada-Nya. Tauhid dijadikan pola pikir, dalam bersikap “Ilahi anta maqshuudii waridhaaka mathluubii” dalam bertindak sesuai dengan Al Qur’an dan Al Hadis.
Ketika beliau ditanya, “Apakah tarikat itu perlu?” beliau menjawab, “Perlu atau tidaknnya tarikat jangan dipersoalkan. Yang perlu adalah bagaimana janji Al Qur’an bisa kita realisasikan. Janji Al Qur’an ternyata selalu dapat direalisasikan oleh Syekh-Syekh tarikat.
Di dalam janji al-Quran yang seringkali terdengar kumandangnya di mimbar-mimbar-mimbar adalah bahwa umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (khair ummat ukhrijat li al-nas) [Ali Imran, 3:110], dan sekaligus umat pilihan yang adil untuk menjadi saksi atas manusia (ummat wasathan litakuna syuhada li al-nas) [Al-Baqarah, 2:143]. Agama mereka pun merupakan agama yang tidak tertanding dalam semua aspek sebagaimana ditegaskan oleh Nabi saw.: Al-Islam ya’lu wa la yu’la ‘alaih (Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih darinya)” [Shahih al-Bukhari 1:454]. Hal ini sekaligus mengandung arti bahwa umat Islam juga tidak tertandingi. Kenyataanya, hingga saat ini umat Islam masih terpuruk dan lebih banyak menjadi penonton daripada pemain di panggung peradaban.
Pernyataan al-Quran, “Betapa sering kelompok yang sedikit mampu …banyak “ [Al- Baqarah, 2:249], Justru sekarang lebih banyak berlaku untuk umat yang lain daripada umat Islam sendiri yang notabene merupakan mayoritas. Hal ini tiada lain karena umat Islam hanya terpaku pada formalitas agama (fikih atau syari’ah dalam arti sempit) yang saat ini justru selalu menjadi sumber khilafiah berkepanjangan. Pada umumnya mereka mengamalkan sya’riah tanpa melibatkan thariqah, padahal di dalam thariqah-sebagaimana ditegaskan dan dibuktikan oleh Al-Mukarram Said Syekh Prof. Dr. H. Kadirun Yahya-tersembunyi apa yang oleh beliau disebut “teknologi al-Quran,” suatu teknologi yang mampu melahirkan energi ketuhanan yang maha dahsyat sebagai sumber senjata untuk mengusir iblis la’natullah, musuh paling nyata setiap mukmin, sehingga pada gilirannya mereka mampu menegakkan shalat al khasyi’in yang juga menjadi kunci mutlak kemenangan itu sendiri. .
Thariqah, Jalan Menuju Ma’rifah
Pengamalan thariqah akan membuahkan apa yang disebut dengan haqiqah, dan jalan tritunggal syari’ah, thariqah, dan haqiqah, pada gilirannya akan membuahkan al-ma’rifah billah (mengenal Allah) yang oleh Nabi SAW disebut sebagai “pangkal ilmu” (ra’s al-‘ilm) [Musnad al-Rabi hlm. 311], bahkan juga “pangkal harta atau modal “ (ra’s al-mal) [Kasyf al-khafa’, II:6], semuanya tertuang secara ringkas dalam sabda Nabi SAW:
“Syari’ah adalah perkataanku, thariqah adalah perbuatanku, haqiqah adalah keadaan (batin)-ku, dan ma’rifah adalah pangkal harta (modal)-ku. [Kasyf al-Khafa,’II:6]”.
Mengenal Allah (al-ma’rifah billah) merupakan tujuan utama penciptaan makhluk. Dalam sebuah hadis Qudsi disebutkan:
“Dulu Aku adalah mutiara yang tersembunyi, lalu Aku ingin dikenal; maka Kuciptakan makhluk agar mereka mengenal-Ku” [Abjad al-Ulum, II:159].
Menurut al-Qari isi hadis tersebut sesuai dengan firman Tuhan, “Tidaklah Kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengabdi kepada-Ku” (wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li ya’buduni); karena ungkapan li ya’buduni ‘.
“Agar mereka mengabdi kepada-Ku” oleh Ibn Abbas ditafsirkan dengan li ya’rafuni ‘ yaitu agar mereka mengenal-Ku’ [Kasyf al-Khafa, II:173].
Penafsiran li ya’buduni dengan li ya’rafuni dikemukakan juga oleh para mufassir lainnya seperti Mujahid yang dikutip oleh al Tsa’alibi dalam Jawahir al-Hisan fi Tafsir al-Quran, al-Baghawi dalam Ma’alim al Tanzil, dan al-Qurthubi dalam al-Jami’ li Ahkam al-Quran, Abu al-Saud dalam Tafsir-nya, Ibn Juraij yang dikutip oleh Ibn Katsir dal Tafsir-nya, dan juga Imam al-Alusi dalam Ruh al-Ma’ani.
Mengenal Allah merupakan keharusan bagi seorang hamba yang ingin kembali kepada-Nya. Mengenal Allah juga berarti mengenal jalan kembali kepada-Nya. Jalan kembali ini pulalah yang sebenarnya juga disebut dengan thariqah, yaitu jalan yang memang disiapkan secara khusus untuk ditempuh oleh hati (qalb), jiwa (nafs) atau ruh (ruh), tiga istilah yang menunjuk kepada satu makna yang dalam bahasa Imam al-Ghazali disebut dengan lathifah rabbaniyyah ‘ yaitu zat maha halus yang dinisbatkan kepada Tuhan’ [Ihya Ulum al-Din].
Zat maha halus tersebut adalah fakultas yang asal penciptaannya berasal dari Tuhan sebagaimana tersirat dari firman Tuhan nafakhtu fihi min ruhi ‘setelah Kutiupkan kepadanya sebagian ruh-Ku’ [Al-Hijr, 15:29; Shad, 38:72]. Fakultas inilah yang mampu mencapai prestasi al-ma’rifah billah ‘mengenal Allah’ dan ia pulalah yang kelak kembali ke “asal”-nya, Allah ‘azza wa jalla.
Persoalan mengenal Allah dan jalan kembali kepada-Nya ini sudah harus diselesaikan di dunia ini. Jika di dunia seseorang tidak mengenal Allah dan jalan kembali kepada-Nya, maka ia tidak akan pernah, setidak-tidaknya sangat sulit untuk kembali kepada Tuhannya; artinya, ia tidak akan masuk ke dalam golongan yang dipanggil oleh Allah dengan firman-Nya:
“Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai, serta masuklah ke dalam golongan hamba-hamba-Ku, dan masuklah ke dalam sorga-Ku”. (Al-Fajr,89:27-30).
Dalam kaitan ini pulalah Allah menegaskan:
“Barangsiapa di dunia buta (mata batinnya), maka dia di akhirat akan lebih buta lagi dan tersesat jalannya.” (Al-Isra, 17:72)
Thariqah, Teknik Berdzikir Efektif
Di samping menunjuk kepada pengertian-pengertian yang telah disebutkan sebelumnya, thariqah juga dapat didefinisikan secara singkat sebagai “teknik berdzikir efektif”.
Sebelumnya telah disebutkan bahwa istilah thariqah dalam al-Quran dan al-Hadis digunakan dalam konteks dzikrullah dalam kerangka tauhid. Dalam hadis al-Bukhari berikut kata thuruq (bentuk jamak dari thariq dan thariqah) juga digunakan dalam konteks ini:
“Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat-malaikat yang bertugas berkeliling di tarekat-tarekat mencari ahli dzikir. Jika mereka menemukan suatu kaum yang sedang berdzikir kepada Allah, mereka berseru, ‘Sebutkan kebutuhan kalian’.”
Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, “Malaikat-malaikat itu kemudian mengelilingi mereka dengan sayap-sayap mereka hingga ke langit dunia” [shahih al-Bukhari, V: 2353, Shahih Ibn Hibban, III: 139, Musnad Ahmad, II:251].
Kata thuruq ‘tarekat-tarekat atau jalan-jalan’ dalam hadis tersebut menunjukan kepada halaqah atau majelis dzikir. Halaqah artinya lingkaran, dan halaqah dzikir menunjukan kepada makna “sekumpulan orang yang duduk melingkar untuk bersama-sama berdzikir dan bermunajat kepada Allah ‘azza wa jalla”. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad halaqah dzikr ini disebut oleh Nabi SAW sebagai riyadh al-jannah ‘taman-taman sorga’:
“Jika kamu melewati taman-taman sorga, maka masuklah ke sana”. Para sahabat bertanya, “Apa taman sorga itu?” Nabi menjawab, “Halaqah-halaqah dzikir” [sunan al-Tirmidzi, V:532, Musnad Ahmad, III:150].
Hadis tersebut memerintahkan orang-orang mukmin agar bergabung dengan halaqah dzikir sebagai sebuah majelis yang sangat dicintai Allah. Imam al-Darami meriwayatkan bahwa Luqman al-Hakim pernah memberikan nasehat kepada putranya sebagai berikut:
“Jika kamu melihat suatu kaum yang sedang berdzikir kepada Allah, maka duduklah bersama mereka; sebab, jika kamu orang yang berilmu, maka ilmumu akan bermanfaat, dan jika kamu orang yang tidak berilmu, maka mereka akan mencurahkan rahmat itu kepadamu bersama dengan mereka. Dan jika kamu melihat suatu kaum yang tidak berdzikir kepada Allah, maka janganlah kamu duduk bersama mereka; sebab, jika kamu orang yang berilmu, maka ilmumu tidak akan bermanfaat bagimu, dan jika kamu orang yang tidak berilmu, maka mereka membuatmu semakin bodoh atau sesat; semoga Allah memandang mereka dengan kemurkaan-Nya, lalu menimpakan kemurkaan itu kepadamu bersama dengan mereka” [Sunan al-Darami, I:117-118].
Di dalam al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyinggung perintah berdzikir dan keutamaannya. Selama ini tidak sedikit ulama yang berpendapat bahwa berdzikir itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Pendapat semacam ini sebenarnya tidak dapat dibenarkan karena diantara dalil-dalil yang berkenaan dengan dzikir justru menunjukan kepada hukum wajib.
Dzikir merupakan aktivitas ibadah yang paling tinggi nilainya. Dalam sebuah firman Allah, di samping digunakan lafaz yang memang mengandung makna keagungan dzikir, Allah bahkan masih menggunakan lam al-tawkid (lam yang dibaca fathah dan menunjuk pada makna “sungguh atau sangat”) untuk menegaskan betapa besar keutamaan, nilai, pahala, atau manfaat dzikir, sebagaimana yang sering dibaca khatib Salat Jumat di akhir khutbahnya, “Wa ladzikrullahi akbar ‘sungguh dzikrullah itu akbar’.” (Q.S. 29:45).
Ke-akbar-an kedudukan dzikrullah sebagai amal terbaik juga dipertegas oleh hadis Nabi SAW dalam riwayat Ahmad dengan sanad hasan:
“Maukah kalian kuberitahu amal yang paling baik untuk kalian, amal yang paling suci di sisi Tuhan kalian, amal yang paling mengangkat derajat kalian, amal yang lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak, dan amal yang lebih baik bagi kalian daripada menghadapi musuh di medan jihad yang kemudian kalian dan musuh kalian saling menebas leher?”
Para sahabat menjawab, “Tentu, wahai Rasulullah.”
Nabi bersabda.” Dzikrullah”[Musnad Ahmad,V:239].
Selain sebagai amalan yang paling agung, dzikrullah bahkan merupakan inti/ruh semua aktivitas. Setiap aktivitas yang di dalamnya tidak ada dzikrullah adalah sia-sia dan tidak mempunyai nilai apa-pun di mata Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Imam al-Nasai, Nabi SAW menyebut aktivitas semacam ini sebagai permainan belaka:
“Segala sesuatu yang tidak bertolak dari dzikrullah adalah permainan” [Al-Sunan al-Kubra, V: 302].
Satu faktor yang menyebabkan dzikrullah menduduki posisi tertinggi dalam keseluruhan aktivitas seorang mukmin terkait erat dengan keberadaanya sebagai pengusir Iblis/Setan dari dalam diri manusia. Tidak dipungkiri bahwa makhluk terkutuk ini selalu menempel di dalam diri manusia sejak manusia itu lahir ke dunia. Imam al-Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda:
“Tidaklah seorang anak-pun dilahirkan kecuali dia pasti disentuh oleh setan [Shahih al-Bukhari, IV:1655].
Dalam bahasa Ibn Abbas yang dikutip oleh Imam al-Hakim dalam al-Mustadrak dan Imam al-Baihaqi dalam Syu’ab al-Iman hadis tersebut diungkapkan dengan kata-kata:
“Tidaklah seorang manusia yang terlahir ke dunia kecuali al-waswas bertengger di hatinya; jika ia melakukan dzikrullah, setan itu menahan diri; tetapi jika ia lalai, setan itu bergerilya membisikan godaan-godaan” [Al-Mustadrak ‘ala al-Shahihayn, II: 590; Syu’ab al-Iman, I: 450].
Ibn Abbas menjelaskan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah dalam Mushannaf –nya dan dikutip juga oleh Imam Ibn Katsir dan Imam al-Thabari dalam kitab tafsir mereka, bahwa yang dimaksud al-waswas adalah Setan, kemudian ia berkata:
“Setan itu mendekam di kalbu anak Adam; jika ia lupa dan lalai, setan itu membisikkan godaan-godaan, dan jika ia berdzikir kepada Allah, setan itu menahan diri” [Mushannaf Ibn [Syaibah, VII: 135; Tafsir Ibn Katsir, IV:576; Tafsir al-Thabari, XXX:355].
Jadi, tidak diragukan lagi bahwa musuh bebuyutan manusia, sang Iblis, tidak pernah berhenti dari menggoda manusia bahkan sejak manusia pertama Adam diciptakan; dan makhluk-makhluk durhaka ini tidak mungkin dapat dihalau kecuali dengan senjata yang disebut dzikrullah. Hal ini ditegaskan langsung oleh Nabi SAW melalui sabda beliau dalam riwayat Imam Ibn Hibban, Tirmidzi, dan Abu Ya ‘la:
“Seseorang tidak akan bisa melindungi ‘diri’-nya dari setan kecuali hanya dengan dzikrullah” [Shahih Ibni Hibban, XIV:125; Sunan Al-Tirmidzi, V: 148; Musnad Abi Ya’la, III: 141].
Persoalannya, setiap orang sudah berdzikir, sudah biasa menyebut asma Allah dan mengingatNya, tetapi dalam kenyataan mereka tetap terperangkap dalam jebakan-jebakan sang Iblis baik yang tampak maupun yang tersembunyi, seperti dengkil, dendam, ‘ujub, marah, dan penyakit-penyakit hati lainnya yang secara simultan menimbulkan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar (al-fakhsya’ wa al-munkar) dalam berbagai bentuknya, dan yang paling layak dipertanyakan adalah bahwa semua itu tidak jarang justru dilakukan oleh orang-orang yang secara lahiriah sudah terbiasa berdzikir. Berbagai kasus yang terjadi di lembaga-lembaga Islam, mulai dari sekolah-sekolah yang berlabel Islam hingga instansi-instansi yang menangani urusan-urusan keagamaan merupakan bukti kegagalan dzikir mereka.
Rahasia kegagalan dzikir mereka sebenarnya hanya terletak dalam satu hal: mereka tidak melibatkan thariqah sebagai “teknik berdzikir efektif”. Logika awam membuktikan bahwa pekerjaan apa pun yang dilakukan dengan tidak melibatkan thariqah ‘teknik/metode/cara’ yang tepat maka sudah dapat dipastikan hasilnya tidak maksimal atau bahkan gagal sama sekali.
Air dan pengolahannya adalah contoh sederhana yang dapat dikemukan di sini.
Dalam kondisi biasa (tanpa teknologi) air hanya berfungsi sebagai pelapas dahaga, mencuci, dan/atau mandi. Dalam kasus ini manfaat air tidak maksimal. Sebaliknya tatkala terhadap air itu diterapkan teknologi tinggi (‘ilm al-thariqah) oleh seorang pakar teknologi yang berkompeten di bidangnya, maka dari pengolahan air itu dapat diciptakan energi raksasa yang sanggup membangkitkan tenaga listrik, menjalankan kereta api, dan bahkan juga dapat berfungsi sebagai peledak yang berkekuatan tinggi.
Kalau air saja dapat diolah menjadi sumber energi raksasa dengan melibatkan teknologi, lalu bagaimana dengan kalimah Allah yang oleh al-Quran disebut sebagai ‘ulya ‘tertinggi’ ( kalimatullahi hiyal ‘ulya)? Bagaimana dengan dzikrullah yang oleh al-Quran digambar kata dengan kata akbar ‘maha hebat’ (wa ladzikrullahi akbar)?!
Disinilah letak urgensi thariqah sebagai “teknik berdzikir efektif”, yaitu agar dzikir yang dilakukan oleh seorang hamba dapat berfungsi maksimal dan mencapai efektivitasnya untuk menghalau sang iblis, terutama, yang tanpa disadarinya telah lama berada di dalam dirinya/hatinya, menjadi biang kerok setiap keangkaramurkaan.
Sebagai “teknik berdzikir efektif” thariqah melibatkan beberapa unsur yang harus difungsikan secara simultan, karena yang satu dengan yang lain memiliki keterkaitan yang sangat erat. Salah satu unsur dari unsur-unsur tersebut adalah dzikir itu sendiri. Yang menjadi fondasi dan ruh semua aktivitas ibadah. Terkait dengan masalah ini, thariqah bahkan dapat dipahami juga sebagai istilah untuk paket-paket dzikir dan tugas-tugas spiritual berdasarkan model kurikulum pembelajaran yang dijadikan sebagai media untuk mencapai kesucian jiwa dan kedamaian hati.
Lafal Dzikir Yang Paling Utama
Di dalam al-Quran perintah berdzikir diungkapkan berkali-kali dan pada umumnya muncul dalam tiga redaksi, yaitu: wadzkur isma rabbika ‘dan sebutlah nama Tuhanmu’ [Al-Insan, 76:25], atau wadzkur rabbaka ‘dan sebutlah Tuhanmu’ [Ali Imran, 3:41], atau wadzkurullaha ‘dan sebutlah Allah’ [Al-Anfal,8:45; al-Jumu’ah 62:10].
Berdzikir dapat dilakukan dengan berbagai lafal yang ma’tsur dari hadis-hadis Nabi saw seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, istighfar, salawat, al-asma al-husna, membaca ayat-ayat suci al-Quran, dan lain sebagainya. Hanya saja, lafal dzikir yang paling utama dan paling agung adalah al-nafy wa al-itsbat (di-Indonesia-kan menjadi “nafi-isbat”), yaitu ungkapan la ilaha illallah ‘tidak ada Tuhan selain Allah’.
Yang didasarkan pada hadis Nabi yang menyatakan bahwa Dzikir yang paling utama adalah la ilaha illallah” [Shahih Ibni Hibban, III:126; Sunan al-Tirmidzi, V: 426 dan Sunan Ibn Majah, II: 1249].
Selanjutnya Nabi SAW mengatakan: “Allah benar-benar mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah semata-mata mengharap ridha-Nya” [Shahih al-Bukhari, I: 164, V: 2063].
Di samping itu, keutamaan dzikir ini dapat dipahami dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam-imam hadis lainnya:
“Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku di Hari Kiamat kelak adalah orang yang berdzikir dengan la ilaha illallah secara murni dari kalbu atau jiwanya” [Musnad Ahmad, II:373; Shahih al-Bukhari, I: 49, V: 2402; al-Sunan al-Kubra, III: 42].
Lafal dzikir nafi isbat (la ilaha illallah), dipilih dan dilazimkan oleh ahli Thariqah Naqsyabandiyah sebagai lafal dzikir yang paling dominan.
Dalam Khulashah al-Tashanif fi al-Tashawwuf yang terhimpun dalam Majmu’ Rasail al-Imam al-Ghazali, Imam al-Ghazali menegaskan, “Penyucian jiwa yang paling efektif adalah dengan mengintensifkan dzikir Tarekat al-Naqsyabandiyah, yaitu dzikir dengan ismu dzat dan nafi isbat” [Majmu’ Rasail al-Imam Ghazali , hal 179].
Unsur-unsur pokok lainnya yang menjadi syarat dan rukun dalam thariqah baik sebagai “teknik berdzikir efektif” maupun sebagai “cara pengamalan syariah” dan “jalan menuju ma’rifah” adalah: mursyid (guru), wasilah (alat), rabithah (proses), dan mujahadah (suluk/iktikaf) semuanya disajikan dalam makalah ini.
Dzikir itu Wajib Bukan Sunnah
Pandangan umum yang dikenal orang selama ini mengenai hukum berdzikir adalah bahwa berdzikir itu sunnah. Pandangan ini tampaknya perlu digarisbawahi dan dikaji ulang. Dimaklumi bahwa sunnah berimplikasi “jika dikerjakan memperoleh pahala dan kalau ditinggalkan tidak apa-apa”, sedangkan wajib memiliki implikasi “apabila dikerjakan memproleh pahala dan kalau ditinggalkan ada sanksi, dosa atau siksa.”
Kalau berdzikir itu sunnah, maka konsekuensinya adalah bahwa orang yang tidak melakukan dzikir tidak dikenai sanksi apa pun, padahal Allah berfirman:
“Barangsiapa tidak mau berdzikir kepada-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunya pada hari kiamat dalam keadaan buta”. (Thaha, 20: 124)
“Barangsiapa berpaling (tidak mau) berdzikir kepada Tuhannya, niscaya Dia memasukkannya kedalam siksa yang pedih.” (Al-Jinn, 72:17)
Dengan menyimak ketiga firman tersebut tidak diragukan lagi bahwa hukum berdzikir itu wajib, bukan sunnah.
Oleh karena itu pula, setelah turun firman Allah, “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat ayat-ayat Tuhan bagi ulil albab, yaitu orang-orang yang berdzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring…(Ali Imran, 3:190-191).” Nabi saw melakukan salat sambil terus menerus menangis, dan ketika ditanya mengapa, beliau bersabda, “Telah turun kepada ayat inna fi khalqis samawati..(sesungguhnya dalam penciptaan langit …dst.); maka celakalah orang yang membacanya tetapi tidak merenungkan isinya.” [Shahih Ibn Hibban, II: 386; Tafsir al-Qurthubi, IV: 310; Tafsir Ibn Katsir, I: 441].
Unsur-unsur Thariqah
Mursyid
Kata mursyid berasal dari bahasa Arab dan merupakan ism fa’il (Ingg. Present participle) kata kerja arsyada – yursyidu yang berarti “membimbing, menunjuki (jalan yang lurus)”, terambil dari kata rasyad ‘hal memperoleh petunjuk/kebenaran’ atau rusyd dan rasyada ‘hal mengikuti jalan yang benar/lurus’ [Lisan al-Arab, III: 175-176].
Dengan demikian, makna mursyid adalah “(orang) yang membimbing atau menunjuki jalan yang lurus” Dalam wacana tasawuf/tarekat mursyid sering digunakan dengan kata Arab Syaikh; kedua-duanya dapat diterjemahkan dengan “guru”.
Dalam al-Quran kata mursyid muncul dalam konteks hidayah (petunjuk) yang dioposisikan dengan dhalalah (kesesatan), dan ditampilkan untuk menyipati seorang wali yang oleh Tuhan dijadikan sebagai khalifah-Nya untuk memberikan petunjuk kepada manusia:
‘Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka ia benar-benar mendapatkan petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan, maka orang itu tidak akan pernah engkau dapati memiliki wali mursyid (pemimpin yang mampu memberi petunjuk).” (Al-Kahfi, 18:17)
Kata wali (pl. awliya) sendiri menunjukan kepada beberapa makna, antara lain al-nashir ‘penolong’ [Lisan al-Arab, XV: 406], al-mawla fi al-din ‘pemimpin spiritual’[Lisan al-Arab XV: 408], al-shadiq ‘teman karib’ dan al-tabi al-muhibb ‘pengikut yang mencintai’ [Lisan al-Arab, XV:411] Semua makna ini berserikat dan secara simultan menjelaskan makna wali dalam ayat diatas, yaitu “orang yang mencintai dan dicintai Allah sehingga layak menjadi pemimipin spritual yang harus diikuti”.
Pengertian wali semacam ini digambarkan dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan beberapa imam hadis lainnya dengan redaksi:
“Barangsiapa memusuhi seorang wali-Ku, maka Aku umumkan perang kepadanya. Tidaklah seorang hamba-Ku mendekat kepada-Ku dengan sesuatu yang paling Aku cintai berupa ibadah-ibadah yang Aku wajibkan kepadanya, dan hamba-Ku itu terus menerus mendekat kepada-Ku dengan ibadah-ibadah sunnah, kecuali Aku pasti dengannya ia mendengar, (Akulah) matanya yang dengannya ia melihat, (Akulah) tangannya yang dengannya ia melakukan sesuatu, dan (Akulah) kakinya yang dengannya ia berjalan. Jika ia meminta kepada-Ku niscaya Aku mengabulkannya; dan jika ia memohon perlindungan kepada-Ku niscaya Aku melindunginya [Shahih al-Bukhari, V: 2384; Shahih Ibn Hibban, II: 58; Sunan al-Baihaqi al-Kubra, III: 346].
Menurut berbagai riwayat yang sahih, wali-wali Allah adalah hamba-hamba Allah yang memiliki karakteristik utama “tidak pernah lepas dari berdzikir kepada Allah” sebagaimana halnya Nabi saw yang oleh ‘Aisyah dengan “selalu berdzikir kepada Allah dalam setiap detik yang beliau milik” (kana yadzkurullaha fi kulli ahyanihi) [Musnad Abi Ya’la, VIII: 355]. Imam al-Thabrani dalam al-Mu’jam al-Kabir-nya meriwayatkan dari Abdullah Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah saw bersabda:
“Sesungguhnya di antara manusia ada kunci-kunci dzikrullah; apabila mereka dilihat orang maka (yang melihat) itu langsung berdzikir kepada Allah” [Al-Mu’jam al-Kabir, X:205].
Maksud “kunci-kunci dzikrullah” dalam riwayat tersebut adalah wali-wali Allah sesuai dengan hadis dalam riwayat Ibn Abbas yang menceritakan bahwa Rasulullah saw ditanya, “Wahai Rasulullah, siapakah wali-wali Allah itu? Beliau menjawab:
“Orang-orang yang apabila mereka dilihat orang maka orang (yang melihat) itu berdzikir kepada Allah karena melihat mereka” [ Mushaannaf Ibn Abi Syaibah, VII: 79; Musnad al-Bazza,VII: 158].
Imam al-Tirmidzi juga meriwayatkan:
"Nabi Musa as pernah bertanya kepada Tuhannya, “Tuhan, siapakah wali-wali-Mu?” Tuhan menjawab:“Orang-orang yang apabila mereka berdzikir engkau pun berdzikir dan apabila engkau berdzikir mereka pun berdzikir” Nawadir al-Ushul fi Ahadits al-Rasul, IV: 86].
Imam al-Suyuthi mengutip sebuah riwayat yang menceritakan bahwa kaum Hawariyyun bertanya kepada Nabi Isa as, “Siapa wali-wali Allah yang tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak pula bersedih?” Nabi Isa menjawab:“Orang-orang yang memandang hakikat dunia sementara manusia memandang permukaannya, dan orang-orang yang memandang dunia yang abadi (akhirat) sementara manusia memandang dunia yang fana” [Tafsir al-Durr al-Mantsur, IV: 370].
Dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda:
“Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah terdapat orang-orang yang bukan nabi dan bukan pula syuhada’ tetapi pada hari kiamat para Nabi dan syuhada’ menginginkan seperti mereka karena kedudukan mereka disisi Allah ‘azza wa jalla.”
Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, siapa mereka dan apa amal-amal mereka? Boleh jadi kami akan mencintai mereka.” Rasulullah bersabda , “Mereka adalah kaum yang saling mencintai dengan ruh Allah tidak atas dasar hubungan darah antara mereka dan tidak pula atas dasar harta yang saling mereka berikan. Demi Allah, wajah mereka adalah nur (Allah) dan mereka berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari nur; mereka tidak takut ketika orang lain takut”. Kemudian Rasulullah membacakan ayat “Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak pula bersedih (Q.S. Yunus, 10:62).” Hadis tersebut dikutip oleh Imam al-Jauzi dari jalur ‘Umar Ibn al-Khaththab r.a. dalam Zad al-Masir-nya, [Zad al-Masir, IV: 43-44], dan dikutip juga oleh Imam Ibn Hibban dalam Shahih-nya [Shahih Ibn Hibbam II: 332], dan oleh Imam al-Bayhaqi dalam al-Firdaus bi Ma’tsur al-Khithab [al-Firdaus bi Ma’tsur al-Khithab, I:134], dari jalur Abu Hurairah.
Mursyid sebagai Pemandu Jalan
Mursyid dalam thariqah adalah seorang wali yang layak diikuti sebagai imam dalam perjalanan menuju Tuhan. Ia adalah wali Allah yang ciri khasnya sebagaimana disebutkan di atas. Jalan menuju Tuhan bukan jalan yang mulus melainkan jalan yang berliku-liku dan penuh dengan rintangan-rintangan berupa ranjau-ranjau Iblis sehingga diperlukan pemandu yang arif untuk bisa selamat dari semua rintangan itu. Seorang salik, orang yang menempuh perjalanan (menuju Tuhan) atau yang biasa disebut dengan murid, yang telah membulatkan kehendaknya untuk menempuh perjalanan (menuju Tuhan) tidak boleh tidak harus didampingi mursyid sebagai pemandu jalan yang menuntun dan sekaligus memperingatkannya apabila ada bahaya yang mengancam. Keberadaan seorang mursyid dengan fungsi ini sangat mutlak.
Barang siapa berjalan tanpa pemandu, ia memerlukan dua ratus tahun untuk perjalanan dua hari, kata Jalaluddin Rumi dalam Matsnawi yang dikutip oleh Annemarie Schimmel [Dimensi Mistik dalam Islam, hlm. 106], untuk menggambarkan betapa sulitnya perjalanan itu dan betapa pentingnya keberadaan seorang pemandu (mursyid).
Posisi mursyid atau syaikh sufi menurut Ibn Taimiyah tidak ubahnya seperti imam dalam shalat dan pemandu haji (dalil-al-hajj); imam shalat diikuti oleh makmum, mereka shalat sesuai dengan shalatnya imam (yushalluna bi shalatihi), sedangkan pemandu haji menunjukan kepada jamaah jalan menuju baitullah (yadullu al-wafd ala thariq al-bait)[ Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah, VIII: 49].
Dalam peristiwa Isra dan Miraj (perjalanan Nabi menuju Tuhan), Nabi saw dipandu oleh Jibril as yang berfungsi sebagai mursyid, imam atau guide, yaitu pemandu jalan yang menuntun dan membimbing beliau hingga sampai di hadirat Allah ‘azza wa jalla.
Dalam Tafsir al-Thabari disebutkan bahwa dalam Miraj itu, Nabi saw bertemu dengan seorang tua renta di sisi jalan, dan ketika beliau bertanya siapa orang itu, Jibril as. berkata, Teruslah berjalan, wahai Muhammad (sir ya muhammad)!
Beliau juga mendengar sebuah suara yang menyeru beliau agar menyingkir dari jalan, “Halumma ya muhammad, ke sinilah Muhammad!, sebelum Nabi saw sempat menoleh Jibril sudah langsung memperingatkan, Teruslah berjalan, wahai muhammad (sir ya muhammad)!
Beberapa saat kemudian Jibril memberikan penjelasan. Orang tua yang engkau lihat di sisi jalan tadi menunjukan bahwa tidak tersisa dari dunia ini kecuali sekadar sisi umur orang tua itu, sedangkan suara yang hendak memalingkanmu adalah Iblis [Tafsir al-Thabari, XV: 6; Tafsir Ibn Katsir, III: 6 Al-Ahadits al-Mukhtarah, VI: 258].
Peristiwa Isra dan Miraj Nabi saw memang menjadi rujukan utama para sufi, terutama yang berkenaan dengan unsur Jibril as. yang berfungsi sebagai mursyid, sang pemandu.
Keberadaan unsur Jibril as sangat mutlak sedemikian rupa sehingga andaikata unsur ini tidak ada, maka Nabi saw akan terperangkap oleh jebakan Iblis. Lalu bagaimana dengan umat beliau? Apakah mereka juga memerlukan unsur Jibril ini? Jawabannya pasti: ya, tidak boleh tidak. Posisi dan fungsi unsur Jibril ini justru diduduki dan dilaksanakan oleh Nabi sendiri.
Urgensi unsur Jibril sangat jelas terutama mengingat pernyataan Nabi saw bahwa shalat adalah miraj-nya orang mukmin [Syarh Sunan Ibn Majah, hlm. 313]. Artinya, orang-orang mukmin juga dimungkinkan mengalami miraj dengan izin dan kehendak Tuhan. Sebagai sarana miraj, dalam shalat seorang mukmin harus melibatkan unsur Jibril; kalau tidak, maka shalatnya akan didominasi oleh unsur setan, sehingga shalat itu menjadi shalat yang tanpa makna, gersang, dan jauh dari nilai-nilai khusyuk, yang pada gilirannya tidak dapat berfungsi sebagai tanha an al-fahsya wa al-munkar mencegah dari perbuatan keji dan mungkar [al-Ankabut, 29:45].
Shalat semacam ini kata Nabi saw dalam riwayat al-Thabrani dengan perawi-perawi sahih [Majma al-Zawaid, II: 258], adalah shalat yang hanya akan menjauhkan pelakunya dari Allah SWT (man lam tanhahu shalatuhu an al-fahsya wa al-munkar lam yazdad minallahi illa budan), [Al-Mu’jam al-Kabir, XI: 54]. Berbagai kasus dalam kehidupan orang-orang mukmin menjadi bukti tak terbantah atas pernyataan ini.
Miraj adalah karunia Tuhan yang berupa perjalanan menuju Dia SWT dengan perbentangan berbagai fenomena ghaib (metafisik) sesuai dengan yang dikehendaki-Nya.
Dalam sejarah Nabi saw dikenal dua jenis miraj: Khusus dan umum.
Miraj khusus dialami Nabi saw pada saat beliau menerima perintah shalat wajib lima waktu, sedangkan miraj umum dialami Nabi saw pada saat-saat yang lain termasuk ketika beliau dimuliakan Allah dengan diangkat sebagai rasul.
Dalam wacana sufi miraj umum lebih sering disebut dengan istilah muraqabah, dan sangat dimungkinkan dialami oleh siapa pun dari kalangan orang-orang beriman. Pengalaman melihat sorga dan neraka dengan mata kepala (muraqabah) yang dialami para sahabat merupakan indikasi nyata atas kemungkinan ini.
Dalam kitab Shahih-nya Imam Muslim memuat bab yang menyinggung soal muraqabah; di dalamnya diriwayatkan sebuah hadis yang berasal dari Hanzhalah al-Usayyidi, salah seorang sekretaris Rasulullah saw; ia berkata bahwa ketika Nabi bercerita tentang sorga dan neraka, ia dan Abu Bakar ra. merasa melihat sorga dan neraka itu dengan mata kepala mereka, tetapi masing-masing dari mereka banyak yang lupa apa yang mereka lihat, lalu mereka memutuskan untuk menghadap Nabi saw dan menanyakan hal itu. Dialog antara Hanzhalah dan Nabi dapat disimak dari kutipan berikut:
Aku (Hanzhalah) berkata, Hanzhalah telah munafik, wahai Rasulullah. Rasulullah saw bertanya, Ada apa?. Aku (Hanzhalah) berkata, Wahai Rasulullah, kami pernah berada di hadapanmu mendengarkan engkau bercerita kepada kami tentang sorga dan neraka sehingga kami seolah-olah melihat sorga dan neraka itu dengan mata kepala. Setelah kami pulang dari hadapanmu, serta bertemu dan bermain-main dengan anak-istri kami dan pergi keperkarangan kami, kami banyak lupa tentang hal itu. Rasulullah saw bersabda, Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, jika kalian berkekalan dengan apa yang kalian lihat dihadapanku dan berkekalan dalam dzikir, niscaya para malaikat menjabat tangan kalian diatas tempat tidur kalian dan dijalan-jalan (tarekat-tarekat) kalian. Sayangnya, wahai Hanzhalah, (muraqabah itu) hanya sesaat dan sesaat (ini diucapkan tiga kali oleh beliau)” [Shahih Muslim, IV: 2106; Musnad Ahmad, IV: 346; Sunan al-Tirmidzi, IV: 666].
Dalam kasus tersebut para sahabat telah mengalami muraqabah dan sekaligus miraj, karena miraj pada dasarnya dapat dipahami sebagai naik dan melintasi alam fisik, keluar dari dimensi ruang dan waktu, serta memasuki dan menyaksikan alam metafisik ketuhanan. Pengalaman miraj para sahabat tersebut terjadi berkat bimbingan Rasul saw sebagai pemandu, sebagaimana Rasul sendiri mengalami miraj berkat bimbingan Jibril as. dengan izin Allah SWT. Dengan kata lain, mereka dibawa miraj oleh Nabi saw sebagaimana Nabi dibawa miraj oleh Jibril as. dengan izin Allah. (Lalu, bagaimana dengan orang-orang mukmin lain yang tidak bertemu dengan Nabi? Siapa yang akan membawa mereka miraj?!).
Hikmah yang dapat diambil dari pengalaman itu adalah bahwa yang bersangkutan pasti menyadari secara haqqul yaqin bahwa ungkapan al-Quran inna lillahi wa inna ilaihi rajiun (kami milik Allah dan kepada-Nya kami pulang) [Al-Baqarah, 2:156] adalah benar (haqq), dan bahwa mereka ketika hidup di dunia pada hakikatnya sedang berada dalam perjalanan pulang menuju Tuhan, sebuah perjalanan yang sangat sulit dan berliku-liku.
Dengan adanya seorang pemandu, perjalanan itu akan terasa lebih ringan, mudah, dan lancar sehingga tepat sekali ungkapan Rumi yang dikutip sebelumnya, Barangsiapa berjalan tanpa pemandu, ia memerlukan dua ratus tahun untuk perjalanan dua hari.
Mursyid sebagai Khalifah Rasul
Imam-imam hadis, selain al-Bukhari dan Muslim, meriwayatkan sebuah hadis perpisahan yang didalamnya antara lain Nabi saw bersabda:
Kalian harus mengikuti sunnahku dan sunnah al-khulafa al-rasyidun yang memperoleh petunjuk; berpeganglah kepada sunnah-sunnah itu dan ‘gigitlah’ sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham kalian [Shahih Ibn Hibba,I: 179; sunan al-Tirmidzi, V: 44; Sunan Abi Dawu, IV: 200; Sunan Ibn Majah, I: 16; Sunan al-Baihaqi al-Kubra, X:114].
Dalam hadis itu tampak bahwa sunnah Nabi saw disandingkan dengan sunnah para khalifah (pengganti) beliau; kedua jenis sunnah ini sama-sama wajib diikuti dan dipegangi secara teguh oleh setiap mukmin. Ini menunjukan bahwa sunnah al-khulafa al-rasyidun adalah sunnah yang suci sebagaimana Sunnah Nabi saw sendiri. Tidak mungkin Nabi saw memerintahkan mengikuti sunnah mereka apabila sunnah itu mengandung cacat atau hal-hal yang bertentangan dengan syara.
Siapakah sesungguhnya yang dimaksud dengan al-khulaf al-rasyidun itu? Selama ini ungkapan al-khulafa al-rasyidun dipahami sebagai pengganti Nabi saw di bidang politik, yaitu sebagai kepala negara/pemerintahan Islam yang bertanggung jawab atas semua urusan politik umat. Mereka adalah Abu Bakar al-Shiddiq ra., Umar Ibn al-Khaththab ra., Utsman Ibn Affan ra., dan Ali Ibn Abi Thalib ra.
Belakangan nama Amirul Mukminin Umar Ibn Abd al-Aziz ra diposisikan sebagai khalifah kelima dan sekaligus terakhir dari al-khulafa al-rasyidun, sehingga secara keseluruhannya al-khulafa al-rasyidun dalam pengertian ini hanya berjumlah lima orang. Tetapi di samping pengertian sebagai pengganti Nabi saw di bidang politik, pengertian al-khulafa al-rasyidun juga dapat ditinjau dari segi spiritual, sebab Nabi saw tidak sekedar sebagai kepala negara/pemerintahan melainkan juga sebagai Nabi dan Rasul yang membawa misi tauhid dan ubudiah serta penyempurnaan akhlak yang mulia.
Beliau adalah pemimpin spiritual yang oleh al-Quran digambarkan memiliki tugas-tugas:
(1) membacakan kepada umat ayat-ayat Tuhan, (2) menyucikan kalbu mereka, serta (3) mengajarkan kepada mereka al-Kitab dan al-Hikmah [Ali Imran, 3: 164].
Tugas-tugas seorang khalifah sudah sepatutnya sesuai dengan tugas-tugas Nabi saw sebagai seorang Rasul, yaitu ta’lim (mengerjakan al-Kitab dan al-Hikmah) dalam kerangka tauhid, ubudiah, dan penyempurnaan akhlak yang mulia. Dengan pengertian kedua ini, al-khulafa al-rasyidun pada dasarnya menunjuk kepada ulama yang oleh Nabi SAW. diposisikan sebagai waratsah al-anbiya (ahli waris para Nabi), dan satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa Nabi saw atau Nabi-Nabi lainnya tidak mewariskan dinar atau dirham; mereka hanya mewariskan al-ilm (ilmu) [Musnad Ahmad, V: 196; Shahih al-Bukhari, I: 46]. Mereka itulah hamba-hamba pilihan yang kepada mereka Allah mewariskan al-Quran [Fathir, 35:32], sehingga mereka disebut dengan ahl al-dzikr yang kepada mereka setiap orang harus bertanya [Al-Nahl, 16:43; al-Anbiya, 21:7].
Ciri khas mereka adalah bahwa mereka tidak pernah meminta upah atas upaya dakwah mereka karena Nabi saw juga tidak meminta upah atas dakwah beliau [Yusuf, 12: 104]; dan Allah memerintahkan agar mengikuti orang-orang yang tidak pernah meminta upah seperti mereka [Yasin, 36:21, Al Furqan 27:57].
Dengan warisan ciri khas semacam ini mereka layak menyandang gelar khalifah (pengganti) Rasul yang sekaligus sebagai penegak hujjah Allah, dan jumlah mereka tentu tidak hanya lima orang meskipun juga tidak banyak.
Sebagai hamba-hamba pilihan Tuhan, jumlah mereka memang sedikit sebagaimana ditegaskan oleh sayyidina Ali Ibn Thalib r.a. ketika berkata kepada Kuhail ibn-Ziyad, Demi Allah, sungguh bumi ini tidak akan pernah kosong dari orang-orang yang menegakkan hujjah-hujjah Allah agar tanda-tanda kebesaran-Nya tidak hilang dan hujjah-Nya tidak terbantahkan. Mereka adalah orang-orang yang jumlahnya sangat sedikit, namun sangat agung dan terhormat di sisi Allah.
Bahwa al-khulafa al-rasyidun yang dimaksud oleh Nabi saw lebih terkait dengan khalifah-khalifah spiritual daripada khalifah-khalifah di bidang politik dapat disimak pula dari kenyataan bahwa Umar Ibn al-Khaththab ra dan beberapa sahabat lainnya ternyata masih diperintahkan oleh Nabi saw agar menemui dan meminta syafaat kepada Uwais al-Qarni ra, seorang laki-laki dalam hadis riwayat Imam Muslim disebut sebagai khayr al-tabiin, orang terbaik di antara orang-orang yang hidup pada masa sahabat;
Sesungguhnya tabiin terbaik adalah seseorang yang bernama Uwais; dia hanya punya seorang ibu dan juga punya penyakit kusta; maka mintalah kepadanya agar ia memohonkan ampunan kepada Allah untuk kalian [Shahih Muslim, IV: 1968; Musnad Ahmad, I: 38].
Berkaitan dengan diri Uwais al-Qarni ra inilah, dalam sebuah riwayat yang berasal dari Abu Hurairah r.a., disebutkan bahwa Nabi saw bersabda:
Iman ada di Yaman dan hikmah pun ada di Yaman (dalam riwayat lain ada tambahan: dan aku cium nafas al-rahman dari arah Yaman, atau, dan aku cium nafas Tuhanmu dari arah Yaman) [ Shahih al-Bukhari, III: 1289; Shahih Muslim, I: 72 dan Shahih Ibn Hibban, XVI: 288].
Nafas al-rahman yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah Uwais al-Qarni. Dia adalah wali Allah yang paling besar pada masanya; disembunyikan oleh Allah di tengah-tengah rakyat jelata sehingga orang-orang tidak mengetahuinya dan bahkan sering mengejeknya. Dia berasal dariku dan aku berasal darinya, kata Rasulullah saw [Al-Firdaus bi Ma’tsur al-Khithab, I:113].
Ungkapan Rasul ini menunjukan kepada hubungan spiritual antara Uwais al-Qarni ra dan Nabi saw meskipun ia belum pernah bertemu dengan beliau.
Kualifikasi Mursyid
Dengan menyimak misi, tugas-tugas, dan ciri khas dakwah Rasulullah saw dan para khalifah (pengganti) beliau dapat dipahami bahwa tidak setiap ulama dapat serta-merta menjadi Mursyid terutama dalam kapasitasnya sebagai pemimpin dan guru spiritual, karena diantara ulama ada pula bahkan banyak sekali yang sekedar berbaju ulama tetapi prilakunya justru bertentangan dengan esensi ulama itu sendiri, yaitu takut kepada Allah sebagaimana diisyaratkan al-Quran:
Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah ulama (Fathir, 35:28).
Di antara mereka banyak pula yang terbuai oleh harta dan kenikmatan duniawi; mereka tidak berdakwa kecuali upah yang akan diperolehnya sudah jelas. Ulama semacam ini oleh Imam al-Ghazali disebut dengan ulama dunia atau ulama su’ (jahat) :
Diantara perkara-perkara yang paling penting adalah mengetahui tanda-tanda yang membedakan antara ulama dunia dan ulama akhirat. Yang dimaksud dengan ulama dunia disini adalah ulama su’ yang bertujuan mengejar kenikmatan dunia serta memburu kehormatan dan kedudukan di antara ahli ilmu [Ihya Ulum al-Din, I: 58].
Oleh karena itu ketika berbicara tentang kualifikasi seorang Mursyid, Imam al-Ghazali menjadikan kebebasan dari kecintaan terhadap harta dan kedudukan sebagai kriteria awal:
Mursyid adalah orang yang: (1) dari batinnya sudah keluar kecintaan terhadap harta dan kedudukan; (2) format pendidikannya berlangsung di tangan seorang Mursyid juga, dan begitulah seterusnya hingga silsilah itu berakhir pada Nabi saw; (3) mengalami riyadhah (latihan jiwa) seperti sedikit makan, bicara, dan tidur, serta banyak melakukan salat, sedekah dan puasa; (4) memperoleh cahaya dari cahaya-cahaya Nabi saw; (5) terkenal kebaikan biografinya dan kemulian akhlaknya seperti sabar, syukur, tawakal, yakin, damai, dermawan, qanaah, amanah, lemah lembut, rendah hati, berilmu, jujur, berwibawa, malu, tenang, tidak tergesa-gesa, dan lain sebagainya; (6) suci dari akhlaq yang tercela seperti sombong, kikir, dengki, tamak, berangan-angan panjang, gegabah dan lain sebagainya; (7) bebas dari ekstremitas orang-orang yang ekstrem; dan (8) kaya dengan ilmu yang diperoleh langsung dari Rasulullah saw sehingga tidak membutuhkan ilmu orang-orang yang mengada-ada (ilm al-mukallafin) [Khulashah al-Tashanif al-Tashawwuf dalam Majmu Rasail al-Imam al-Ghazali, hlm. 173].
Sedikit berbeda dari Imam al-Ghazali, al-Mukarram Saidi Syekh Prof. Dr. H. Kadirun Yahya mengumumkan kualifikasi sebagai berikut:
1. Pilih Guru yang Mursyid, dicerdikan oleh Allah SWT, bukan dicerdikan oleh yang lain-lain, dengan izin dan ridha Allah, karena Allah.
2. Yang kamil mukamil (sempurna dan menyempurna), diberi karunia oleh Allah, karena Allah.
3. Yang memberi bekas pengajarannya, (kalau ia mengajar atau mendoa berbekas pada si murid, si murid berobah kearah kebaikan), berbekas pengajarannya itu, dengan izin dan ridha Allah, biidznillah.
4. Yang masyhur kesana kemari, kawan dan lawan mengatakan, ia seorang Guru Besar.
5. Yang tidak dapat dicela oleh orang yang berakal akan pengajarannya, yaitu tidak dapat dicela oleh hadits dan Qur’an dan oleh ilmu pengetahuan (tidak bersalah-salahan dengan hadits, Qur’an dan akal).
6. Tidak setengah kasih kepada dunia, karena bulatnya hatinya, kasih kepada Allah. Ia ada giat bergelora dalam dunia, bekerja hebat dalam dunia, tetapi bukan karena kasih kepada dunia itu, tetapi karena prestasinya itu adalah sebagai abdinya kepada Allah SWT dalam hidupnya.
7. Mengambil ilmu dari Polan yang tertentu; Gurunya harus mempunyai tali yang nyata kepada Allah dan Rasul dengan silsilah yang nyata [Ibarat Sekuntum Bunga dari Taman Firdaus, hlm. 173].
Wasilah (Nurun ‘ala Nurin)
Ungensi posisi Mursyid yang sangat penting dalam thariqah sebagai jalan menuju Tuhan sebenarnya erat kaitannya dengan masalah wasilah yang oleh Allah diperintahkan agar orang-orang mukmin mencarinya:
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah (yang menyampaikanmu) kepada Allah, serta berjuanglah di jalan-Nya, agar kamu menang. (al-Maidah, 5:35)
Dari uraian-uraian berikut akan dipahami bahwa Mursyid adalah pembawa wasilah sebagaimana Jibril adalah pembawa Buraq yang oleh Imam Zubaidi disebut sebagai kendaraan para nabi [Syarh al-Nawawi Shahih Muslim, II: 210].
Pengertian Wasilah
Wasilah artinya alat atau menurut definisi al-Razi dan Louis Ma-luf yaitu alat yang dipergunakan untuk mendekatkan sesuatu kepada sesuatu yang lain [Mukhtar al-Shihah, I: 300; al-Munjid fial-Lughah: 900]. Menurut Abd al-Rauf, wasilah adalah alat yang memudahkan sampainya sesuatu kepada sesuatu yang lain, atau dengan kata lain yang memungkinkan tercapainya suatu tujuan [al-Ta’arif:726]. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia hampir tidak pernah lepas dari yang dimanakan wasilah dengan berbagai bentuknya.
Seseorang tidak mungkin bisa berkomunikasi dengan keluarganya yang tinggal di luar negri, misalnya, tanpa menggunakan wasilah yang disebut telepon. Hubungan melalui telepon semacam ini adalah hubungan langsung, bukan hubungan melalui perantara. Telepon bukan perantara, melainkan alat yang memungkinkan terjadinya hubungan langsung antara dua orang yang saling berjauhan. Perantara sangat berbeda dengan alat (wasilah). Dalam bahasa Arab, perantara biasa disebut dengan wasithah; bukan wasilah. Uang dan kendaraan adalah contoh lain dari wasilah yang sangat dibutuhkan untuk mempermudah tercapainya tujuan.
Dalam kaitannya dengan kehidupan beragama, yang dimaksud wasilah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan diri kita. Dengan pengertian semacam ini, maka sudah barang tentu alat tersebut sudah harus bisa sampai terlebih dahulu kepada Allah, padahal tidak ada sesuatu yang dapat sampai kepada Allah kecuali yang berasal dari Allah itu sendiri. Satu-satunya yang dapat sampai kepada Allah hanyalah cahaya (Nur) Allah sendiri, sebagaimana tidak ada yang dapat sampai kepada matahari kecuali cahaya matahari itu sendiri. Dengan demikian, wasilah yang dimaksud dalam ayat 35 Surah al-Maidah pasti bukan amal saleh, bukan pula keimanan dan ketaatan sebagaimana yang dipahami orang selama ini, melainkan Cahaya (Nur) Allah.
Perintah Tuhan dalam ayat 35 Surat al-Maidah tersebut adalah perintah mencari wasilah, bukan perintah mencari amal saleh, keimanan, dan ketaatan. Mengenai tiga perkara ini perintah Tuhan yang muncul adalah mengerjakan, sehingga redaksi yang digunakan Tuhan dalam al-Quran bukan ibtaghu, melainkan i-malu kerjakanlah, aminu berimanlah, dan athi-u taatlah atau kata-kata lain yang menjadi derivasinya. Jadi, kata ibtaghu carilah dalam ungkapan ibtaghu al-wasilata menjadi kata kunci dalam memahami perintah ini.
Dalam peristiwa spektakuler Isra-Miraj, selain unsur Jibril dan Muhammad, terdapat satu unsur lagi yang terlibat, yaitu Buraq, kendaraan para nabi. Dikatakan kendaraan ini disebut buraq karena warnanya yang maha putih, cahayanya yang maha terang, kecepatannya yang maha tinggi, dan segala sesuatu yang melekat pada buraq mirip dengan kilat semuanya diluar persepsi manusia. Kata buraq memang terambil dari barq kilat [Lisan al-Arab, X: 15]. Dalam riwayat yang berasal dari anas bin Malik r.a. disebutkan bahwa buraq itu lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada bagal (peranakan kuda jantan dan keledai betina) [Shahih al-Bukhari, II: 1173; Shahih Muslim, I: 145, 150].
Bahasa yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam menggambarkan karakteristik buraq sebagai kuda terbang adalah bahasa kias (majaz). Hal itu tampaknya memang disengaja oleh Nabi SAW agar bisa dipahami oleh akal umat sesuai dengan tingkat peradaban dan pengetahuan mereka ketika itu; dan bahasa semacam ini sangat sering digunakan oleh Beliau SAW dalam al-Hadis dan bahkan juga oleh Allah SWT dalam al-Quran. Dan Allah SWT tidak mengutus seorang rasul-pun kecuali dengan bahasa yang dipahami kaumnya agar ia bisa memberikan penjelasan yang terang.
"Dan tidaklah Kami mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya agar ia memberikan penjelasan yang terang," (Ibrahim, 14:4).
Benda tercepat yang dipahami bangsa Arab ketika itu adalah kuda untuk binatang darat dan burung untuk binatang udara, sehingga sangat wajar apabila Nabi SAW menggambarkan buraq sebagai binatang serupa kuda atau keledai yang bisa terbang sebagai perpaduan antara kecepatan kuda dan burung. Sejalan dengan perjalanan sang waktu, peradaban dan pengetahuan manusia berkembang dengan pesat. Dari penelitian-penelitian para ilmuwan berhasil diketahui bahwa benda yang memiliki kecepatan paling tinggi bukan lagi kuda atau burung; kecepatan itu dimiliki oleh cahaya. Dari buku-buku fisika diketahui bahwa kecepatan cahaya adalah 300.00 km/detik.
Andaikata Rasulullah SAW hidup dan mengalami Isra-Miraj pada abad ini, abad teknologi yang dengan berbagai jenis kendaraan super canggih, maka dapat dipastikan bahwa buraq yang dikendarai beliau dalam peristiwa spektakuler itu tidak akan digambarkan sebagai kuda terbang yang lebih cepat dari kuda atau burung, melainkan sebagai benda yang jauh lebih cepat daripada cahaya fisik, yang tiada lain adalah Cahaya Allah sendiri, Cahaya Metafisika Ketuhanan, yang hakikatnya hanya diketahui oleh Sang Pemilik.
Jadi, buraq adalah Cahaya (Nur) Tuhan, dan Cahaya (Nur) inilah yang disebut wasilah. Sebagaimana unsur Jibril, keberadaan unsur buraq mutlak diperlukan dalam menempuh perjalanan menuju Tuhan.
Lebih dari itu, amal saleh yang sering disebut-sebut dalam kasus tiga orang yang terjebak dalam goa, sebenarnya juga kurang tepat apabila disebut sebagai wasilah. Di sini perlu ditegaskan bahwa ketiga orang yang terjebak dalam goa itu sesungguhnya tidak berwasilah dengan amal saleh mereka. Mereka hanya memohon ganjaran kepada Allah atas amal saleh yang pernah mereka lakukan, dan ganjaran yang mereka minta adalah berupa pembebasan mereka dari jebakan batu yang menutup pintu goa itu.
Tidak seorang pun dari mereka yang mengatakan ad-uka bi (wasilati) amal (aku memohon kepada-Mu dengan (berwasilah pada) amalku); mereka hanya mengatakan:
"in kunta ta’lamu anni fa’altu dzalika ibtigha-a wajhika fafruj lana minha furjatan nara minhassama (jika Engkau mengetahui bahwa aku melakukan hal itu semata-mata karena mencari wajah-Mu, maka bukakanlah satu lobang yang darinya kami bisa melihat langit)" [Shahih al-Bukhari, II: 739; Shahih Muslim, IV: 2099; Shahih Ibni Hibban, III: 178-179-251-252].
Artinya, dengan menyebut amal saleh mereka, sesungguhnya mereka hanya memohon balasan untuk amal saleh itu, yaitu berupa dibukakannya pintu goa yang tersumbat batu tersebut [Fath al-Bari, VI: 510].
Demikian pula, pendapat bahwa al-Asma al-Husna (nama-nama Allah SWT yang paling indah) adalah wasilah atas dasar Firman Allah SWT dan Allah SWT memiliki nama-nama yang paling indah, maka serulah Dia dengan asma-asma itu [Al-A’raf, 7:180], juga kurang tepat, sebab nama-nama Allah yang dimaksud semuanya sudah jelas sehingga tidak perlu dicari lagi.
Bukankah yang diperintahkan Tuhan dalam ayat ke-35 surah al-Maidah itu adalah mencari wasilah yang diungkapkan dengan kata-kata wabtaghu ilayhil wasilata dan carilah wasilah (yang menyampaikan) kepada-Nya?
Lebih dari itu, terjemahan paling tepat dari ungkapan fad-uhu biha dalam ayat ke 180 surah al-Araf tersebut adalah maka serulah Dia dengan menyebut nama-nama itu, bukan maka bermohonlah kepada-Nya dengan (berwasilah dengan) nama-nama itu, sejalan dengan firman Allah lainnya yang berbunyi:
"Serulah Allah atau serulah al-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu menyeru (Tuhanmu), Dia mempunyai al-Asma’ al-Husna." (Al-Isra’, 17:110)
Diriwayatkan dari Ibn Abbas r.a. bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW sedang shalat di Mekah dan menyeru Tuhannya dengan "Ya Allah Ya Rahman atau Ya Rahman Ya Rahim." Mendengar hal ini, orang-orang Musyrik berkata, Lihatlah orang yang bersembunyi ini (Nabi saw); dia melarang kita menyembah dua tuhan, sementara dia sendiri menyeru dua Tuhan. Maka turunlah ayat 110 surat Al-isra’ (17):
"Serulah Allah atau serulah al-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu menyeru (Tuhanmu), Dia mempunyai al-Asma al-Husna." [Al-Durr al-Mantsur, V: 348; Zad al-Masir, V: 98; Tafsir al-Qurthubi, VII: 325; Fath al-Qadir, II: 268; Tafsir al-Thabari, XV: 182].
Kalbu Rasul sebagai Tempat Wasilah
Di dalam al-Quran, Allah SWT membuat perumpamaan tentang Cahaya (nur)-Nya yang diungkapkan dengan redaksi:
"Perumpamaan cahaya-Nya adalah seperti misykah lobang dinding yang tidak tembus sebagai tempat lampu yang didalamnya ada mishbah lampu dan mishbah itu ada di dalam Zujajah kaca." (Al-Nur, 24:35).
Menurut Ka’ab al-Ahbar dan Ibn Jarir r.a. yang dimaksud Nurihi alam ayat ini adalah Nuri Muhammad, Nur Muhammad [Tafsir al-Qurthubi, XII: 259]. Ketika ditanya oleh Ibn Abbas tentang ayat ini, lebih lanjut Ka’ab mengatakan:
"Ini adalah perumpamaan yang dibuat oleh Allah SWT untuk Nabi-Nya shallallahu ‘alayhi wasallam; al-misykah adalah dada (jasmani)-nya, al-Zujajah adalah kalbu (rohani)-nya, sedangkan al-mishbah adalah nubuwat." [Tafsir al-Bughawi, III: 346].
Komentar senada diungkapkan oleh Ibn Umar r.a. yang dikeluarkan oleh Imam al-Thabrani, Ibn ‘Adi, Ibn Mardawiyyah, dan Ibn. ‘Asakir:
"Al-misykah adalah rongga dada (jasmani) Muhammad saw, al-zujajah kalbu (rohani)-nya sedangkan al-mishbah adalah nur yang ada didalam kalbunya." [Majma al-Zawaid, VII:83; al-Mu’jam al-Awsath, II: 235; al-Mu’jam al-Kabir, XII: 317; Tafsir al-Qurthubi, XII: 263; Fath al-Qadir, IV: 36].
Cahaya (nur) yang ada dalam kalbu Nabi tersebut, atau yang biasa disebut dengan Nur Muhammad, termasuk didalamnya al-Quran yang juga disebut dengan Cahaya (nur) yang diturunkan kedalam kalbunya [Al-Nisa, 4: 174; Al-Baqarah, 2:97] merupakan cahaya Allah ada dibumi sebagai satu ujung sedangkan ujung yang lain ada disisi Allah sendiri. Hal ini ditegaskan dengan kelanjutan firman-Nya dalam ayat yang sama:
"Cahaya (Allah) di atas cahaya (Muhammad); Allah menuntun kepada cahaya-Nya orang yang dikehendaki."
Maksudnya adalah bahwa Cahaya Allah berhubungan langsung dengan Ccahaya Muhammad, karena pada hakikatnya Cahaya Allah dan Cahaya Muhammad adalah SATU, dan ditempat lain digambarkan sebagai tali Allah yang harus dipegangi kuat-kuat. Dalam kaitan ini Allah berfirman:
Dan berpeganglah secara teguh kepada tali Allah, dan janganlah bercerai-berai. (Ali Imran, 3: 103)
Ayat lain yang tampaknya juga penting dikemukakan disini untuk memahami keterkaitan Cahaya (Nur) Tuhan dengan kalbu orang mukmin sebagai singgasana nur itu, disamping keterkaitannya dengan hidayah, dzikir, dan perjalanan pulang menuju Tuhan adalah:
Barang siapa yang dilapangkan Allah dadanya untuk Islam, maka berada diatas Cahaya (Nur) Tuhannya; maka celakalah orang-orang yang berhati keras sehingga tidak berdzikir kepada Allah; mereka berada dalam kesesatan yang nyata. (Al-Zumar, 39:22)
Imam al-Qurthubi mengutip sebuah hadis yang berasal dari Ibn Mas’ud yang mengatakan bahwa para sahabat bertanya kepada Nabi saw tentang ayat itu, Bagaimana dada orang itu menjadi lapang? Rasulullah saw menjawab:
Jika Cahaya (Nur) itu masuk ke dalam kalbunya, maka ia menjadi lapang dan terbuka. Para sahabat masih bertanya, Apa tanda-tanda hal itu? Rasulullah saw menjawab: Melakukan perjalanan pulang ke negeri abadi (akhirat) dan meninggalkan negeri tipu daya (dunia) serta bersiap-siap menjemput kematian sebelum tiba saatnya [Tafsir al-Qurthubi (Al-Jami’ li Ahkam al-Quran), XV: 247].
Dari informasi di atas semakin jelas bahwa Cahaya (Nur) Allah SWT bersemayam di dalam kalbu orang yang dikehendaki lapang dadanya oleh Allah SWT; dan karena kondisi orang semacam ini dioposisikan dengan orang yang berhati keras sehingga tidak berdzikir kepada Allah SWT, maka berarti bahwa orang yang didalam kalbunya terdapat Cahaya (Nur) Allah SWT tiada lain adalah ahli dzikir, orang yang tidak pernah lepas dari berdzikir kepada Allah SWT. Tidak seorang pun yang mendapat gelar sebagai ahli dzikir kecuali Nabi SAW sendiri dan hamba-hamba Allah SWT yang oleh beliau disebut sebagai mafatih al-dzikr kunci-kunci dzikir; mereka adalah wali-wali Allah yang apabila mereka dilihat orang maka orang (yang melihat) itu langsung berdzikir juga. Mereka itulah para ‘ulama yang disebut sebagai waratsah al-anbiya ahli waris para nabi, yang kepada mereka Allah mewariskan Al-Quran, sehingga di kalbu mereka itulah wasilah atau Nur Tuhan bersemayam.
Mencari dan melihat mereka adalah kewajiban yang diperintahkan Allah kepada orang-orang yang beriman. Menemukan mereka berarti menemukan wasilah. Dengan wasilah, mereka akan dapat berhubungan langsung dengan Allah serta memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari-Nya, sebagaimana bumi berhubungan langsung dengan matahari melalui cahayanya sehingga memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari matahari itu sendiri Rabithah (Merabit)
Unsur lain yang juga sangat fundamental dalam thariqah sebagai jalan menuju Tuhan dan sekaligus sebagai teknik berdzikir efektif adalah rabithah al-mursyid (merabit mursyid) yang dalam istilah Imam al-Munawi disebut dengan shuhbat al-mursyid bersahabat dengan mursyid, yaitu ketika ia menyinggung cara pencapaian akhlak yang terpuji dalam al-Faydh al-Qadir-nya:
Cara memperoleh akhlak yang terpuji adalah dengan memperbanyak dzikir sambil bersahabat dengan mursyid yang sempurna [Faydh al-Qadir, III: 467].
Bersahabat dengan mursyid melahirkan akhlak yang agung, menyemaikan kesadaran keagamaan yang benar, dan membangkitkan glora cinta ilahi yang tersalur dari kalbu mursyid ke dalam kalbu murid. Bersahabat dengan mursyid yang sempurna adalah langkah awal yang harus ditempuh dalam perjalanan menuju Tuhan. Perjalanan ini sekaligus menjadi sarana diagnosa dan terapi terhadap penyakit-penyakit yang dijangkitkan oleh virus paling ganas bernama iblis.
Dalam setiap kalbu terdapat apa yang disebut hazhzh al-syaithan bagian setan, dan bagian inilah yang diambil Jibril dari kalbu Nabi Muhammad SAW pada saat Beliau SAW berusia empat atau lima tahun dan pada saat menjelang keberangkatan beliau dalam perjalanan malam menuju Tuhan [Shahih Muslim, I: 147; Shahih Ibn Hibban, XIV: 242; al-Mustadrak, II: 575; Musnad Ahmad, III: 149, 288; Musnad Abi Ya’la,VI: 108, 224; Musnad Abi Awanah, I: 113, 125].
Pengertian Rabithah (Merabit)
Dari segi bahasa makna rabithah adalah hubungan atau ikatan; terambil dari kata rabth yang berarti mengikat atau menghubungkan; [Al-Munawir Qamus ‘Arabi-Indunisi, hlm 501]; Ungkapan rabithah al-mursyid, dengan demikian, menunjukan kepada makna menghubungkan diri dengan mursyid atau merabit dengan mursyid.
Di dalam al-Quran perintah melakukan rabithah diungkapkan melalui firman Tuhan:
Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu, serta merabitlah dan bertakwalah, agar kamu memperoleh kemenangan. (Ali Imran, 3: 200).
Kata rabithu dalam ayat tersebut menurut Ibn Manzhur dalam Lisan al-Arab-nya bermakna hafizhu atau lazimu berkekalan/terus-menerus, yaitu al-muwazhabah ‘ala al-amr berkekalan/ terus-menerus melakukan sesuatu. Asal makna rabithu (ribath atau murabathah) adalah al-iqamah ‘ala jihad al-‘aduw (melakukan perang terhadap musuh) [Lisan al-Arab, VII: 303].
Pemahaman ideal mengenai maksud kata rabithu (ribath atau murabathah) dalam firman Allah tersebut, dengan menyimak makna-makna yang terkait dengan kata itu sendiri, muncul dalam thariqah, yaitu berkekalan/terus-menerus menghubungkan diri secara rohani dengan mursyid dalam rangka memerangi iblis sebagai musuh manusia yang paling nyata. Tidak ada musuh yang paling layak untuk selalu diwaspadai dan diperangi kecuali iblis la’natullah yang memang berusaha terus menghancurkan manusia.
Lebih jauh dapat dikatakan bahwa rabithah al-mursyid (merabit mursyid) pada dasarnya adalah berjamaah secara rohani dengan mursyid, yaitu imam-berimam dalam khafilah rohani Rasulullah SAW. Menunjuk kepada pengertian inilah Imam Ja’far al-Shadiq, tokoh sufi dari kalangan ahli bait Nabi SAW, yang dikutip oleh Abu Nu’aim al-Ishfahani dalam ensiklopedia orang-orang suci–nya yang berjudul Hilyat al-Awliya mengatakan:
Barangsiapa menjalani hidup dengan bergabung dalam batin (rohani) Rasul, maka dialah yang disebut orang sufi [Hilyat al-Awliya’, I: 20].
Di samping itu, dapat pula dikatakan bahwa rabithah al-mursyid (merabit mursyid) menunjuk kepada makna melibatkan Rasul SAW dalam setiap munajat dan ibadah agar munajat dan ibadah itu dapat langsung mendapat sambutan dari Allah sebagaimana yang diisyaratkan oleh firman Allah:
Andaikata mereka ketika menzalimi diri mereka datang kepadamu (Muhammad), kemudian mereka memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohon ampun untuk mereka, niscaya mereka mendapati bahwa Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. (Al-Nisa’, 4: 64).
Melibatkan Rasul SAW atau merabit mursyid dalam ibadah dapat disimak pula dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan imam-imam hadis lainnya disebutkan bahwa ketika Umar meminta izin kepada Nabi saw untuk menunaikan ibadah umrah, Nabi SAW bersabda:
"Wahai saudara mudaku, serikatkan (libatkan) kami dalam doamu dan jangan lupakan kami [Sunan al-Tirmidzi, V: 559; Musnad Ahmad, II: 59; Sunan Ibn Majah, II: 966].
Dalam kasus yang berbeda, melibatkan Rasul SAW atau merabit mursyid dapat disimak dari kisah Umar ibn al-Khaththab r.a. yang melibatkan Paman Nabi SAW yang bernama Abbas ra. ketika ia berdoa memohon hujan:
"Ya Allah, dulu kami bertawassul kepada-Mu dengan nabi-Mu, lalu engkau memberi kami hujan. Sekarang, kami bertawassul kepada-Mu dengan paman nabi-Mu, maka berilah kami hujan. Mereka pun kata sang perawi hadis diberi hujan oleh Allah [Shahih al-Bukhari, I: 342, III: 1360; Shahih Ibn Hibban, VII: 110- 111 dan Sunan al-Baihaqii al-Kubra, III: 352, al-Mu’jam al-Kabir, I: 72].
Artinya, Umar melibatkan ‘Abbas ra. sebagai pengganti Rasul SAW untuk mendapatkan karunia Allah SWT berupa hujan. Dengan melibatkan ‘Abbas ra. sesungguhnya Umar ra . hendak bergabung dalam khafilah rohani Rasul SAW melalui orang yang masih hidup dan yang dicintai Rasul SAW meskipun Umar ra. sendiri memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Rasul SAW.
Berdasarkan hal ini, maka orang-orang mukmin lainnya, apalagi yang hidup pada masa sekarang, sudah seyogianya mencari seorang hamba Allah SWT yang karena kecintaan dan ketaatannya kepada Allah SWT dan Rasul-Nya SAW layak dicintai oleh Allah SWT dan Rasul-Nya SAW dan layak pula menduduki posisi sebagai khalifah pengganti Rasul SAW.
Teknik Melakukan Rabithah
Di dalam shalat, ketika melakukan tasyahud, kita diperintahkan mengucapkan salam kepada Nabi SAW, Assalamu’alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh (salam dan rahmat serta barakah Allah untukmu wahai Nabi SAW). Perintah ini harus dilakukan secara lahir dan batin, secara lahir dengan mengucapkan salam itu sendiri, sedangkan secara batin adalah menghubungkan rohani kita dengan rohani Rasul SAW, agar kita bisa bersama dengan Beliau SAW.
Bersama dengan Rasul SAW sekaligus mengandung makna bersama dengan Allah SWT karena Rasul SAW tidak pernah berpisah sedetik-pun dari-Nya. Kenyataan bahwa di dalam rohani Beliau SAW tersimpan Nur Allah SWT, dan bahwa Beliau SAW sebagaimana ditegaskan oleh Aisyah ra. selalu berdzikir kepada Allah SWT dalam setiap detik yang Beliau SAW miliki (kana yadzkurullaha fi kulli ahyanihi) [Musnad Abi Ya’la, VIII: 355] merupakan indikasi nyata atas makna ini.
Dalam kaitan inilah mengapa sebagian Kaum Arifin yaitu orang-orang yang sudah mengenal Allah SWT secara tahkik berkata:
"Bersamalah engkau selalu dengan Allah, dan jika engkau belum bisa, maka bersamalah engkau selalu dengan orang yang sudah bersama dengan Allah" [Tanwir al-Qulub, hal. 512].
Namun begitu, karena kita tidak mengenal Rasul SAW secara jasmani, maka yang dapat kita lakukan adalah menghubungkan rohani kita dengan rohani ulama yang kita kenal secara jasmani, yaitu ulama yang benar-benar berkapasitas sebagai Waratsah al-Anbiya (Ahli Waris Para Nabi), yang kepada mereka beliau mewariskan isi rohani beliau dengan izin Allah SWT.
Hamba-hamba Allah SWT seperti itu dalam al-Quran disebut antara lain dengan al-Shadiqun, dan Allah memerintahkan kita agar selalu bersama dengan mereka (secara jasmani dan rohani).
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu selalu bersama orang-orang yang benar. (Q.S. al-Taubah, 9: 119).
Firman Allah di atas dijelaskan oleh Imam al-Baidhawi dalam Tafsir-nya dengan ungkapan:
"(Hendaklah kamu bersama dengan mereka) dalam keimanan dan janji-janji mereka, atau dalam agama Allah dari segi niat, perkataan, dan perbuatan." [Tafsir al-Baydhawi, III: 178].
Penjelasan senada dikemukakan oleh Imam al-Alusi dalam Ruh al-Maani-nya [Ruh al-Ma’ani, XI: 45], dan juga oleh Imam Abu Saud dalam Tafsir-nya Irsyad al-Aql al-Salim ila Mazaya al-Quran al-Karim dengan redaksi yang lebih gamblang:
"(Hendaklah kamu bersama dengan mereka) dalam keimanan dan janji-janji mereka, atau dalam agama Allah dari segi niat, perkataan, dan perbuatan, atau dalam semua urusan." [Tafsir Abi al-Sa’ud,IV: 110].
Artinya, bersama atau berjamaah dengan orang-orang yang benar itu dilakukan dalam semua keadaan dan dalam semua persoalan, baik secara jasmani maupun secara rohani.
Bahkan, bersama atau berjamaah secara rohani jauh lebih mungkin direalisasikan daripada berjamaah secara jasmani, sebab tidak mungkin kita dapat berjamaah dengan mereka secara jasmani dalam semua keadaan. Maka al-Shadiqun yaitu orang-orang yang benar, dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang benar dalam keimanan mereka kepada Allah, sehingga sebutan lain yang dikemukakan al-Quran untuk mereka adalah al-Muminuna Haqqan, orang-orang mukmin sejati (hak), yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah SWT, hati mereka bergetar dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah SWT kepada mereka keimanan mereka semakin bertambah, dan hanya kepada Allah SWT mereka bertawakal, menegakkan shalat dan menginfakkan sebagian harta yang dikaruniakan kepada mereka [Al-Anfal, 8: 3-5]; bukan orang-orang yang beriman tetapi di dalam hatinya tumbuh subur sifat-sifat nifaq (munafik) yang diantara ciri-ciri utama mereka adalah bahwa mereka tidak berdzikir kepada Allah kecuali sedikit [Al-Nisa, 4: 142].
Mereka tiada lain adalah wali-wali Allah yang oleh Nabi sebagaimana disinggung sebelumnya disebut dengan Mafatih al-Dzikr ‘kunci-kunci dzikir’, dan yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan kaum sufi, dan oleh Ibn Taimiyah disebut sebagai golongan yang paling baik setelah Nabi. [Majmu’ al-Fatawa, XI: 17]. Memandang mereka melahirkan dzikir kata Nabi dalam riwayat Imam al-Thabrani ketika menggambarkan keberadaan mereka [Al-Mu’jam al-Kabir, X: 205]. Memandang mereka, terutama yang dilakukan secara rohani, mewujudkan apa yang dimaksud dengan rabithah di sini.
Rabithah sebagai Penghalau Iblis
Melakukan rabithah pada dasarnya dimaksudkan sebagai realisasi atas perintah berjamaah yang dalam nash diungkapkan dengan berbagai redaksi. Imam al-Bukhari dalam al-Tarikh al-Kabir-nya mengutip sebuah hadis Nabi saw, Kalian harus berjamaah [al-Tarikh al-Kabir, VIII: 447], sementara Imam Ahmad dalam Musnad-nya meriwayatkan sebuah hadis bahwa Nabi saw. bersabda:
Wahai manusia, kalian harus berjamaah dan hindarilah bercerai-berai [Musnad Ahmad, V: 370].
Imam al-Tirmidzi dan al-Nasai meriwayatkan dari Ibn Umar bahwa Umar berkhotbah menyampaikan sabda-sabda Nabi yang di dalamnya antara lain beliau bersabda:
Kalian harus berjamaah dan hindarilah bercerai (dari jamaah), karena setan bersama orang yang sendirian [Sunan al-Tirmidzi, IV: 465; al-Sunan al-Kubra, V: 388].
Dalam riwayat Imam al-Baihaqi hadis tersebut diungkapkan dengan redaksi:
Kalian harus berjamaah, karena tangan Allah ada di atas jamaah dan setan bersama orang yang sendirian [Syu’ab al-Iman, VII: 488]
Imam Abu al-Hujjaj al-Mazzi dalam Tahdzib al-Kamal mengutip ungkapan Ibn Mas’ud yang disampaikan oleh Amr ibn Maimun dengan redaksi:
Kalian harus berjamaah, karena sesungguhnya tangan Allah ada di atas jamaah dan Dia sangat menyukai jamaah [Tahdzib al-Kamal, XXII: 264].
Hadis-hadis di atas semuanya mengisyaratkan pentingnya berjamaah sebagai ajaran agama yang sangat fundamental, baik dalam urusan ibadah maupun dalam urusan muamalah, baik secara jasmani maupun secara rohani.
Dalam shalat kita dianjurkan berjamaah; bahkan setengah ulama menghukumi shalat berjamaah itu wajib berdasarkan hadis-hadis Nabi yang antara lain mengancam akan membakar rumah-rumah penduduk yang dekat dengan mesjid tetapi penghuninya tidak mau shalat berjamaah [Shahih Muslim, I: 451; Syarh al-Nawawi ‘ala Shahih Muslim, V: 153].
Tujuan paling pokok dari berjamaah adalah melindungi diri dari gangguan iblis yang selalu mencari celah untuk memalingkan manusia dari kebenaran menuju kesesatan, dan mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan.
Kalau yang dimaksud berjamaah hanya semata-mata berjamaah secara jasmani, maka efektivitas perlindungan diri tidak akan tercapai secara maksimal, sebab yang menjadi sarang iblis adalah kalbu manusia, sehingga kalbu pun harus dikondisikan agar juga berjamaah, yaitu dengan melakukan rabithah (merabit mursyid).
Rabithah yang dilakukan secara berkesinambungan melahirkan berbagai fenomena positif sebagai karunia Tuhan yang jenisnya bergantung kepada kehendak-Nya, antara lain yang paling utama adalah mengalami atau merasakan kahadiran Tuhan. Apa yang dialami Nabi Yusuf as. ketika nyaris terjerumus dalam kemesuman merupakan salah satu indikasi atas kenyataan ini.
Di dalam al-Quran diceritakan bahwa Yusuf sudah nyaris melakukan perbuatan mesum bersama Zulaikha andaikata ia tidak melihat dan mengalami bukti Tuhannya. Ibn Abbas r.a. menjelaskan, yang dikutip oleh Imam al-Thabari dalam Tafsir-nya, bahwa ungkapan andaikata Yusuf tidak melihat bukti Tuhannya dalam surahYusuf ayat ke-24 tersebut adalah andaikata ia tidak melihat bayangan bentuk wajah ayahnya [Tafsir al-Thabari,XII: 186]. Dari penjelasan Ibn Abbas ini semakin jelas bahwa Yusuf mengalami rabithah secara otomatis dengan izin Allah.
Dalam hal berdzikir kepada Allah khususnya, melakukan rabithah merupakan keharusan, karena jalan yang ditempuh dalam berdzikir adalah jalan rohani yang sangat halus dan penuh dengan ranjau-ranjau iblis yang selalu berusaha memalingkannya dari jalan Allah untuk kemudian menjerumuskannya ke dalam kesesatan.
Dalam kaitan inilah Imam al-Nawawi al-Jawi menegaskan dalam kitabnya Nihayah al-Zayn, Orang yang berdzikir wajib mengikuti salah seorang Imam dari Imam-imam Tasawuf [Nihayah al-Zayn (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.) hlm. 7].
Suluk
Asas pertama tarekat adalah al-iradah, yaitu kehendak atau kemauan bulat untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan menapaki jalan-jalan (menujuNya) secara sungguh-sugguh sedemikan rupa sehingga yang bersangkutan benar-benar mengalami dan merasakan (kehadiran) Tuhan (Rukun Ihsan: Seolah-olah beribadah melihat Allah apabila tidak maka sadirilah bahwa Allah melihatnya). Perintah Tuhan mengenai hal ini sangat jelas ketika berfirman:
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan carilah wasilah, serta bersungguh-sungguhlah menapaki jalan-jalan (menuju kepada)-Nya agar kamu memperoleh kemenangan/kesuksesan. (Al-Maidah, 5:35).
Sebenarnya tidak hanya manusia yang diperintahkan Tuhan untuk menapaki jalan-jalan-Nya lebah-pun bahkan menjadi objek yang di-khitab Tuhan dengan perintah yang sama melalui wahyu yang disampaikan kepadanya, Maka tempuhlah jalan-jalan Tuhan -Mu yang telah dimudahkan untukmu [Al-Nahl, 16: 69]. Dalam kasus lebah ini terdapat tanda ketuhanan yang layak direnungkan oleh murid (orang yang berkehendak bulat bertemu dengan Tuhan). Perjalanan menuju Tuhan tidak mungkin dapat dilakukan, dan jalan-jalan menuju Tuhan pun tidak akan pernah tersingkap, kecuali dengan mujahadah (perjuangan yang sungguh-sungguh) yang dimotori oleh iradah tersebut. Hal ini ditegaskan Tuhan dalam sebuah firman-Nya:
Dan orang-orang yang ber-mujahadah di dalam Kami, kepada mereka Kami benar-benar menunjukkan jalan-jalan menuju Kami; sesungguhnya Allah benar-benar bersama dengan orang yang mengalami ihsan (beribadah seolah-olah melihat Allah). (Al-Ankabut, 29:69).
Dalam wacana sufi perjalanan dalam menempuh jalan-jalan menuju Tuhan disebut dengan suluk dan orang yang melakukan perjalanan disebut salik.
Di dalam suluk para salik menyibukan diri dengan riyadhah (latihan kejiwaan) dalam rangka pendekatan diri kepada Allah (al-taqarrub ilallah) melalui pengamalan ibadah-ibadah faraidh (wajib) dan nawafil (sunnah); semua aktivitas ini dilakukan diatas fondasi dzikrullah, di samping dzikrullah itu sendiri dijadikan sebagai amalan yang berdiri sendiri, lepas dari ibadah-ibadah lainnya, sebagai wujud konkret pengamalan firman Allah dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dan Muslim:
Aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku kepada-Ku, dan Aku bersamanya ketika ia berdzikir kepada-Ku; jika ia berdzikir kepada-Ku dalam dirinya,maka Aku berdzikir kepadanya dalam diri-Ku; jika ia berdzikir kepada-Ku dalam suatu kelompok, maka Aku berdzikir kepadanya dalam kelompok yang lebih baik daripada mereka. Jika ia mendekat kepada-Ku sejengkal, maka Aku mendekat kepadanya sehasta; jika ia mendekat kepada-Ku sehasta; maka Aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia mendatangi-Ku dalam keadaan berjalan, maka Aku mendatanginya dalam keadaan berlari [Shahih al-Bukhari, VI: 2694; Shahih Muslim, IV: 2061].
Intinya semua sunnah Nabi sebagai model al-Quran yang hidup, nyata, dan sempurna, yang dalam bahasa Aisyah diungkapkan dengan redaksi akhlak Nabi adalah al-Quran [Musnad Ahmad, VI: 91; Al-Mu'jam al-Awsath, I: 30], diwujudkan secara konkret dan sungguh-sungguh dalam suluk. Berkekalan dalam wudhu, berdzikir dalam setiap keadaan (berdiri, duduk dan berbaring), berjamaah dalam semua salat wajib, menjaga moderasi antara lapar dan kenyang, menghiasi waktu malam dengan berbagai ibadah dan salat sunah, mengosongkan kalbu dari selain Allah, mengarahkan segenap konsentrasi dan perhatian sebagian contoh sunnah Nabi yang dipraktekkan dalam suluk.
Suluk sekaligus, merupakan jalan menuntut ilmu dan marifah yang dengannya Allah melempangkan jalan menuju sorga yang notabene jalan menuju Allah sendiri karena sorga tidak ada kecuali di sisi Allah. Sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, Muslim, dan imam-imam hadis lainnya, mendukung kenyataan ini:
Barangsiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah memudahkan baginya jalan menuju sorga [Shahih al-Bukhari, I: 37; Shahih Muslim, IV: 2074; Musnad Ahmad, II: 325].
Suluk dalam Pandangan Ibn Taimiyah
Ibn Taimiyah yang selama ini dituding sebagai anti thariqah ternyata justru sangat mendukung suluk sebagai unsur fundamental dalam thariqah. Dalam kaitan ini beliau menegaskan dalam Majmu' al-Fatawa-nya:
Suluk adalah menempuh jalan yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya berupa realisasi akidah, ibadah, akhlak.
Semua ini sangat jelas dalam ibadah al-Quran dan al-Sunnah, karena suluk menempati posisi makanan yang merupakan keharusan bagi orang mukmin. Oleh karena itu, semua sahabat mengenal suluk dengan petunjuk al-Quran dan al-Sunnah dan sekaligus dari penyampaian Rasul sendiri; mereka dalam hal itu tidak membutuhkan ahli-ahli fikih dari kalangan sahabat, dan mereka pun dalam hal itu tidak pernah saling bertentangan satu sama lain, sebagaimana mereka saling bertentangan dalam kasus-kasus fikih yang pengetahuan tentang kasus-kasus ini tertutup bagi kebanyakan sahabat, sehingga mereka berbicara dalam fatwa-fatwa yang diminta oleh suatu kelompok dalam kasus-kasus itu.
Adapun (suluk) yang dilakukan oleh orang yang hendak mendekatkan diri kepada Allah dengan mengintensifkan ibadah yang diwajibkan dan ibadah yang disunnahkan, maka masing-masing dari mereka berpedoman kepada al-Quran dan al-Sunnah, karena al-Quran dan al-Hadis sarat dengan hal ini. Dan jika salah seorang dari mereka dalam hal itu berbicara dengan perkataan yang tidak ia sandarkan kepada dirinya sendiri, maka perkataan itu atau maknanya disandarkan kepada Allah dan Rasul-Nya; kadang-kadang di antara mereka ada yang mengucapkan kata-kata hikmah, dan hal itu ternyata berasal dari Nabi saw sendiri; ini sama dengan kata-kata hikmah, yang dikatakan orang dalam menafsirkan firman Allah nurun 'ala nurin 'cahaya di atas cahaya' [Majmu' al-Fatawa, XIX: 273].
Lebih jauh Ibn Taimiyah menegaskan bahwa masalah suluk merupakan bagian dari masalah akidah yang semuanya ditetapkan dalam al-Quran dan al-Sunnah sehingga tidak layak dipertentangkan:
Masalah suluk merupakan salah satu jenis masalah akidah; semuanya ditetapkan dalam al-Quran dan al-Sunnah...Mereka (para sahabat) tidak pernah saling bertentangan dalam masalah akidah dan tidak pula dalam masalah thariqah 'jalan' menuju Allah yang dengannya seseorang dapat menjadi salah seorang wali dari wali wali Allah yang abrar 'bebas dari noda durhaka' dan muqarrabin' didekatkan kepada Allah'. Oleh karena itu, syekh-syekh tarekat sufi jika mereka memerlukan rujukan dalam perkara-perkara syariat seperti yang berkenaan dengan nikah, warisan, bersuci, sujud sahwi, dan yang semacamnya, mereka mengikuti (taklid) ahli-ahli fikih...berijtihad; dan barangsiapa di antara mereka mengikuti Rasul, maka ia benar; dan barangsiapa menyimpang dari Rasul, maka ia salah [Majmu' al-Fatawa XIX: 274].
Jadi, dalam pandangan Ibn Taimiyah, sebuah pandangan yang sangat ideal, suluk merupakan masalah akidah sehingga tidak dapat didekati dengan pendekatan fikih, atau merupakan realisasi konkret dari tasawuf yang oleh Imam Muhammad Ibn Ahmad bin Jazi al-Kalabi al-Gharnathi disebut sebagai fikih batin [al-Qawanin al-Fiqhiyyah li Ibn Jazi, hal. 277].
Hal-hal yang berkenaan dengan suluk semuanya didasarkan pada al-Quran dan al-Sunnah. Khalwat Nabi saw di Gua Hira', khususnya, menjadi rujukan utama bagi para salik sebagaimana ditegaskan juga oleh Buya Hamka ketika ia mengatakan:
Maka kaum Shufiyah yang mensucikan dirinya dalam khalwatnya itu, pun mengambillah contoh teladan atas amal-amal mereka dalam khalwat, suluk dan tariqat, dan bermacam-macam sistem yang lain: khalawat dan tahannust Nabi di Gua Hira', sampai terbuka hijab kegaiban oleh kemurnian jiwa [Tasauf, Perkembangan dan Pemurniannya, hlm. 23].
Melalui suluk yang memenuhi syarat dan rukunnya seseorang dengan izin Tuhannya akan mencapai tauhid yang murni atau mengalami Tuhan secara haqq al-yaqin 'keyakinan yang hak yang tidak bercampur dengan keraguan sedikit pun', sehingga tidak lagi memerlukan argumentasi-argumentasi logis mengenai keberadaan dan keesaan-Nya; ia sudah mendapatkan pancaran cahaya langsung dari Tuhan sehingga ia pun berjalan di muka bumi bagaikan pelita yang menerangi sekelilingnya. Pelita mereka berasal dari nurun 'ala nurin 'cahaya di atas cahaya', yang oleh Ibn al-Qayyin sambil mengutip firman Tuhan dalam ayat ke 35 dari surah al-Nur digambarkan dengan ungkapan:
Lampu-lampu seseorang yang 'mengalami' Tuhan secara tahkik (muwahhid) dan yang berjalan (salik) di atas jalan dan thariqah Rasul menyala dan bersinar dari pohon yang diberkati, pohon zaitun yang tidak tumbuh di Timur dan tidak pula di Barat; yang minyaknya sudah hampir bisa menerangi tidak disentuh api; nurun 'ala nurin 'cahaya di atas cahaya'; Allah membimbing kepada cahaya-Nya orang-orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia [Madarij al-Salikin, III: 98].
Suluk, Realisasi Khalwat, 'Uzlah dan I'tikaf
Dalam tarekat sufi suluk dipahami dan diwujudkan dalam bentuk khalwat dan 'uzlah, yaitu mengasingkan diri selama jangka waktu tertentu (10, 20, atau 40 hari) di sebuah tempat yang bebas dari kebisingan dan hiruk pikuk duniawi.
Teladan yang diambil oleh para salik dalam hal ini seperti ditegaskan Buya Hamka adalah kegemaran Nabi melakukan khalwat dan tahannuts di Gua Hira'. Imam al-Bukhari dan Muslim serta beberapa imam hadis lainnya meriwayatkan sebuah hadis bahwa umm al-mu'min Aisyah berkata:
Nabi digemarkan oleh Allah untuk melakukan khalwat, beliau selalu berkhalwat di Gua Hira' dan melakukan tahannuts di sana, yaitu beribadah selama beberapa malam tertentu [Shahih al-Bukhari, I: 4; Shahih Muslim, I: 140; Shahih Ibn Hibban, I: 216; Musnad Ahmad, VI: 232].
Para sufi melakukan suluk di masjid-masjid atau surau-surau yang oleh al-Quran disebut sebagai rumah-rumah yang diizinkan Allah untuk dimuliakan dan dijadikan tempat berdzikir menyebut asma-Nya [Al-Nur, 24:36]. Rumah-rumah semacam inilah yang oleh para salik dijadikan tempat khalwat dan 'uzlah; mereka menetap disitu selama beberapa hari untuk melakukan ibadah dan dzikir secara intensif. Dengan demikian, tidak mengherankan apabila suluk mereka disebut juga dengan I'tikaf yang dari segi bahasa bermakna berdiam di sebuah tempat selama jangka waktu tertentu.
Dalam kasus ini para salik merujuk kepada I'tikaf Nabi SAW selama sepuluh hari dalam bulan Ramadhan. Dalam Shahih al-Bukhari disebutkan bahwa 'Aisyah ra. berkata:
Nabi SAW selalu I'tikaf selama sepuluh hari terakhir dari bulan bulan Ramadhan sampai Allah mewafatkan beliau [Shahih al-Bukhari, II: 213; Shahih Muslim, II: 831].
Namun begitu, sebagaimana diceritakan oleh Abu Dzar al-Ghiffari, tidak jarang pula Nabi melakukan I'tikaf sepuluh hari pertama dan kadang-kadang sepuluh hari ke dua atau pertengahan dari bulan Ramadhan [Shahih al-Bukhari, II: 713; Shahih Muslim, II: 825].
Dan satu yang barangkali penting digarisbawahi di sini adalah bahwa I'tikaf pada dasarnya merupakan ibadah tersendiri; artinya tidak harus terkait dengan keharusan berpuasa dan tidak harus pula terkait dengan bulan Ramadhan. Imam al-Hakim dan al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibn. Abbas bahwa Nabi SAW bersabda:
Tidak ada keharusan berpuasa atas orang yang beri'tikaf kecuali ia menetapkan puasa itu untuk dirinya sendiri [Al-Mustadrak, I: 605; Sunan al-Baihaqi al-Kubra, IV: 318; Sunan Daruquthi, II: 199]. Imam al-Baihaqi dan beberapa Imam hadis lainnya meriwayatkan dari Aisyah ra. bahwa ia berkata:
Nabi SAW pernah melakukan I'tikaf selama sepuluh hari pertama bulan syawal [Sunan al-Baihaqi al-Kubra, IV: 318; Sunan Abi Dawud, II: 331; al-Sunan al-Kubra, II: 260].
Ibn al-Qayyim mengutip pendapat ulama yang mendukung keabsahan I'tikaf sebagai ibadah yang mandiri ketika ia mengatakan:
I'tikaf merupakan ibadah yang berdiri sendiri, sehingga puasa tidak menjadi syarat dalam I'tikaf sebagaimana halnya ibadah-ibadah lainnya seperti haji, salat, jihad dan ribath (merabit); I'tikaf adalah menetap di suatu tempat tertentu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, sehingga puasa tidak menjadi syarat dalam I'tikaf sebagaimana halnya ribath (merabit); dan I'tifaf merupakan qurbah (pendekatan diri kepada Allah) itu sendiri sehingga puasa tidak menjadi syarat dalam I'tikaf sebagaimana halnya haji [Hasyiyah Ibn al-Qayyim, VII: 106].
Satu hal yang pasti adalah bahwa suluk yang dilakukan dengan ikhlas semata-mata mencari ridha Allah SWT akan melahirkan manusia baru yang dari dalam hatinya memancar mata air dan sumber-sumber hikmah yang kemudian mengalir pada lisannya sebagaimana ditegaskan oleh Nabi SAW dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah:
Tidaklah seorang hamba mengikhlaskan dirinya selama empat puluh pagi (hari) kecuali dari kalbunya memancar sumber-sumber hikmah yang mengalir pada lisannya [Mushannaf Ibn Abi Syaibah, VII: 80; Musnad al-Syihab, I: 285].